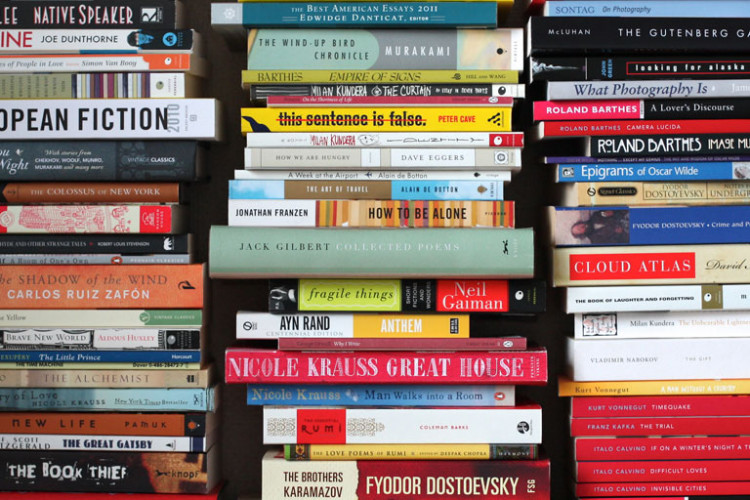Gentrifikasi & Toko Rekaman Fisik
Melihat Lebih Jauh Pada Fenomena Record Store Day

Setiap tahun para penggemar rilisan fisik merayakan antusiasmenya di Record Store Day. Pada hajatan yang pertama dimulai sejak 2007 ini setiap band dan label rekaman berlomba-lomba merilis karya dalam bentuk fisik baik itu berupa CD, kaset, dan piringan hitam. Setiap tahun hajatan ini selalu bertambah ramai, setidaknya di Indonesia. Tahun ini saja Record Store Day diselenggarakan hampir di 20 kota di Indonesia. Tersebar mulai dari Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Kalimantan Timur, dan masih banyak lagi. Kalau melihat antusiasme se-ramai ini, kadang saya tidak habis pikir untuk mempertanyakan apakah benar konsumsi musik orang-orang sudah melupakan rilisan fisik dan beralih pada musik digital (streaming /download)?
Akhir tahun lalu, sejumlah toko rekaman besar seperti Duta Suara dan Disc Tarra yang selama ini menjadi rantai distribusi album rekaman menyatakan diri bubar dan menutup semua gerainya di seantero Indonesia. Fenomena ini menyusul kasus yang sama ketika toko rekaman legendaris Aquarius mengalami nasib serupa beberapa tahun sebelumnya. Toko rekaman merupakan figur penting dalam konteks ekosistem musik sebuah kota. Kita bisa menemukannya di berbagai tempat: berada di pinggiran jalan, sebuah ruko, hingga di kawasan perbelanjaan (mall). Namun, beberapa tahun terakhir senjakala toko rekaman ini menyebabkan fenomena distribusi musik tak melulu harus berada di toko rekaman. Kehadiran media sosial, terutama Facebook dan Instagram, menjadi jalur distribusi baru. Beberapa toko rekaman pun lebih memanfaatkan media baru tersebut. Bahkan distribusi album rekaman sekarang ramai melalui gerai restoran cepat saji. Dari fenomena tersebut, apakah masih relevan kemudian akan hadirnya toko rekaman fisik di sebuah kota?
Dari beberapa wawancara yang saya baca mengenai fenomena ini banyak yang menyalahkan maraknya pembajakan hingga perubahan konsumsi ke musik digital (streaming /download) sebagai penyebab utama kemunduran toko rekaman di berbagai kota. Tak banyak sebenarnya yang melihat fenomena ini sebagai sebuah persoalan kota seperti gentrifikasi yang marak terjadi di kota-kota besar. Gentrifikasi seringkali diartikan naiknya nilai suatu lahan karena investasi lahan tersebut harganya kian melonjak. Seperti yang saya lihat dalam film Last Shop Standing: The Rise, Fall, and Rebirth of the Independent Records Shop (2009) yang disutradarai oleh Graham Jones ini menyoroti tutupnya sekitar 2000 toko rekaman di Inggris karena beberapa faktor mulai dari teknologi digital, maraknya supermarket besar (semacam HMV atau Tesco), namun yang paling menarik ketika pajak yang juga ikutan naik dan berpengaruh besar terhadap keberadaan toko-toko rekaman ini. Seperti yang ditulis oleh situs thevinylfactory, gentrifikasi ini berpengaruh cukup besar membuat sejumlah toko rekaman di Inggris satu per satu hilang. Seperti yang diutarakan oleh Alain de la Mata, pemilik toko rekaman Intoxica Records yang bubar pada 2012 lalu: “They proposed one, we said yes. They proposed a second one, we said yes again. When they came back with a third proposal, though, it involved an unlimited service charge. Baffled by the situation, they decided to read between the lines – clearly they didn’t want us to renew the lease. We could have been forced to rebuild the entire building every year!”.
Mahalnya harga sewa lahan pun memiliki dampak cukup besar, terutama mempengaruhi biaya operasional. Setidaknya dari yang saya tahu dan temui – di Kota Bandung dan Jakarta – beberapa toko rekaman besar itu menempati pusat-pusat perbelanjaan mahal dan mewah. Atau berada di jalan elit yang menjadi kawasan dagang/perbelanjaan cukup ternama. Asumsi saya, hal itu tentu memiliki dampak yang membuat harga lahan kian melonjak dan mencekik toko-toko rekaman.
Di satu sisi, terjadi fenomena cukup unik. Toko-toko rekaman “kecil” justru yang berada di luar mall seperti pasar, ruko, lapakan, hingga terminal malahan mampu bertahan dengan segala keterbatasannya. Pemanfaatan pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Santa (Jakarta) dan Pasar Cikapundung (Bandung) telah menjadi sentrum baru distribusi album rekaman. Pasar tradisional itu pun menjadi gairah baru para anak muda – terutama penggemar rilisan fisik – untuk tetap datang dan berbelanja di sana. Toko-toko rekaman yang ada di pasar hingga terminal itu juga telah “berinovasi” menjadi ruang baru komunitas. Toko-toko rekaman itu tak hanya menjadi tempat transaksi ekonomik semata, akan tetapi juga menjadi tempat transaksi pengetahuan seputar musik. Menjadi tempat nongkrong kalangan pecinta musik dari musisi, kolektor, hingga pengamat musik. Sesuatu yang tak bisa didapatkan di toko-toko musik yang ada di mall mewah dan besar.
Masifnya perubahan yang terjadi pada pasar-pasar itu tak lepas dari masalah. Kembali dari apa yang saya dengar setelah pasar kian ramai pihak penguasa lahan atau pengelola pasar menaikkan harga sewa. Tantangan yang dihadapi bukan persoalan pembajakan atau musik digital. Tapi tantangan menghadapi naiknya nilai sewa lahan atau pajak retribusi yang melonjak yang dapat membuat toko-toko rekaman tersebut berada di ujung tanduk.
Gentrifikasi menjadikan toko-toko rekaman itu selalu berstrategi dan berinovasi. Perubahan yang terjadi memang tak selamanya bisa diantisipasi. Dalam film Last Shop Standing diceritakan beberapa toko rekaman, misalnya, menggelar showcase ataupun meet and greet agar pengunjung selalu setia datang ke toko mereka. Beberapa toko rekaman seperti di Bandung dan Jakarta aktif mengadakan kegiatan-kegiatan musik berbasis komunitas. Seperti para pedagang di Pasar Santa dan Blok M yang masih aktif menggelar bazaar dan festival album rekaman. Begitu pula di Bandung, komunitas Pasar Cihapit dan Omuniuum juga aktif mengadakan kegiatan-kegiatan serupa. Puncaknya, festival Record Store Day yang selalu menjadi gairah dan antusiasme para pecinta musik. Ternyata keinginan mendengarkan musik melalui piranti fisik masih banyak diminati, apalagi oleh anak-anak muda dan remaja yang berbondong-bondong membeli kaset, CD, hingga piringan hitam.
Keberadaan toko-toko rekaman itu tak sekedar menjadi tempat transaksi ekonomik semata. Pada aspek lain tersimpan berbagai kegiatan-kegiatan berbasis komunitas yang terus hidup dan menjadi kunci eksistensi saat ini toko-toko rekaman untuk bertahan dan menghidupi dirinya sendiri. Keberadaan toko-toko rekaman yang ada di sebuah kota merupakan sebuah ekosistem dari baik dari segi ekonomik hingga terciptanya akses pengetahuan.
Musik menyimpan suatu misteri. Begitu pula dengan industri musik dan segala kompleksitasnya. Sekian analisis dan kajian mengenai industri musik yang dianggap “mati” dan “bangkrut” dan sekian teori-teori untuk memperbaikinya ditemui di berbagai ulasan buku dan media massa. Namun, melihat gairah orang-orang yang setia dan senantiasa membeli rilisan fisik membuat saya percaya bahwa ada satu hal yang tak pernah “mati” dalam musik: gairah atau passion itu sendiri. Persoalannya bukanlah maraknya pembajakan atau teknologi – toh perkembangan teknologi tak bisa kita cegah. Atau sekian perubahan sosial yang menciptakan gentrifikasi-gentrifikasi baru dimanapun – sesuatu yang lazim di kota besar. Apalagi tanpa adanya jaminan intervensi dan regulasi dari pemerintah yang membuat pemilik lahan bisa menaikkan harga lahan secara tiba-tiba. Tapi, toh, toko rekaman “kecil” di beberapa kota besar itu mampu bertahan dari setiap perubahan dan berstrategi dengan segala keterbatasannya. Salah satunya, mengembalikan kembali orang-orang agar senantiasa berkunjung ke toko rekaman. Every day is a records store day!
“Gentrifikasi & Toko Rekaman Fisik” ditulis oleh:
Idhar Resmadi
His writings are most often focused on music and culture. He is also active as a researcher, speaker, moderator, and lecturer in various music and cultural forums. His publications include Music Indie Label Records (2008), Like This: Kumpulan Tulisan Pilihan 2009-2010 Jakartabeat (2011), NU-Substance Festival (2013) and Based on a True Story Pure Saturday (2013). He has written for numerous media outlets in Indonesia.