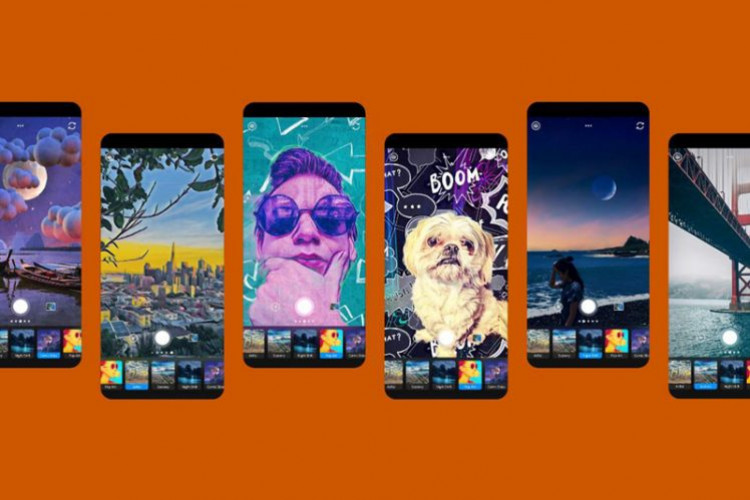Kurasi Seni bersama Jim Supangkat
Muhammad Hilmi (H) berbincang dengan kurator Jim Supangkat (J).
by Ken Jenie
























H
Anda salah seorang penggagas “Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia” pada 1975, apa alasan di balik pemberontakan Anda terhadap seni rupa lama?
J
Memang saya menyebut-nyebut “seni rupa lama” pada pernyataan Gerakan Seni Rupa Baru. Seni rupa lama ini adalah batasan akademis pada pengajaran di semua perguruan tinggi seni rupa di Indonesia waktu itu. Batasan ini mengutamakan seni lukis, seni patung dan seni grafis yang punya kekhasan yang diazaskan. Lukisan, misalnya, harus dua dimensional, dan, patung harus tiga dimensional. Lukisan yang permukaannya terlalu menonjol keluar, atau, patung yang permukaannya dilukis dengan cat, dipertanyakan.
Gerakan Seni Rupa Baru adalah pemberontakan akademistis pada perguruan tinggi seni rupa di Bandung dan di Yogyakarta. Seni rupa baru adalah seni rupa yang menabrak semua batasan-batasan akademis tadi. Seni rupa baru bahkan membebaskan bentuk karya seni rupa. Membuat karya, tidak harus misalnya, menggunakan high materials seperti kanvas, cat Rembrant, marmer, logam atau hand made paper. Jadi bisa saja membuat karya dari barang jadi (ready mades) bahkan barang-barang bekas. Saya membuat karya-karya seperti ini sejak 1972, waktu masih menjalani pendidikan.
Seni rupa kontemporer sekarang ini bisa dibilang seni rupa baru bila dilihat dalam konteks Gerakan Seni Rupa Baru. Pada 1975 istilah “contemporary art” dengan pengertiannya yang sekarang, belum meluas bahkan di Eropa dan Amerika Serikat.
H
Apa yang membuat Anda memutuskan menjadi kurator, kritikus seni?
J
Saya mengambil keputusan menjadi kurator pada 1990 setelah mengikuti ARX (Artists Regional Exchange) sebuah forum seni rupa kontemporer di Perth, Australia pada 1989. Waktu itu saya menyadari munculnya peluang bagi seniman Indonesia untuk memasuki forum seni rupa dunia melalui Australia. Forum ini membuat saya sadar juga tentang perlunya profesi kurator pada upaya ini sementara waktu itu tidak ada kurator di Indonesia dan kekosongan ini harus diisi.
Secara kebetulan pada 1989 saya mendapat informasi tentang perubahan pengertian kurator di Amerika Serikat setelah sejumlah kurator museum ramai-ramai meninggalkan museum dan menyatakan mereka adalah independent curator. Mereka menyusun pengertian baru tentang kurator.
Percaya bahwa peluang memasuki forum dunia memang sedang terbuka bagi seniman Indonesia, dan, tertarik pada pengertian kurator yang progresif, saya bersama Alm. Sanento Yuliman memutuskan untuk menjadi kurator. Dugaan saya ternyata tidak meleset, pada dekade 1990, Australia dan Jepang memusatkan perhatian pada perkembangan seni rupa kotemporer Asia dan seperti kita ketahui, progam-program dikedua negara ini menjadi batu loncatan seniman Indonesia untuk memasuki forum seni rupa dunia.
H
Bagaimana menjalani transisi dari seniman ke kurator? Apakah pengalaman bekerja di dua media, di Tempo dan di Aktuil, berpengaruh dan membantu saat itu?
J
Iya memang, saya sempat bimbang sebelum mengambil keputusan menjadi kurator karena saya merasa harus meninggalkan profesi seniman kalau mau jadi kurator. Sebagai seniman tentu saja saya punya keinginan juga untuk muncul di forum dunia, apalagi karya kolaboratif yang saya buat bersama tiga kawan seniman di ARX, 1989 menarik perhatian karena mengundang reaksi masyarakat di Perth. Karya ini membela penderita AIDS yang waktu itu masih dicerca, dikutuk , disingkirkan dan diperlakukan seperti kaum pariah. Seperti kita ketahui baru pada 1991 masyarakat dunia mulai merangkul penderita AIDs dan mereka yang terinfeksi HIV.
Namun saya akhirnya memutuskan untuk menjadi kurator dan berhenti berkarya. Sebetulnya menjadi seniman sekaligus kurator bukannya tidak mungkin. Di berbagai negara banyak seniman yang bekerja juga sebagai kurator. Tapi untuk konteks Indonesia saya merasa kurator seharusnya meninggalkan profesi seniman, supaya tidak kepancing menjadi korup.
Tentu ada pertimbangan lain di balik keputusan itu. Sudah sejak di pendidikan seni rupa saya tertarik pada pemikiran dan teori-teori seni rupa dan terbiasa menuliskan pikiran-pikiran saya. Kebiasaan menulis ini yang membawa saya ke majalah Aktuil, Zaman dan Tempo. Anda benar dengan bekerja di media massa, khususnya Tempo, kemampuan saya menulis berkembang.
H
Di zaman di mana semuanya instan, siapa saja bisa menjadi apa saja, termasuk menjadi seniman. Apakah hal yang sama berlaku pada gejala menjadi kurator?
J
Sekarang ini profesi independent curator tidak lagi terikat pada citra pergerakan ketika gagasan tentang kurator independen muncul. Dalam perkembangan sekarang isitilah ini dimaknai harafiah di mana predikat “independent” membebaskan kurator dari tanggung jawab publik. Maka praktek apa pun yang dilakukan “kurator-kurator bebas” ini tidak bisa disalahkan. Di Tiongkok, kebanyakan independent curator yang kebetulan saya temui adalah art dealers.
Di tengah perkembangan seperti itu muncul kesadaran bahwa kurator museum, adalah kurator yang punya tanggung jawab publik karena mereka bekerja di lembaga publik dan hasil kerja mereka berkaitan dengan kebudayaan dan citra peradaban sesuatu masyarakat. Karena itu kurator museum harus memegang kode ethik dengan keras. Tanggung jawab ini juga yang membuat kemampuan mereka menjadi ukuran. Kurator yang menjadi chief curator di museum-museum adalah kurator-kurtator terbaik, diukur dari ilmu yang dikuasainya.
Kurator independen tidak punya tanggung jawab seperti itu dan tidak dituntut punya kemampuan. Karena itu siapa pun bisa menjadi kurator. Apakah mereka “laku” atau tidak bergantung pada siapa yang “membeli” jasa mereka. Di pasar seni rupa, justru kurator yang tidak keras kepala yang disukai karena bisa diajak pat gulipat dalam menjalankan bisnis karya seni.
Di Indonesia di mana museum publik relatif tidak ada para kurator umumnya kurator independen. Namun ketika merintis profesi kurator saya menentukan sikap dan menjadi kurator independen yang punya tanggung jawab publik walau tidak ada tuntutan untuk ini. Pertimbangannya di Indonesia tidak ada kurator museum jadi kurator yang punya tanggun jawab publik, tidak ada. Sepengetahuan saya sebagian besar kurator di tanah air mengambil sikap yang sama.
H
Bagaimana sebenarnya posisi kurator dalam penciptaan karya seni ? Karya/eksibisi seperti apa yang harus ada proses kurasinya, apakah ada batasan-batasan tertentu?
J
Hubungan kurasi dengan pameran seni rupa sudah menjadi tradisi sehingga jarang dipersoalkan lagi apakah pameran harus dikurasi atau tidak. Dasarnya adalah kepercayaan bahwa nilai-nilai pada karya seni rupa berada di wilayah pemikiran, dan, diperlukan pengalaman melihat yang ada ilmunya, untuk membaca nilai-nilai ini. Kalau ada seniman atau seniman-seniman yang merasa punya kemampuan melakukan sendiri hal-hal ini, mereka tidak memerlukan kurator dan pameran mereka tidak perlu dikurasi.
Munculnya profesi kurator independen menambah dimensi kurasi. Kemunculan profesi ini tidak terlepas dari perkembangan seni rupa kontemporer yang dipicu pengaruh cultural criticism pada 1980an yang intinya adalah sikap kritis masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam penggalian nilai-nilai budaya. Waktu itu nilai-nilai yang digali para kurator museum adalah nilai-nilai absolut berdasarkan sejarah seni rupa yang tercermin pada koleksi museum. Kurator independen mengambil sikap lain. Bersama seniman mereka terjun ke masyarakat dan menggali nilai-nilai budaya yang aktual. Di sini komunikasi dengan masyarakat, presentasi pameran, policy memancing impact menjadi persoalan penting. Kerja sama seniman dan kurator pada penyelenggaraan pameran memperhitungkan hal-hal ini.
H
Bagaimana pandangan Anda tentang perkembangan kurator di Indonesia?
J
Menggembirakan. Pada studi tentang praktek kurasi di Asia Tenggara yang diprakasi Japan Foundation beberapa waktu lalu terungkap jumlah kurator di Indonesia jauh melebihi jumlah kurator di negara-negara Asia Tenggara lain. Prakteknya yang melibatkan pemikiran dinilai punya dampak pada kemajuan. Bila dibandingkan, di beberapa negara Asia Tenggara lain banyak kurator yang bekerja di bawah organizer dan urusannya cuma presentasi pameran.
Padahal pendidikan formal untuk menjadil kurator tidak ada di Indonesia. Di semua perguruan tinggi seni rupa tidak ada pendidikan art historian yang sudah sejak tingkat pertama mendalami teori-teori seni rupa dan lulusannya bisa menjadi kritikus, kurator, sejararawan seni rupa atau pemilik galeri. Mereka yang tertarik menjadi kurator sebelumnya memang sudah tertarik pada pemikiran dan teori-teori seni rupa dan mempelajari sendiri seluk beluk sejarah seni rupa dan berbagai pengetahuan lain. Sekarang ini ada beberapa perguruan tinggi seni rupa yang membuka peluang bagi prakasa ini. Sebagian kurator tercatat menyelesaikan studi S2 dan S3 di perguruan tinggi seni rupa ini.
H
Bagaimana melihat publikasi/jurnal dan kritik seni rupa di Indonesia?
J
Ya, saya sering dengar pendapat yang melihat kritik seni di Indonesia menurun frekuensinya dan menyebabkan perkembangan seni rupa kita menjadi tidak karuan. Memang, profesi kurator dan kritikus pada dasarnya berbeda. Kritikus menulis komentarnya setelah melihat sesuatu pameran sementara kurator menulis pengantar pameran pada katalog setelah menyiapkan pameran selama berbulan-bulan bersama seniman/seniman-seniman. Namun pada perkembangan sekarang batasan kritikus-kurator sudah menjadi abu-abu.
Ketika saya mengikuti konperensi International Association of Art Critics (IAA) di Tokyo, Jepang pada 1997 batasan kritikus-kurator masih dipersoalkan kurator-kurator Jepang yang mengaku pada saya tidak pernah sekali pun menulis kritik di media massa. Mereka bertanya-tanya apa mereka layak menjadi anggota asosiasi kritikus walau akhirnya mereka mendaftar juga. Pada konperensi terungkap, tidak ada masalah, mereka bisa saja menjadi anggota IAA. Di sidang pertama disebutkan dengan ringan bahwa tulisan kuratorial pada katalog pameran bisa saja dianggap kritik seni.
Memudarnya peran kritik seni terjadi di seluruh dunia paralel dengan perubahan yang terjadi karena munculnya seni rupa kontemporer. Secara umum, penilaian karya seni yang melibatkan kualifikasi yang menjadi kerjaan kritikus sudah bergeser menjadi penggalian nilai-nilai dan upaya sosialisasinya. Selain itu berkembangnya kurasi membuat publik menoleh ke penjelasan kuratorial yang panjang lebar dan mendalam. Kritik seni di media massa yang ringkas dan hanya didasarkan melihat pameran tentunya terasa kurang credible. Saya rasa para kritisi menyadari hal ini. Daripada berusaha menyaingi penjelasan kuratorial lebih baik menulis resensi pameran yang tentunya berguna bagi publik yang tidak langsung melihat pameran dan mendapat katalog pameran.
H
Di tahun 1997, Anda menulis buku berjudul “Indonesian Modern Art and Beyond”, sekarang hampir sepuluh tahun kemudian, apa ada yang berubah pada seni rupa di Indonesia? Apakah Anda akan menulis sekuelnya?
J
Ya betul, buku itu diprakarsai Yayasan Seni Rupa Indonesia untuk melengkapi kesertaan Indonesia pada pameran yang diselenggarkan Word Economic Forum, 1997 di Davos, Swiss. Isinya pengantar ringkas tentang perkembangan seni rupa di Indonesia dari zaman kolonial, sampai perkembangan 1990an.
Kalau dilihat sekarang, buku itu nggak bagus. Editing Bahasa Inggrisnya buruk sekali karena editornya nggak mutu. Distribusinya kebetulan tidak bagus juga. Penulisannya sekadar mendispkripsikan perkembangan yang jauh dari pendekatan melalui teori sejarah seni rupa karena saya ragu-ragu. Tapi saya mencatat di buku itu kemunculan seni rupa kontemporer (beyond modern art) yang berkembang paralel dengan seni rupa kontemporer di Asia. Sekarang perkembangan ini sudah menjadi jelas bukan berubah.
Kalau buku itu bagus, sekarang saya tentunya tinggal menyuruk ke berbagai detail perkembangan. Tapi buku itu tidak bagus, jadi hukumannya saya harus menulis buku baru tentang seni rupa Indonesia yang pendekatannya sama sekali lain. Dalam jangka waktu hampir 20 tahun banyak perubahan pada pemikiran saya, banyak keraguan yang rasanya sirna. Moga-moga ini perkembangan.
H
Menurut Anda, apa yang harus diperbaiki pada iklim seni rupa Indonesia?
J
Saya sependapat dengan pandangan yang sudah sering dikemukakan yaitu perlunya pengembangan infrastruktur. Namun saya tidak melihatnya sebagai persoalan lembaga-lembaga pada infrastruktur. Saya cenderung melihatnya sebagai mekanisme percaturan nilai-nilai pada infrastruktur. Mekanisme ini merupakan exercises menaikkan tingkat berpikir bersama dalam lingkup masyarakat dalam menghadapi hal-hal kecil yang hasilnya diperlukan untuk menghadapi persoalan-persoalan besar.
Dalam garis besar bisa saya sebutkan ada dua tingkat berpikir. Yang satu, pemikiran di tingkat praxis di mana kenyataan dilihat secara spesifik dan disiasati, diperhitungkan, dikalkulasi bahkan secara profesional. Di sini kenyataan dilihat sebagai particulars yang berkaitan dengan persoalan praktis yang sudah kodratnya berhubungan dengan interes yang personal. Pemikiran yang lebih tinggi berada di ruang metafisis di mana kenyataan dilihat sebagi universals. Di sini kenyataan kehilangan sifat materialnya dan juga aspeknya yang spesifik dan praktis. Pada pemikiran ini bisa ditemukan kesadaran tentang nilai-nilai, hati nurani, spirit, kebaikan (goodness), pikiran positif dan common sense. Percaturan nilai-nilai pada infrastruktur kesenian berada pada pemikiran ini. Karena itu tingkat berpikir metafisis ini seringkali memperlihatkan sifat-sifat kesenian seperti kepekaan (sensibilty), keharuan, pesona keindahan, kontemplasi dan pencerahan.
Dampak komodifikasi karya seni rupa yang sekarang ramai menunjukkan tidak bekerjanya mekanisme pada infrastruktur itu. Terjadi ekskalasi harga karya seni rupa yang bertumpu pada isu-isu tidak signifikan seperti lukisan palsu misalnya, kepercayaan pada mekanisme pasar, bahklan kerja sama dengan seniman. Di sini nilai nominal karya seni rupa yang mencapai jutaan dolar tidak didasarkan nilai-nilaii intrinsik karyanya. Ketika isu ini memasyarakat muncul upaya keras untuk membuat gejala tidak masuk akal ini menjadi masuk akal. Common sense tidak bisa dipaksakan dan masyarakat merasakannya.
Dalam sklala besar, baru saja kita menyaksikan perdebatan publik dalam scope nasional di mana hukum, politik, konstitusi bahkan hak azasi manusia yang kehilangan kadar filosofisnya dikaji sebagai particulars. Kita bisa merasakan bagaimana kepentingan personal ditampilkan secara demonstratif, dan merasakan terdesaknya etika sosial, hati nurnai, kepekaan dan kesantunan terdesak pada perdebatan ini. Kembali terlihat upaya mati-matian untuk membuat gejala tidak masuk akal menjadi masuk akal. Sekali lagi terlihat bahwa common sense tidak bisa dipaksakian dan masyarakat merasakannya.
H
Adakah cerita menarik selama menjabat kurator galeri nasional?
J
Saya tidak pernah menjadi kurator Galeri Nasional sejak diresmikan pada 2000 sampai sekarang, karena Galeri Nasional lahir dari usul saya dan saya mehindari kesan bahwa saya membuat proposal supaya saya bisa menjadi kurator Galeri Nasional. Kecurigaan ini beredar luas waktu itu. Tapi memang saya punya banyak cerita menarik tentang Galeri Nasional walau bukan sebagai kuratornya.
Galeri Nasional lahir pada masa Prof. Edi Sedyawati menjadi Direktur Jendral Kebudayaan, pejabat yang betul-betul memikirkan kebudayaan di tengah anggaran yang boleh dibilang nyaris nol bila dibandingkan anggaran Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Depdikbud waktu itu. Pada masa jabatannya Ibu Edi yang dikenal juga sebagai penari lebih mengandalkan kawan-kawannya seniman dari pada para pejabat dan pegawai Ditjenbud. Saya salah satu di antaranya. Dengan cara ini Ibu Edi melahirkan berbagai tanda budaya yang terkategori besar dengan anggaran tambal sulam. Lahirnya Galeri Nasional, salah satunya.
Ibu Edi mengajukan academic paper Galeri Nasional ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) pada 1996 dan dengan gigih menghadapi proses sulit. Butuh tiga tahun, melalui beberapa Mendikbud dan beberapa Menpan ujntuk menggolkan usulan ini. Galnas akhirnya diresmikan pada 2000, namuni sebagai lembaga Eselon 3, setara Taman Budaya di daerah-daerah, yang anggarannya kembali nyaris nol. Untuk membantu supaya bisa berdiri Menpan memberi status swa dana, alias cari duit sendiri lah, dengan janji kalau sudah bisa jalan akan dinaikkan menjadi lembaga Eselon 2 setara dengan Museum Nasional yang anggarannya tentu lebih besar.
Untuk mengatasi kondisi apes seperti itu saya dan Ibu Edi mencoba merangkul organisasi swasta, galeri dan seniman yang punya sponsor untuk membiayai program pameran Galnas. Kami tahu, mereka bisa menjual karya-karya sesudah pameran. Cukup fair karena mereka mengeluarkan dana. Namun kami membuat ketentuan tidak boleh menjual karya atau melakukan transaksi apa pun selama pameran.
Persyaratan lain, kualitas pameran tidak bisa ditawar. Untuk ini dibentuk tim kurator Galnas. Saya minta para kurartor untuk mau gantian secara periodik menjadi kurator-kurator Galnas tanpa gaji. Kerjanya mengkaji dan menyeleksi dengan ketat proposal pameran yang masuk untuk menyusun program tahunan. Semua kurator bersedia dan yang terpilih mau datang beberapa kali setahun untuk sidang di Galnas dengan imbalan uang jalan.
Seperti kita ketahui dengan cara itu Galnas dalam perkembangannya memunculkan pameran-pameran besar bahkan yang berskala internasional. Galnas menjadi semacam lembaga arbitrasi dalam mengukur reputasi seniman dan perkembangan seni rupa kita. Di forum dunia, Galnas dikenal sebagai Galeri Nasional “sungguhan” dengan anggaran “sungguhan”. Tidak ada yang menyangka bahwa Galnas yang dipahami di mana pun sebagai lembaga negara dan bukan sekadar lembaga pemerintah dibiayai masyarakat secara tanggung renteng. Depdikbud yang pernah menjadi Deparbud, tahu tapi tidak peduli karena tidak mengerti. Status Galnas tetap saja Eselon 2 dan dipimpin oleh seorang kepala UPT (unit pelayanan terpadu) yang kedudukannya di bawah direktur.
Baru tahun lalu Pak Katjung Maridjan, Dirjenbud yang sekarang menaikkan anggaran Galnas. Bersamaan dengan ini meminta saya kembali menyusun academic paper untuk menaikkan status Galnas ke Eselon 2. Saya dengar, rencana Pak Kacung yang tergantung selama hampir satu tahun pada formasi Kemendikbud yang dulu, sudah disetujui Pak Anis, Mendikbud sekarang, dan sedang dalam proses diajukan ke Menpan. Kita bersyukur.
H
Tentang pameran “Aku Diponegoro”, bagaimana asal mula ide-nya muncul?
J
Wah soal ini Anda harus mencari informasi ke Goethe Institut. Ketika saya diminta untuk membantu sebagai kurator saya mengira pameran ini merupakan kelanjutan pameran Raden Saleh pada 2012. Ternyata tidak. Goethe Institut memutuskan untuk menampilkan Pangeran Diponegoro yang penangkapannya menjadi tema lukisan Raden Saleh yang akan dipamerankan karena baru saja direstorasi dengan bantuan Goethe Institut.
H
Apa visi yang ingin dicapai dengan melibatkan seniman dari berbagai generasi termasuk seniman kontemporer di pameran Aku Diponegoro ini?
J
Estimasi awal pada penyusunan kurasi adalah kontinuitas munculnya Pangeran Diponegoro pada perkembangan seni rupa Indonesia yang mengacu pada sejarah Indonesia. Namun estimasi ini ternyata tidak bisa ditegaskan pada pameran karena tanda-tanda yang muncul dalam pengkajian dan tercermin pada karya para seniman peserta pameran justru menunjukkan diskontinuitas.
Mulanya adalah tanda-tanda bahwa Pangeran Diponegoro muncul sebagai icon pada lukisan dan poster perjuangan antara 1946 -1949. Proses dekolonisasi ini melibatkan perang di antara pendukung Republik dengan KNIL, tentara Belanda yang membawa bendera Sekutu dan PBB. Tidak bisa ditemukan jawaban mengapa Pangeran Diponegoro yang dimunculkan sebagai icon pada perjuangan ini. Catatan sejarah yang menjadi pengetahuan umum waktu itu adalah Perang Diponegoro yang dikenal sebagai Perang Jawa (1825-1830) adalah perlawanan terbesar dan termahal pada masa kolonial.
Gejala yang terbaca sebagai tanda-tanda sejarah pada ungkapan seni itu menarik perhatian para sejarawan karena tidak diperhatikan pada penulisan sejarah Indonesia. Apalagi sesudah Indonesia merdeka masih bisa ditemukan lukisan-lukisan yang menampilkan Pangeran Diponegoro sebagai tema. Melihat ke belakang, Pangeran Diponegoro muncul pada lukisan Raden Saleh yang dibuat pada Abad ke-19, dan, ditemukan juga beberapa tanda lain antara Abad ke 19 dan awal Abad ke-20. Lahir kemudian pertanyaan apakah ada kontinuitas yang bisa menunjukkan Pangeran Diponegoro sebagai icon dalam sejarah Indonesia ?
Namun dalam sejarah Indonesia dengan narasi bangsa sebagai kanon, perlawanan Pangeran Diponegoro dibaca sebagai salah satu di antara berbagai perlawanan di seluruh tanah air pada masa kolonial. Dengan mengangkat para pemberontak di masa kolonial sebagai pahlawan-pahlawan nasional, narasi bangsa ingin membangun tanda-tanda bangsa pada wilayah Indonesia sebagai negara post kolonial, yaitu negara yang wilayahnya sama dengan wilayah jajahan pada masa kolonial. Lukisan yang menampilkan Pangeran Diponegoro sesudah Indonesia merdeka menunjukkan persepsi ini. Di sini terlihat diskontinuitas yang membuat lukisan-lukisan ini tidak bisa memberi jawaban mengapa Pangeran Diponegoro yang muncul sebagai icon pada perjuangan 1946-1949.
Pembahasan Pangeran Diponegoro muncul kembali pada perkembangan seni rupa Indonesia setelah lukisan Raden Saleh dengan tema penangkapan Pangeran Diponegoro (1858) dikembalikan keluarga Kerajaan Belanda pada 1979. Lukisan ini kemudian memunculkan kajian sejarah tentang Raden Saleh dan Pengeran Diponegoro yang merupakan bagian dari ilmu sejarah yang mencar kebenaran dan karena itu berjarak dari sejarah sebagai narasi bangsa. Kajian ini kembali menunjukkan diskontinuitas pada upaya melihat Pangeran Diponegoro sebagai icon sejarah Indonesia.
Namun kajian ilmu sejarah itu memunculkan kesadaran baru pada narasi bangsa yang sekarang belum umum dibahas. Muncul dimensi baru pada pembacaan perlawanan Pangeran Diponegoro yaitu dimensi internasional. Pemberontakan ini merupakan salah satu pergolakan sosial di antara berbagai pergolakan sosial pada Abad ke-19 di Eropa dan daerah-daeerah koloninya. Semua pergolakan ini menunjukkan awal kesadaran tentang keadilan sosial dan demokrasi dalam lingkup dunia. Sejarah Indonesia karena itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah dunia. Seniman kontemporer pada pameran ini yaitu seniman muda yang sudah menjadi bagian perkembangan global memperlihatkan passion dalam membaca tanda-tanda itu karena merasa menemukan sejarah mereka.
H
Salah satu highlight pameran Aku Diponegoro adalah karya Raden Saleh, bagaimana signifikansi karya ini dan karya Raden Saleh yang lain?
J
Pada kesadaran baru narasi bangsa yang saya kemukakan tadi, terselip kesadaran tentang perkembangan seni rupa kita, dan tentunya lukisan Raden Saleh yang Anda persoalkan berada pada posisi sentral. Dari pembacaan perkembangan seni rupa ini terungkap tanda-tanda yang dibawa Raden Saleh ternyata tidak terbatas pada perkembangan seni rupa Indonesia.
Dalam beberapa tulisan di jurnal seni sudah saya kemukakan bahwa dimensi sosial politik pada lukisannya tentang penangkapan Pangeran Diponegoro bisa dibaca sebagai alasan mendasar mengapa tradisi art making yang berkembang di dunia Barat diadaptasi di luar dunia Barat. Gejala ini bukan fenomena budaya, seperti pada pembahasan sekarang ini yang macet pada dikhotomi Barat-Timur. Tanda-tanda pada lukisan Raden Saleh ini menunjukkan adaptasi yang terjadi pada Abad ke-19 adalah fenomena sosial politik. Adaptasi art making ini tidak bisa dilepaskan dari adaptasi awal pemikiran modern pada Abad ke-19 yang memunculkan dorongan untuk merdeka di daerah-daerah koloni dan upaya membangun negara yang demokratispada awal Abad ke-20. Pada adaptasi ini kita tidak mempersoalkan awal pemikiran modern ini sebagai pemikiran yang berkembang pada kebudayaan Barat.
Adaptasi itu tidak harus dilihat sebagai pengkopian blue print. Adaptasi ini gejala paralel yang muncul bersamaa di seluruh dunia pada Abad ke-19. Seperti sudah saya singgung tadi, pada Abad ke-19 ini muncul berbagai gejolak sosial di Eropa dan daerah-daerah koloninya. Perang Diponegoro dan perang Padri di Sumatera yang mendahuluinya bisa dimasukkan ke jajaran pemberontakan masyarakat di Eropa dan daerah-daerah koloninya,. Lingkupnya lokal, seperti pemberontakan masyarakat di Eropa yang tercermin antara lain pada dua Revolusi Prancis, yang lokal juga.
Raden Saleh, yang hidup di kalangan elite yang dekat dengan penguasa dan kaum feodal, seperti halnya GWF Hegel, Auguste Comte, Karl Marx, atau John Sutart Mill tergolong kaum intelektual dari kalangan elite yang membenarkan secara ideologis pemberontakan masyarakat. Ini makna lukisannya tentang penangkapan Pangeran Diponegoro dan banyak lukisannya yang lain. Dasarnya bisa diperkirakan pemikiran GWF Hegel pada awal Abad ke-19 yang melihat hubungan mutual antar manusia tidak bisa ditemukan pada hubungan majikan dan budak, yang bisa dibaca sebagai hubungan penjajah dan yang dijajah.
Pemahaman itu membantu kita membaca karya-karya Raden Saleh yang lain.
Karya-karyanya yang mengadaptasi tradisi art making tidak memperlihatkan tanda-tanda akulturasi budaya karena sepenuhnya mencerminkan romantisisme yang berkembang pada saat yang sama di Eropa. Namun sekarang bisa kita lihat bahwa pesan pada lukisan-lukisannya yang kontekstual, ternyata berbeda.
Seperti kita ketahui Raden Saleh sering mengangkat tema perburuan binatang buas. Penggambaran perburuan ini tidak lazim. Perburuan ini hampir selalu digambarkan sebagai pertarungan yang menyerupai perang antara para pemburu dengan binatang-binatang buruan. Ungkapan ini bisa dibaca sebagai perseteruan di antara penjajah dan yang dijajah. Tema lain yang sering muncul juga pada lukisan-lukisan Raden Saleh adalah pergulatan harimau dengan banteng, dan, perkelahian fatal manusia dengan binatang buas. Ungkapan ini bisa dibaca sebagai beradunya kekuatan-kekuatan yang bertentangan dalam perjuangan hidup atau mati. majinasi yang dibangun dengan kepekaan seni ini dalam sejarah Indonesia menjadi realitas sosial politik pada awal Abad ke-20.
H
Peter Carey sempat bercerita bahwa penyajian artefak sejarah yang berhubungan dengan Pangeran Diponegoro menemui kesulitan karena ada beberapa barang yang disakralkan dan tidak bisa dipindahkan ke galeri nasional. Hal yang cukup umum bila dikaitkan dengan pengarsipan di Indonesia, bagaimana Anda melihat fenomena seperti ini?
J
Saya rasa kita membicarakan jubah Pangeran Diponegoro yang tidak jadi hadir pada pameran dan cukup ramai dikomentari di jaringan sos-med. Tentunya saya ikut menyesali pembatalan ini. Kekhawatiran museum di mana jubah ini disimpan tentang kerusakan sama sekali tidak beralasan. Pada tim pameran kami ada konservator dari jerman, Susanne Erhards yang bersama Peter Carey adalah orang-orang paling kompeten dalam menangani Jubah Diponegoro ini. Mereka tidak hanya jaminan keamanan pada transportasi dari Magelang ke Galnas. Mereka malah menyediakan diri untuk memberi saran ahli tentang bagaimana selanjutnya mengamankan artefak berharga ini.
Pembatalan itu tidak bisa disangkal membuat museum di mana artefak itu disimpan malah kehilangan peluang untuk mempublikkan benda bersejarah koleksinya, dan ini adalah tugas para pengelola museum. Tapi apa boleh buat, sangat mungkin para pengelola museum tidak tahu apa tugas dan kewajiban mereka dan Anda benar ini gejala umum pada pengarsipan dan permuseuman kita.
Saya cenderung tidak membahas kejanggalan seperti itu yang saya yakin sangat banyak. Bisa frustasi. Saya lebih suka membahas mengapa kejanggan ini terjadi dan bagaimana menemukan kemungkinan untuk mengatasi kejanggalan ini.
Tadi saya mempersoalkan mekanisme percaturan nilai-nilai pada infrastruktur kesenian dan bukan persoalan lembaga-lembaga pada infrastruktur ini, Sekarang kita membicarakan lembaga-lembaga pada infrastruktur budaya. Seperti kita ketahui, lembaga-lembaga paling penting pada infrastruktur busaya ini, yaitu museum di berbagai daerah, museum nasional, galeri nasional, perpustakaan nasional, dan, situs-situs bersejarah di berbagai daerah dikelola dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Harus segera saya kemukakan bahwa lembaga-lembaga ini bukan lembaga pemerintah, tapi lembaga-lembaga negara.
Karena tanggung jawab mengelola lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan budaya masyarakat dan citra peradaban, pemerintah harus menggariskan national cultural policy yang disusun para ahli dari berbagai bidang, seperi terjadi di berbagai negara maju. Pada kebijakan ini lah bisa ditemukan berbagai rinci ketentuan tentang bagaimana menjalankan museum sehingga para pengelolanya tahu apa tugas dan kewajiban mereka. Seperti kurator museum yang tadi saya persoalkan, para pengelola ini punya tanggung jawab publik.
Sepengtahuan saya national cultural policy tidak pernah digariskan sejak republik berdiri. Mungkin karena tidak terpikir, mungkin juga karena ditakut-takuti seniman. Kita selalu menjadi tegang menghadapi policy pemerintah yang berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian. Takut kebijakan ini akan mendefinisikan segala hal pada kesenian dan kebudayaan yang wajib diikuti seniman dan masyarakat.Khususnya Seniman,yang takut kebebasannya terkekang. Saya rasa ini mitos dan paranoia.
Ketegangan itu membuat kita tidak pernah menoleh ke lembaga-lembaga negara dan mempertanyakan apa mungkin lembaga-lembaga ini, seperti halnya perusahaan atau organisasi apa pun, bisa dijalankan tanpa policy ? Dan juga tidak pernah sampai pada kesadaran bahwa menyusun kebijakan di bidang budaya ini adalah kewajiban pemerintah yang justru harus dituntut kalau tidak ada.
Tentunya national cultural policy harus mempunyai visi untuk menyusun berbagai program pada lembaga-lembaga negara pada infrastruktur budaya ini. Program-program ini punya tanggung jawab. Seperti tadi sudah saya kemukakan, program-program ini seharusnya memacu mekanisme percaturan nilai-nila pada infrastruktur kebudayaan dan kesenian.
Tidak ada istilah terlambat untuk memulai sesuatu yang bisa punya dampak positif dan kita bisa mulai dari lembaga-lembaga negara utama yang paling diamati pada pergaualan internasional, dan, sudah kita miliki. Lembaga-lembaga ini adalah Perpustakaan Nasional, Museum Nasional, dan, Galeri Nasional. Ini materi untuk mulai menyusun national cultural policy. Sekarang ini Perpustakaan Nasional sebagai lembaga berada di bawah Sektertariat Negara, sementara Museum Nasional dan Galeri Nasional berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah. Menurut pendapat saya ketiga lembaga sebaiknya disatukan di bawah Kemendikbud yang paling kompeten untuk menyusun national cultural policy.
Diperlukan penetapan prioritas yang bersifat nasional dalam menjalankan roda ketiga lembaga negara agar dampaknya tidak terbatas pada kesenian dan kebudayaan secara umum. Menurut pendapat saya prioritas ini adalah kesadaran sejarah yang kemiskinannya tidak bisa kita sangkal dan baru saja kita saksikan pada peristiwa gagalnya menampilkan Jubah Diponegoro pada pameran ini. Kemiskinan ini tercermin juga pada pengajaran sejarah di sekolah-sekolah yang tidak bisa membangun gambaran jelas di mana letak awal sejarah Indonesia.
Museum Nasional adalah media yang ideal untuk mengenalkan geo history Indonesia yaitu sejarah nusa antara yang dikenal juga sebagai Indos Nesos. Koleksinya, sekitar 150.000 artefak bisa menunjukkan heritage Bangsa Indonesia yaitu latar belakang budaya yang tidak mengenal batas-batas wilayah negara. Sementara itu Galeri Nasional adalah sarana untuk mempersoalkan sejarah Bangsa Indonesia dalam wilayah negara, Republik Indonesia. Koleksi Galeri Nasional memang mencerminkan sejarah ini. Pameran, “Aku Diponegoro” yang menunjukkan tanda-tanda awal munculnya spirit untuk menjadi bangsa yang merdeka, adalah contoh pameran yang selayaknya ditampilkan di Galeri Nasional.