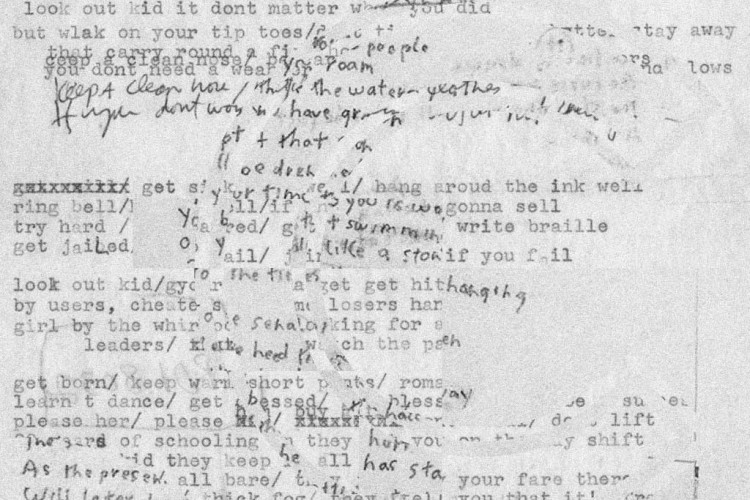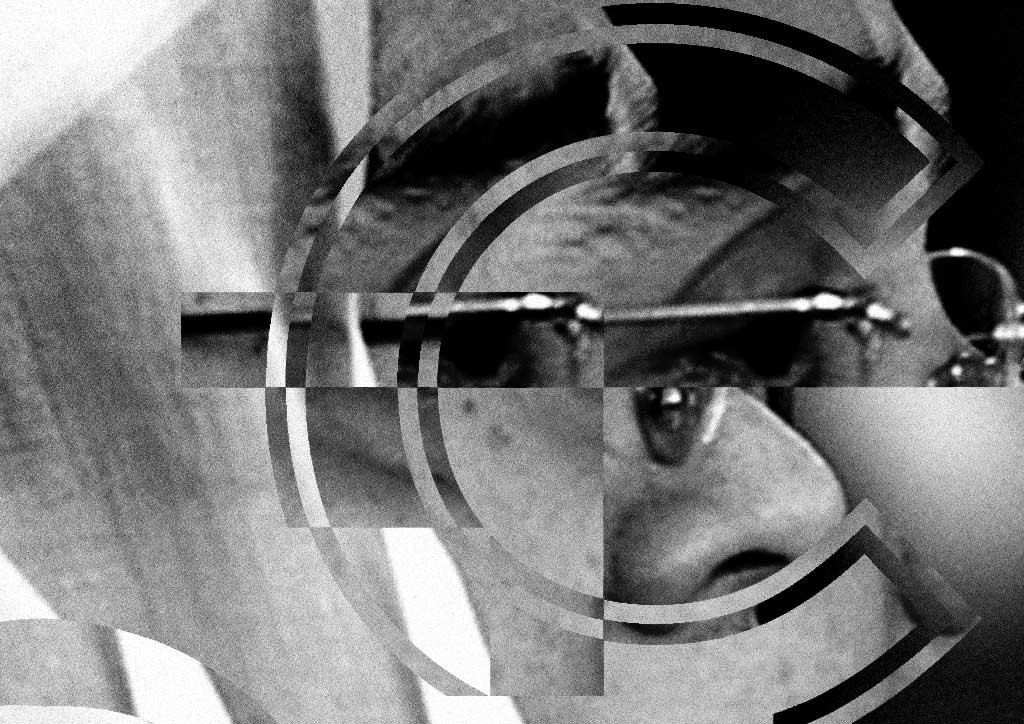
Suatu ketika di sebuah pondok pesantren yang pernah saya ikuti, adik dari ustad kami meninggal. Sang adik meninggal setelah didera sakit sekian lama. Saat itu, ustad kami yang biasanya tegar, tegas dan bijaksana, tampak layu. Dengan maksud ingin menenangkan sang ustad, saya lalu menghampiri beliau sembari berkata, “Ustad yang sabar ya, ‘kan kalau meninggalnya karena sakit berarti dosanya dihapus dan pasti arwahnya masuk surga”. Alih-alih cerah, raut sang ustad justru memerah. Sambil menahan amarahnya, beliau menghardik saya, “Dosa dan surga itu urusan Allah, kita manusia sama sekali tidak berhak untuk menentukannya. Kewajiban kita itu untuk berusaha sebaik-baiknya dan berbuat sebaik-baiknya!”
Lama saya dibuat bingung oleh kalimat sang ustad. Sekian tahun ujaran tersebut meninggalkan sebuah lubang di hati saya. Baru belakangan, saya mulai paham apa maksud beliau sebenarnya.
Paham itu datang pelan-pelan melalui timeline social media saya. Di sana, saya menjadi saksi bagaimana surga yang harusnya suci membuat kita jadi saling membenci. Seolah hanya satu paham saja yang berhak memegang kunci sang nirwana. Di luar paham itu, silahkan mengantri ke neraka, tak peduli bagaimana akhlak mereka sehari-harinya. Yang membuat ini semakin menyesakkan dada, pemicunya adalah seutas masalah yang remeh esensinya. Gara-gara masalah politis di sebuah propinsi kecil, seluruh Indonesia terbakar.
Nalar lantas dipenggal dan digantikan oleh kemarahan. Baik buruk tak berarti lagi. Dibagi kemudian ayat-ayat dengan embel-embel kebencian terhadap kaum tertentu. Dicomot sekenanya dari konteks dan asbabun nuzul-nya (sebab turun sebuah ayat). Habis sudah damai yang harusnya jadi inti dari ajaran ini. “As-silmu” (kedamaian), “aslama” (menyerahkan diri), “istalma mustaslima” (penyerahan total kepada Allah), “saliimun salim” (bersih dan suci), dan “salamun” (selamat) yang sejatinya merupakan sifat-sifat utama yang mendefiniskan ajaran ini tinggal sisa-sisa saja.
Kyai yang menebarkan kedamaian dilabeli ingkar, tokoh penyebar kebencian dirayakan, tragedi yang memakan korban dianggap sebagai pengalih perhatian.
Kalau terus begitu, bukankah kita semua juga menistakan agama kita sendiri? Agama yang menyebarkan kedamaian, kita kabarkan sebagai agama yang penuh azhab, membimbing pada perpecahan, semua demi pintu surga untuk kalangan kita sendiri. Jangan salahkan kalau kemudian beberapa umat merasa jengah dengan agamanya sendiri. Kita juga sama sekali tak berhak marah ketika beberapa orang iri dengan pemuka agama lain yang lebih hangat dalam menyampaikan ajaran-Nya.
Di saat yang sama, kita mengutuki biksu yang memberantas kaum Muslim Rohingya di Myanmar. Ini sebuah hipokrisi yang mengerikan. Bukankah kita sendiri sedang pelan-pelan menjadi biksu-biksu penuh amarah itu, yang mengusir orang-orang “kafir” dari bumi kita?
Ngeri ini semakin terasa nyata saat kebencian tersebut menjangkiti orang-orang disekitar saya. Ada seorang salah satu seniman idola yang dulu saya kenal dengan karya kritisnya, kini gemar membagikan laknat terhadap umat yang berseberangan pendapat. Pula dosen ilmu komunikasi yang dulu saya anggap panutan, kini ikut tenggelam dalam lautan kebencian. Tak jarang beliau membagi berita dari situs yang validitas beritanya diragukan. Ilmu yang beliau dulu ajarkan amblas, tak berbekas. Berlembar-lembar halaman buku Littlejohn (kitab wajib ilmu komunikasi yang berisikan perspektif semiotika hingga kritis) yang beliau ajarkan dahulu kini terasa sia-sia adanya. Terakhir bahkan beliau ikut menyatakan bahwa meninggalnya Intan Marbun, balita korban teror di gereja Samarinda adalah pengalihan isu belaka.
Hati nurani mati, akal sehat lenyap menguap.
Sejujurnya, sempat ada ragu menghampiri. Jangan-jangan memang gerakan-gerakan penuh kebencian itu benar-benar membela Islam. Bahwa saya terlalu moderat (atau justru liberal?) untuk mengakuinya.
Tapi semakin saya membaca, semakin saya tahu bahwa sebenarnya tak ada agama yang dibela di sana. Kalaupun ada, agama adalah semata sumbu yang meledakkan murka umat, yang kemudian diarahkan untuk jadi motor kepentingan golongan tertentu. Nasi sudah jadi bubur, amarah terlanjur membuat persaudaraan kita jadi amburadul.
Kalau begini melulu, lantas kapan kita bisa maju dan memikirkan masalah yang lebih nyata seperti masalah lingkungan juga kemanusiaan. Kapan kita bisa lagi bahagia saat membuka grup WhatsApp teman dan keluarga? Kapan kita bisa berdebat – bukan mengenai siapa yang lebih beragama – tetapi apa yang kita bisa lakukan untuk membagi kebahagiaan kita? Kapan kita bisa menerapkan temuan dan inovasi terkini untuk membuat hidup kita lebih indah dan berfaedah? Supaya kita bisa lebih nyaman untuk membangun hablum minannaas, hablum minallah (hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan Allah). Ataukah masalah-masalah seperti ini terlalu duniawi dan tak bisa membawa kita masuk surga?)
Sembari memutar ulang ingatan masa-masa saya di pondok pesantren, saya berharap ustad saya dalam keadaan bahagia, dan sehat adanya. Dan yang paling penting, kedamaian selalu di hatinya.
“Surga dan Hipokrisi Kita” ditulis oleh:
Muhammad Hilmi
Managing Editor at Whiteboard Journal. His passion in music and the arts inspired him to be involved in multiple creative projects, including his own publication and record label.