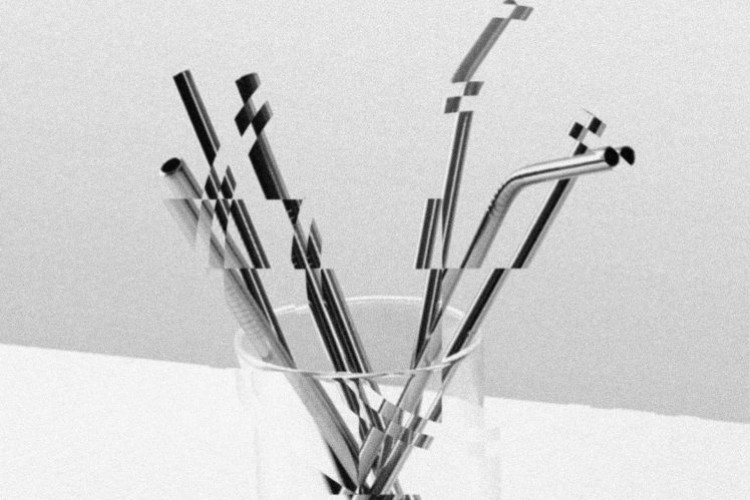“Dare to walk out of your comfort zone,
explore new places because if you don’t step forward,
you will always be in the same place”
Beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Agustus, saya berkesempatan menjadi relawan pengajar di Skola Lipu, yakni sekolah non formal yang dibangun oleh Yayasan Merah Putih guna mengedukasi Masyarakat Adat Tau Taa Wana. Masyarakat ini tinggal di dalam hutan dan tersebar di tiga kabupaten, yaitu di Kabupaten Tojo Una-Una, Banggai, dan Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Perjalanan ini dimulai dari kota Palu menuju Kolonodale, yaitu sekitar 18 jam via travel, kemudian dilanjutkan dengan ferry dari pelabuhan Kolonodale ke Batu Rube yang memakan waktu kurang lebih 5 jam. Setelah itu saya dan teman saya juga beberapa pendamping lapangan melanjutkan perjalanan ke Desa Taronggo.
Di desa Taronggo saya tinggal di rumah Apa Imel dan Indo Imel , wanita paruh baya ini adalah seorang guru lokal yang mengajar di Skola Lipu Sumbol. Dalam cerita kali ini beliau berperan besar dalam memberikan saya arahan dan cerita-cerita mengenai Masyarakat Adat Tau Taa Wana. Pada waktu itu saya mengajar di tiga Skola Lipu, tepatnya di Lipu Sumbol, Salisarao, dan Viautiro. Kata “Lipu” sendiri artinya adalah kampong. Untuk mencapai Sumbol, saya beserta teman saya serta Indo Imel dan beberapa pendamping lapangan harus berjalan selama satu jam dari desa Taronggo. Pemandangan yang disuguhkan selama perjalanan sungguh menakjubkan. Sungai Salato dan pegunungan Tokala serta kebun-kebun masyarakat Tau Taa Wana benar-benar membayar kelelahan saya.
Di Lipu Sumbol, saya menyaksikan sendiri eratnya relasi Masyarakat Adat Tau Taa Wana dengan alam. Untuk bahan makanan, mereka mengambil langsung dari tanah mereka sendiri. Mereka menanam padi ladang, sayur singkong dan ubi kayu. Masyarakat ini juga menanam tembakau sendiri untuk merokok, mereka melintingnya dengan kulin jole, dan untuk minuman tradisional mereka membuatnya dari fermentasi beras pulut dan disebut baru.
Di Sumbol, Salisarao dan Viautiro saya dan seorang teman saya mengajarkan baca dan tulis dalam Bahasa Indonesia. Karena dalam kesehariannya Masyarakat Adat Tau Taa Wana, masih menggunakan bahasa Taa dan bisa dibilang sangat sedikit yang mengerti Bahasa Indonesia. Bangunan Skola Lipu tidak seperti bangunan sekolah pada umumnya, sekolah ini dibangun menggunakan kulit kayu sebagai dinding, daun sagu sebagai atap dan bambu sebagai lantainya. Begitu juga dengan rumah-rumah masyarakat Tau Taa Wana yang terbuat dari bahan-bahan yang sama.
Sistem belajar di Skola Lipu jauh berbeda dengan sekolah-sekolah formal. Di Skola Lipu, siswa-siswinya dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu; tingkat pertama bagi siswa yang baru belajar membaca, tingkat kedua bagi siswa yang sudah bisa membaca tetapi belum lancar menulis, dan ketiga yang sudah bisa membaca dan menulis dengan lancar. Oh Iya, ada lagi perbedaan Skola Lipu dan sekolah formal, yaitu waktu pelaksanaannya. Skola Lipu hanya berlangsung dua kali seminggu, karena di hari lainnya anak-anak Tau Taa Wana harus membantu orang tua mereka di Navu.
Selain itu, kegiatan belajar di Skola Lipu tidak melulu dilaksanakan di dalam ruang kelas. Terkadang saya mengajar di pinggir sungai atau di depan sekolah yang di sekitarnya terdapat pepohonan dan berbagai tanaman. Kegiatan belajar dilakukan di ruang terbuka karena mereka diharapkan untuk tetap melestarikan alam seperti pesan nenek moyang mereka yang telah dipelihara secara turun temurun.
Sesudah beberapa hari saya mengajar di Lipu Sumbol, saatnya saya pergi ke Lipu Salisarao. tempat ini berada di atas gunung dan terbilang sulit untuk dijangkau, terutama bagi saya yang tidak memiliki pengalaman naik gunung sebelumnya. Jujur saja, pada waktu itu saya sedikit takut karena selain jalannya licin, treknya pun sangat curam. Tetapi bermodalkan nekat dan berkat semangat dari Indo Imel saya tetap melanjutkan perjalanan. Terlebih lagi hari itu hujan deras, terpaksa saya dan Indo Imel melanjutkan perjalanan dengan basah kuyup.
Menurut cerita masyarakat Tau Taa Wana, Salisarao diambil dari nama seorang pemuda bernama Sali yang selalu memakan Uvu Sarao atau buah pinang. Sesampainya di Salisarao, saya disambut oleh salah seorang warga yang kerap disapa dengan nama Apa Ince, untuk bermalam di rumahnya. Lalu keesokan harinya saya mulai bersiap untuk mengajar di Skola Lipu Salisarao dan dari kejauhan saya melihat anak-anak sudah siap untuk mulai sekolah. Ketika saya memasuki kelas, saya melihat seekor ular yang menggantung diatap, tidak lama setelah itu saya lari keluar sekolah karena takut, namun seorang siswi bernama Sera menghampiri saya dan berkata “ibu guru, etu ule yore” ,ia berbicara dalam Bahasa Taa yang artinya ular itu sedang tidur. Mendengar itu saya menjadi sedikit tenang dan kemudian memulai pelajaran membaca dan menulis. Benar saja, hingga kelas selesai ular itu pun tetap tidur dan masih di posisi yang sama. Kira-kira begitulah pengalaman saya yang tidak dapat dilupakan di Lipu Salisarao, mulai dari perjalanan yang bagi saya lumayan berat, hingga ular tidur yang sempat membuat saya lari ketakutan. Tentunya itu tidak akan pernah saya lupakan.
Lanjut ke Viautiro. Tempat ini sedikit lebih jauh dari Salisarao. Arti dari Viautiro sendiri adalah lubang besar, dan memang di Viautiro terdapat lubang besar seperti Goa yang disebut sebagai Viau Kumborang, di dalamnya terdapat batu yang menyerupai perempuan dan konon menurut cerita turun-temurun, perempuan itu dikutuk menjadi batu. Sebelum mengajar saya sempat berkunjung ke sana untuk beristirahat sejenak. Di Lipu Viautiro sebenarnya ada guru lokal yang bernama Pono. Ia adalah anak dari Tau Tua Lipu (Kepala kampung) Viautiro, dan menurut cerita dari Pono, akhir-akhir ini siswa yang datang untuk sekolah semakin sedikit. Ketika saya mengajar di sana, hanya ada tiga orang siswa yang hadir. Namun begitu, saya tidak kecewa dan tidak menyurutkan niat saya untuk tetap mengajar.
Dan di Viautiro lah puncak dari pengalaman saya yang tidak terlupakan. Mengapa demikian? Karena pada saat itu saya dan salah seorang kawan serta sang pendamping lapangan tidak membawa persediaan makanan sedikitpun. Alhasil, saya dan salah satu siswa bernama Pengge, pergi mencari ubi kayu untuk dibakar. Di sini pertama kalinya saya menggunakan parang untuk mengambil bahan makanan langsung dari tanah. Perasaan saya pada saat itu sungguh campur aduk. karena saya tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa suatu hari saya dapat melakukan hal itu.
Pengalaman mengajar di Skola Lipu sungguh luar biasa, bagi saya, ini merupakan pengalaman eksklusif dan dapat dibilang a life changing experience. Selain mengajar, saya juga mendapat banyak pelajaran dan di samping itu saya sangat kagum dengan kebiasaan hidup Masyarakat Adat Tau Taa Wana, mereka begitu hormat dengan alam dan menjaganya dengan sangat baik sebagaimana alam menjaga mereka.
Salam rindu untuk keluarga ku, seluruh Masyarakat Adat Tau Taa Wana.
“Three Months of Life Changing Experience: Indahnya Mengajar di Hutan” ditulis oleh:
Mutiara Sobary
Mahasiswa studi filsafat yang pernah menjadi instruktur yoga serta volunteer di Skola Lipu.