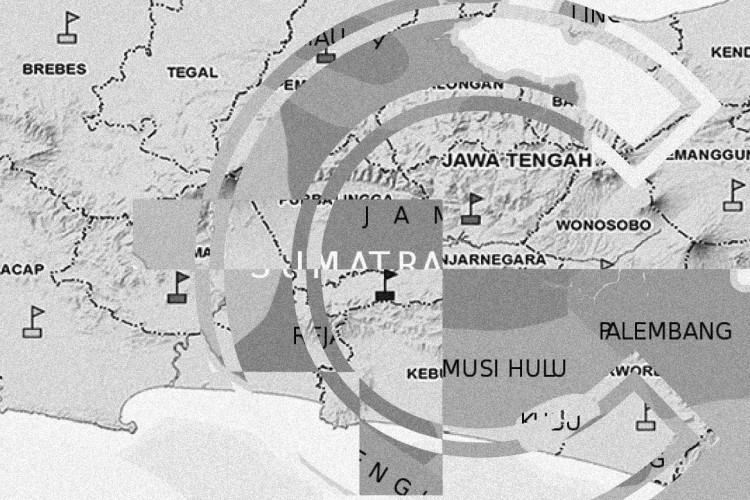Begitu turun dari bus karyawan yang membawa kami dari kantor di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sampai di depan Museum BI di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, kami bergegas menyeberang jalan raya yang seharusnya tidak kami lakukan, tapi kami lakukan berulang-ulang. Padahal sejak tahun 2005 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun terowongan penyeberangan orang dari depan Museum Bank Mandiri sampai ke Stasiun Jakarta Kota yang panjangnya sekira 48 meter dengan lebar 8,10 meter. Turun naik tangga itulah yang menyebabkan kami malas melewati fasilitas yang kini sudah berwajah begitu cantik, meski ada sedikit jerawat itu. Kami memilih jalan pintas. Jalan yang tak sepantasnya kami pilih. Jalan raya dengan kendaraan yang melaju cepat. Bahkan teramat cepat, jadi pilihan.
Dan saya menjadi bagian anak-anak nakal itu.
Stasiun Jakarta Kota yang dibangun pada 1870 dan kembali dibuka pada tahun 1929 itu, memang menjadi titik awal perjalanan kami pulang kantor menuju rumah. Saya satu dari satu juta pengguna kereta listrik yang kerap bertolak dari Stasiun Jakarta Kota setiap hari. Modernisasi terlihat di sejumlah titik bangunan yang sejak tahun 1993 dijadikan Cagar Budaya oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui surat keputusan Gubernur DKI Jakarta no. 475 itu.
Semangat kesederhanaan adalah jalan terpendek menuju kecantikan yang dipegag Frans Johan Louwrens Ghijsels sudah pudar. Ghijsels adalah arsitek Belanda kelahiran Tulungagung 8 September 1882 yang bersama teman-temannya di Algemeen Ingenieur Architectenbureau atau biro arsitek merencang Batavia BOS atau Bataviasche Ooster Spoorweg Maatschapij (Maskapai Angkutan Kereta Api Batavia Timur), tempat di mana saya dan ribuan pengguna kereta listrik sekarang menanti kepastian kedatangan kereta kami.
Papan petunjuk posisi kereta listrik memang mengabarkan di mana kereta kami berada. Namun suara parau lelaki melalui pelantang berkali-kali mengabarkan hal sebaliknya. Bahkan, permintaan maaf berkali-kali kami dengar. Kami berada dalam ketidakpastian. Saya mulai tak nyaman. Mungkin dalam suasana ini, saya tidak sendirian. Ada ribuan orang dengan tas punggung di dada dan masker warna-warni berdiri dalam emosi yang membuat kami tampak bodoh.
Saya membuka gawai. Mencoba mengatasi emosi dengan mendengarkan lagu-lagu Gregory Alan Isakov, musisi kelahiran Johannesburg, Afrika Selatan itu. Saya ingin menyelamatkan diri.
***
Selasa, 3 Oktober 2017, sekira pukul 07.40 wib, kereta listrik dengan nomor 1507 tujuan Bogor – Angke anjlok di sekitaran Stasiun Manggarai. Roda belakang mengarah ke Cikini. Roda depan mengarah ke Sudirman. Jelas, ini dua arah yang sangat berbeda. Foto anjloknya kereta listrik menjadi viral di media sosial, termasuk grup percakapan digital kami.
Proses evakuasi dan perbaikan persinyalan yang memakan waktu cukup lama, berdampak panjang. Bahkan sampai malam, jadwal kereta listrik masih terganggu. Tidak tepat waktu.
Saya menyaksikan proses evakuasi kereta listrik dari televisi di kantor. Melihat dari jauh dan berdoa, agar evakuasi segera selesai, dan jadwal kereta listrik kembali normal. Karena malam ini, saya ada janji sama istri, akan menemani berbelanja kebutuhan anak lelaki kami. Saya tidak ingin gagal memenuhi janji ini.
Tiba-tiba layar gawai menyala. Nama istri muncul di layar. Saat saya buka, ia mengabarkan peristiwa anjloknya kereta listrik yang dia lihat di televisi. Hal yang sama, yang juga saya lihat di televisi.
“Manggarai anjlok” begitu kabarnya.
Saya jawab, “Iya tadi jam 8,”. “Sekarang sudah lancar?” tanyanya.
“Kata teman-teman sih sudah lancar. Mungkin sedikit tertahan. Tapi semoga tidak,” kata saya.
“Amin,” jawabnya.
***
Sekitar pukul 19.00 wib, di Stasiun Jakarta Kota, kereta listrik tujuan Bekasi belum juga terlihat di jalur 10, 11 dan jalur 12. Pun dengan kereta tujuan Bogor. Kami makin tak sabar. Saya pun demikian. Papan informasi itu tengah berbohong kepada kami. Album dari Gregory bertajuk The Weatherman sudah habis saya putar. Artinya, saya sudah menanti kereta listrik sekira 44 menit 50 detik.
Suara parau lelaki di pelantang kembali terdengar. Bukan mengabarkan posisi kereta. Sekali lagi, dia meminta maaf kepada kami atas ketidaknyamanan ini. Dari balik masker, saya hanya bisa mengumpat, “Sialan!”
Di saat yang sama, saya bersumpah, semoga arwah kerbau yang kepalanya ditanam oleh Gubernur Jendral jhr. A.C.D de Graeff yang berkuasa pada Hindia Belanda dari 1926-1931 menghantui pengelola moda transportasi ini.
Saya menghubungi istri. Mengabarkan bahwa kereta listrik terlambat lagi. Janji menemaninya berbelanja kembali tidak tunai. Laki-laki macam apa saya ini. Suami seperti apa yang kerap tidak bisa menunaikan janjinya. Dasar kereta listrik sialan. Sejenak, saya teringat Iwan Fals. Teringat lagu berjudul Kereta Tiba Pukul Berapa.
Sekira pukul 19.25 wib, kereta listrik kami tiba di Stasiun Jakarta Kota. Kami yang sudah menunggu di jalur 11 harus menjadi liar dan ganas saat pintu kereta terbuka. Bahkan ketika pintu belum terbuka sempurna. Berebut kursi bukan saja milik politisi dan pejabat tinggi. Bahkan kami yang warga biasa ini pun berebut kursi atas nama kenyamanan.
Saya mengalah. Saya menjadi bagian orang yang tak mau ikut berebut. Beradu sikut dan badan untuk sekedar menikmati tidur yang sebentar dan kurang paripurna. Kerja di ibukota memang mengubah kambing menjadi serigala. Mengubah burung perkutut menjadi rajawali. Bahkan teman satu kantor, Bambang Hadi Purwanto, rela berjalan cepat, jauh lebih cepat dari teman-teman yang lain dari Museum BI ke Stasiun Jakarta Kota hanya untuk bisa mendapatkan tempat duduk di kereta listrik. Hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Sebelum dia pindah rumah dari Jalan Kramat, Jakarta Pusat ke Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Bambang Hadi Purwanto yang mula mengirim gambar anjloknya kereta listrik ke grup percakapan digital itu. Pukul 8.46 wib, Bambang Hadi Purwanto yang juga wartawan senior di DAAI TV Indonesia mengabarkan bahwa ada kereta listrik anjlok. Dia mengejek kami yang sore nanti pulang menggunakan moda transportasi itu. Sementara di hari yang sama, dia harus pergi ke Biak untuk liputan di pulau seluas 1.904 kilometer per segi itu. Sungguh terpuji.
***
Dua belas ribu kilometer dari Jakarta, pada waktu yang hampir bersamaan, Pemerintah Wilayah Catalonia mengklaim bahwa 90,9 persen pemilih dalam referendum kemerdekaan memilih untuk merdeka dari Spanyol. Referendum ini diwarnai dengan kerusuhan antara pemilih dan polisi anti huru-hara yang mengakibatkan 844 orang terluka.
“Nanti klub Barcelona bagaimana ya?” kata Romy, teman satu kantor yang biasa turun di Stasiun Cakung itu.
“Saya tidak ada urusan dengan Barcelona, mas. Yang penting Real Madrid juara,” jawab saya singkat.
Dia lantas meneruskan membaca berita melalui gawainya. Maskernya mulai kendur. Orang-orang mulai mendesak tubuh kami. Jarak tas kami dengan wajah orang yang duduk di depan kami tidak sampai sejengkal. Senggol sedikit, tas kami sudah kena ke muka orang di depan kami.
“Kami kaum masker warna-warni, seperti pelangi. Juga kaum tas punggung yang kami letakkan di dada, adalah kaum paling sabar di dunia, untuk saat ini”
Saya memejamkan mata sebentar. Membayangkan wajah masam istri karena janji yang kembali batal. Saya membayangkan teh sekarlangit yang sudah dingin. Saya membayangkan anak lelaki kami, Rakai Temahan Akkaru sudah pulas memeluk guling baunya itu. Saat saya membuka mata, saya hanya bisa mencaci maki kereta listrik yang masih tertahan di Stasiun Juanda. Sementara, waktu sudah menujukkan pukul 19.45 wib. Waktu yang seharusnya membuat saya sudah berada di rumah, menikmati segelas teh panas dan bermain dengan bocah lelaki yang kini berusia 20 bulan itu.
“Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini,” suara parau lelaki lewat pelantang di gerbong kereta listrik. Berkali-kali dia minta maaf. Berkali-kali diulangi. Berkali-kali pun kami mencaci. Orang-orang sudah habis rasa kecewanya. Pengguna kereta listrik tujuan Jakarta – Bekasi paling sering mendengar kalimat pengulangan itu. Belum rampungnya double track jalur kereta api jarak jauh menjadi satu alasan. Di luar itu, tentu masih banyak lagi persoalan di kereta api kita ini.
Saya hanya bisa membuka gawai, berharap ada kabar dari istri.
***
Sekira pukul 20.30 wib, kereta yang saya tumpangi baru masuk Jatinegara. Jadi sekira 45 menit, kereta baru melewati 4 stasiun. Sungguh rentang waktu yang sangat lama. Tak aneh jika jendela gerbong kereta listrik terpaksa dibuka. Pendingin ruangan yang berada di titik tengah kedua pintu, tak cukup membuat penumpang nyaman dan segar. Caci maki sudah seperti makan malam yang terlambat bagi kami.
Saya dan Romy masih saja berdiri tanpa bisa menggeser tubuh sedikit pun. Tak hanya kami yang mengalami hal itu. Ratusan orang di dalam kereta yang sama dengan kami pun, pasti mengalami hal serupa. Jadi, kami bukan satu-satunya penumpang “terkutuk” yang menahan keluh kesah di dalam kereta yang lebih pas jika disebut keong.
Di stasiun yang berdiri sejak 1910 ini, penumpang sudah menutup telinga semua. Raungan pelantang yang mengabarkan untuk tidak berdesak-desakan dan menunggu kereta berikutnya pun sudah dianggap angin lalu. Di stasiun yang dirancang arsitek Ir. S. Snuyff, kepala sementara Biro Perancang Departemen Pekerjaan Umum itu, saya dan Romy kembali terdesak. Saya tak ingat lagi, sudah berapakali mencoba menahan dorongan penumpang-penumpang yang berada di sekitar saya. Berkali-kali mencoba, tapi tetap gagal menahan.
Dan saya pasrah terdorong sampai ke tengah gerbong yang sudah tidak dapat kesejukan dari pendingin ruangan itu. Beruntung, saya membawa tas punggung yang saya letakkan di dada. Lumayan untuk menahan tubuh berkeringat orang di depan saya.
Lelaki tua berkumis tipis dan berkacamata tebal di samping kiri saya mencoba sekuat tenaga menahan himpitan dua tubuh lelaki besar di depan dan belakangnya. Keringat tipis membasahi wajah yang mulai keriput itu. Dari bahasa tubuhnya, dia terlihat marah dengan dua lelaki yang terus menghimpitnya. Saya ingin membantunya. Tapi saya juga tak bisa bergerak. Saya tak berdaya. Saya hanya bisa melihat lelaki tua itu kesakitan.
Betapa egoisnya penumpang-penumpang kereta listrik ini. Atau kereta listrik ini yang mengubah kita menjadi begitu acuh? Gawai di dalam tas bergetar. Saya tak bisa membuka tas di dada. Saya biarkan bergetar beberapa saat. Tangan saya susah bergerak. Bahkan untuk sedikit mengambil udara “segar”, saya harus menurunkan sedikit masker saya.
Saya yakin, itu dari istri saya. Ia pasti tak sabar menunggu kedatangan suaminya pulang kerja. Ia ingin menemani suaminya makan malam. Ia pasti sudah menyeduh segelas teh hangat yang sedikit manis, dan meletakkan di meja makan.
Romy turun di Stasiun Cakung. Dan di gerbong yang kami naiki, hanya terlihat tiga orang, termasuk teman saya itu yang bergerak turun. Saya lihat, Romy cukup kesusahan membelah penumpang yang sudah habis tingkat kepeduliannya itu. Beberapakali, Romy terlihat menepuk bahu orang yang ada di depannya untuk memberi sedikit, ya sedikit saja, jalan.
***
Sekira pukul 21.20 wib, kereta listrik sampai di Stasiun Kranji, tempat di mana saya merasa lega karena bisa keluar dari tubuh besi sialan itu. Buru-buru saya keluar, tepatnya ikut arus penumpang yang mendorong penumpang lain di depannya. Sampai di tubir kereta listrik, saya sekali lagi melihat lelaki setengah baya itu sedang marah-marah kepada seorang lelaki yang lebih muda usianya. Saya yakin, itu lelaki sial yang telah menghimpit lelaki setengah baya itu.
Orang-orang yang turun dari kereta acuh melihat kejadian itu. Tak ada yang berusaha melerai kejadian itu. pun saya. Saya hanya melihat dari jauh. Berusaha ingin mendekat, tapi rindu bermain sama anak lelaki dan bercerita dengan istri mengalahkan rasa itu.
Kereta listrik ini benar-benar telah mengubah saya, mungkin juga mengubah jutaan pengguna kereta listrik yang lain. Terkadang, kami begitu acuh pada peristiwa-peristiwa di sekitar. Terkadang, kami cukup perduli dengan remeh-temeh di dalam gerbong, seperti memberikan tempat duduk untuk perempuan yang sengaja atau tidak sengaja berdiri di depan kita dengan muka lelah. Entah lelah bekerja atau lelah menaiki anak tangga di sejumlah stasiun.
***
Di kamar, saya melihat istri dan anak lelaki saya pulas mendekap guling masing-masing. Di timeline media sosial masih ramai membicarakan masalah kereta listrik yang kerap menghadirkan peristiwa yang membuat kami tampak begitu bodoh.
“Kereta dan Kebodohan Kita” ditulis oleh:
Dony P. Herwanto
Documentary Maker, Journalist.