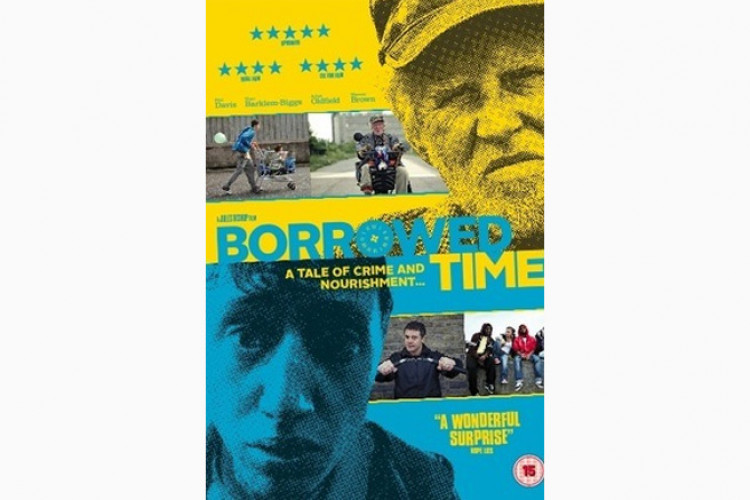Seni Kolaboratif bersama Wok the Rock
Muhammad Hilmi (H) berbincang dengan aktifis budaya Wok the Rock (W).
by Ken Jenie





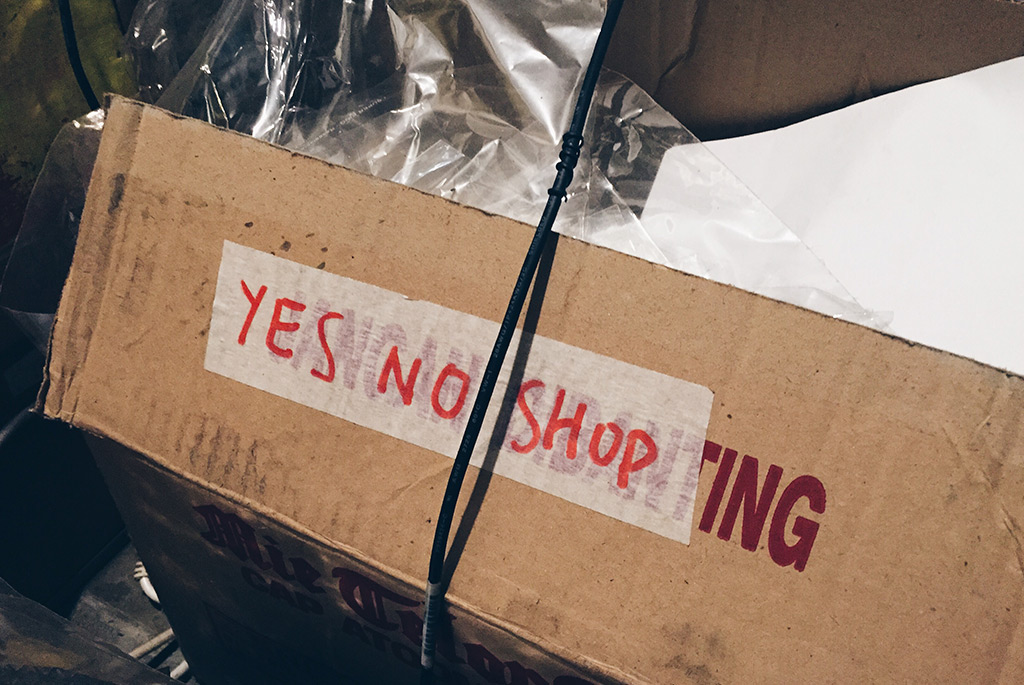







H
Bagaimana ketertarikan terhadap bidang seni tumbuh pada diri Mas Wok?
W
Sejak kecil, bahkan bisa dibilang bahwa saya dilahirkan dengan bakat pada bidang seni (tertawa). Tapi memang sedari kecil, mungkin mulai dari balita, saya suka menggambar. Bapak saya terutama yang mengenali bakat tersebut, meskipun saya saat itu belum paham apa itu seni sebenarnya. Saat sekolah, beliau selalu berkata pada guru seni saya, “Tolong beri perhatian khusus pada anak saya”. Dengan begitu, mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga SMP, saya selalu mendapat atensi lebih dari pengajar pelajaran seni.
Melalui “pengkondisian” itu, dan memang kebetulan saya menikmati proses berkesenian, saya lalu menjadikan bidang ini sebagai aktivitas utama saya, yang juga berperan sekaligus sebagai hobi. Di rumah saya dulu, ada satu bagian dinding selebar 4 meter dengan cat hitam, saya dibekali kapur warna-warni untuk mencorat-coret dinding tersebut. Jadilah saya banyak menghabiskan waktu untuk menggambar.
Untuk musik, saya mulai mendengar dan menikmatinya secara mendalam itu dari kelas 3 SD. Musik yang saat itu saya dengarkan adalah tipikal soundtrack-soundtrack anime. Ketika Bapak saya ada keperluan ke luar kota, saya selalu menitip pada beliau untuk membelikan saya kaset soundtrack anime, seperti Voltus atau soundtrack film silat Mandarin. Ketika saya masuk kelas 4 SD, kakak saya yang paling tua masuk SMP dan mulai mengenali musik barat. Maka di rumah saya kemudian mulai bisa terdengar lagu Duran Duran, dan semacamnya. Saya mulai membeli kaset saya sendiri, selain Duran Duran, saya juga beli Twisted Sisters, ya.. seputaran musik yang populer ketika itu.
H
Ketertarikan terhadap seni ini terus berlanjut hingga Mas Wok mengambil kuliah di Institus Seni Indonesia Jogja?
W
Ada cerita seru disini. Jadi saat saya kelas 6 SD, ada seorang tetangga yang ditaksir oleh kakak perempuan saya. Untuk keperluan pendekatan, saya kemudian sering diajak bermain bersama tetangga tersebut. Kebetulan tetangga saya tadi kuliah di ISI, dengan jurusan Desain Grafis. Melihat saya memiliki bakat dan ketertarikan di dunia seni, kakak saya sering melibatkan saya dalam obrolan bersama tetangga saya tadi. Dari obrolan bersama tersebut, saya lalu tahu bahwa ada kampus yang secara spesifik mengajarkan tentang seni. Tetangga saya tadi kemudian memotivasi saya untuk kuliah di ISI. Ketika saya bercerita kepadanya bahwa saya lemah pada teknik gambar realis, dan lebih tertarik untuk menggambar artwork seperti kover album Iron Maiden, dan semacamnya, tetangga tersebut justru semakin antusias untuk menganjurkan saya untuk kuliah di kampusnya sambil berkata, “Kalo di jurusanku, kita kerjaannya bikin kover untuk kaset!”. Saat itu juga, dengan usia masih 10-12 tahun, saya langsung yakin dan mantap bahwa saya akan kuliah desain grafis nantinya.
Keinginan tersebut saya ceritakan kepada Bapak saya. Bahwa saya selepas SMA akan mengambil jurusan desain grafis, sembari berkata bahwa cita-cita saya saat dewasa nanti adalah menjadi perancang desain untuk kover album musik (tertawa). Sangat spesifik.
Karena Bapak saya adalah seorang agen toko buku, maka saya menambahkan detail pada cita-cita saya tadi. “Yah, setidaknya kalau tidak bisa jadi desainer untuk kover album, saya akan bisa jadi desainer untuk kover buku atau majalah”. Atau istilahnya jaman dahulu untuk profesi ini adalah redaktur artistik. Sejak dahulu, saya sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menjadi pelukis, atau seniman fine arts.
Cita-cita ini menjadi semacam obsesi dari SMP hingga SMA. Yang ada di kepala adalah keinginan untuk cepat lulus. Ternyata setelah lulus SMA daftar di ISI tidak diterima (tertawa). Mau daftar ke ITB, tidak diperbolehkan oleh orang tua, karena alasan bahwa Bandung terlalu jauh dari Madiun. Akhirnya tahun itu saya mengambil kuliah D3 di UGM dengan jurusan periklanan. Tahun depannya, saya mendaftar lagi di ISI, baru saya diterima.
H
Bagaimana pengaruh masa kuliah ini pada karakter Mas Wok sebagai seniman?
W
Nah, ini masih ada hubungannya dengan masa saya kuliah D3 Periklanan. Sebenarnya saya cukup menikmati masa kuliah disana, meski hanya singkat temponya. Saya sangat senang mempelajari mata kuliah ilmu komunikasi, hingga psikologi persepsi. Dan itu cukup membekas dan berpengaruh pada ketika saya kuliah desain kemudian hari.
Pada masa kuliah desain, sempat terpikir untuk pindah ke jurusan seni murni. Karena melihat anak-anak seni murni lebih sosial, lebih sering berkegiatan, seru. Saya masuk ISI pada tahun 1995, dan itu adalah era dimana mahasiswa seni-nya sedang memiliki gairah besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Mereka ingin memberi tawaran baru pada seni Indonesia, sesuatu di luar dari apa yang telah dijalankan oleh sosok seperti Jim Supangkat. Ada nama-nama seperti S. Teddy, Ugo Untoro, Ade Dharmawan, Soni Irawan, Bob Sick, Yustoni Volunteero, Venzha, yang meski masih sepantaran dengan saya, tapi menjadi senior di kampus, sedang bergerilya dalam menciptakan movement kesenian. Itu sangat menarik perhatian saya.
Sebagai mahasiswa desain, saya sangat menikmati pelajarannya, tapi secara sosial, saya tidak enjoy jadi mahasiswa desain yang cenderung pragmatis. Untungnya, ada kakak kelas mahasiswa desain yang meyakinkan saya supaya lanjut terus di jurusan desain. Bahwa saya akan lebih belajar banyak pada jurusan ini, desain cakupannya luas, ada fotografi, animasi, juga komunikasi. Misalnya saya ingin bersosialisasi dengan anak seni, itu bisa dilakukan tanpa harus pindah major.
Saya kemudian semakin yakin dengan jurusan desain ketika membaca buku Barbara Kruger, Fluxus, hingga Dada dan melihat bahwa seniman-seniman ini sangat multidimensi dalam berkarya. Persis seperti pendekatan desain komunikasi visual. Bahkan mereka bisa menciptakan satu genre seni tersendiri dengan gaya tersebut. Termotivasi dari pendekatan seniman-seniman tadi, saya lalu memantapkan diri untuk menjadi mahasiswa desain yang bercita-cita menjadi seorang seniman.
H
Unsur kolaboratif cukup kuat pada setiap karya Mas Wok, dimana banyak karya Mas Wok seperti berdialog dengan penikmatnya, darimana karakter ini muncul?
W
Mungkin, karakter ini lahir ketika saya mulai aktif di scene punk. Itu sekitar tahun 1996. Saya tertarik dengan sub-kultur ini awalnya karena musiknya, ini membuat saya kemudian dekat dengan anak-anak punk Jogja yang saat itu masih cukup sedikit. Movement adalah salah satu bahasan wajib diantara kami saat itu. Saya belajar hidup komunal bersama mereka, kami sering ngumpul, ngobrol, bikin sesuatu bersama-sama. Belajar DIY ethics juga bersama mereka. Dari situ, saya paham bahwa kita tidak bisa memulai movement sendirian, harus dilakukan bersama-sama. Ditambah saat itu eranya masih orde baru, segalanya masih dibatasi.
Saya lalu dibawa pada pemahaman bahwa DIY tak selamanya harus dimaknai secara literal, kita tak perlu benar-benar sendirian dalam menerapkan etos DIY ini, justru kita berjalan bersama-sama, asal tidak bergantung pada struktur kelembagaan yang besar. Ini mungkin mula lahirnya elemen kolaboratif pada karya-karya saya.
Saat itu, saya juga tinggal pada rumah kos yang berisi fotografer-fotografer muda dengan keinginan untuk menciptakan skena fotografi sendiri. Rumah kos tersebut pada dasarnya adalah bekas Mes Auri, maka dari itu kami sering menyebutnya sebagai “Mes”. Karya fotografi dari anak-anak Mes ini biasanya susah masuk ke galeri-galeri foto pada umumnya, karena pendekatan mereka yang berkebalikan dengan teknik foto konvensional. Kami sering mengalami penolakan-penolakan seperti, “Foto kok kayak gini?” “Fotografer kok tidak memotret?”. Di sisi lain, karya teman-teman tadi juga tidak dianggap di scene seni rupa yang saat itu belum melihat fotografi sebagai salah satu bentuk seni rupa. Tak pernah ada ajakan untuk ikut pameran. Jalan keluarnya, kami bikin pameran sendiri.
Melihat bagaimana saya bersama teman-teman di scene punk sering mempraktekkan etos DIY dalam tiap aktivitas kami, anak-anak Mes terinspirasi untuk menerapkan semangat ini pada gerakan mereka. Saya lantas diajak untuk menciptakan sebuah galeri dengan semangat DIY tadi. Ruang tamu Mes lalu kami sulap menjadi galeri, pencahayaan dan segala detail kami kerjakan sendiri. Lalu berjalanlah pameran disana, dimana kami belajar mengelola pameran seni, membangun koneksi, termasuk salah satunya adalah berkenalan dengan teman-teman di Galeri Jurnalistik Antara. Di Galeri Antara, kami berhubungan dengan Mas Yudhi Surjoatmodjo, kebetulan beliau saat itu concern pada genre “fotografi lain-lain”, yakni karya fotografi diluar fotografi jurnalistik, dokumenter atau salon, sangat pas dengan karakter karya kami. Dari sini lantas semangat komunal mulai mengakar pada diri saya.
Meskipun sebenarnya, sejak tahun 1997-2007, karya saya formatnya masih single object photography, atau video. Belum kolaboratif, dimana saya mengerjakan karya saya sendirian. Tapi secara sosial, saya selalu bergerak secara komunal. Semua dilakukan secara kolektif.
Saya memiliki banyak ketertarikan, ada desain, seni, movement, dan musik. Awalnya keempat elemen tersebut berjalan terpisah. Jadi saya mengerjakan desain, kadang bikin poster untuk acara yang saya cetak sendiri, kadang membantu band teman untuk membuat artworknya, semua saya jalani secara terpisah satu sama lain. Tapi saya cukup puas, saya merasa bahwa saat itu saya telah menghidupi mimpi saya di usia yang masih relatif cukup muda (tertawa).
Tapi pada tahun 2007, saya mulai kelelahan. Capek juga rasanya melakukan empat aktivitas sekaligus yang tak ada benang merahnya satu sama lain. Lalu saya berpikir bahwa akan enak sepertinya untuk membuat sebuah karya yang mampu menggerakkan keempat elemen tadi secara bersamaan. Saya mengawalinya dengan project “Burn Your Idol” yang menggabungkan elemen desain grafis, seni, musik hingga internet dan bisa dikerjakan secara kolektif. Ini mungkin titik tolaknya.
H
Mas Wok bisa dibilang sebagai seniman yang mengangkat gaya baru pada seni dan fotografi, seperti apa resistansi yang dihadapi Mas Wok ketika itu?
W
Resistansinya cukup keras. Suatu ketika, atas undangan dan kurasi Mas Yudi, MES 56 diberi kesempatan pameran di Galeri Antara, yang dikenal sebagai galeri foto jurnalistik. Maka jadilah kami dibantai, dibilang menyalahi prinsip fotografi, dan semacamnya.
Tapi itu bukan hal baru. Di Jogja pun, para fotografer jurnalistik dan salon yang datang juga hampir pasti menolak karya yang kami pamerkan untuk disebut sebagai karya fotografi. Kami dibilang keliru, bahwa kami seenaknya saja dalam “merusak” konsep fotografi. Masak, fotografi kok pakai scanner? Screencap? Hal-hal seperti itu kami hadapi. Tapi diantara sekian celaan tadi, biasanya ada satu-dua orang yang sebenarnya memahami konsep yang kami angkat. Salah satunya adalah seorang fotografer bernama Layung Buworo. Meski ruang lingkup kerjanya adalah fotografi klasik, beliau memahami dan bahkan mau membantu untuk menjelaskan kepada khalayak fotografi tentang apa sebenarnya makna dari karya kami. Meski dampaknya juga tak sedemikian besar, karena jumlahnya tak sepadan.
Intinya sebenarnya adalah untuk melakukannya bersama-sama. Juga mungkin untuk menjalaninya secara sporadis, dalam artian kita bisa melakukannya secara kecil-kecilan, tapi kita melakukannya tanpa terlalu banyak pertimbangan. Seperti ketika dulu kami awal-awal di Mes juga setiap bikin pameran yang datang selalu sedikit, tapi kami terus melakukannya secara kontinyu, sembari membangun jaringan.
Contohnya adalah ketika kami menjalin hubungan dengan Mas Yudi yang saat itu menjabat sebagai kurator Galeri Antara. Ini cukup penting bagi sejarah MES 56. Kebetulan beliau memiliki ketertarikan pada apa yang kami praktekkan di MES. Sebagai anak baru, kami kemudian menghampiri beliau, setelah sebelumnya berkenalan via email. Sehabis dari Jakarta, kami juga menjalin hubungan dengan teman-teman di Bandung, saat itu dengan Gustaff Harriman Iskandar dari Trolley Magazine yang memperkenalkan kami dengan Tarlen dari Tobucil dan anak-anak Ripple. Persis seperti praktek di scene punk, misalnya ada pergerakan punk di Malang, kami akan berkunjung ke sana, sambil berbagi referensi, kaset, hingga zine. Juga membicarakan tentang kemungkinan barter gigs dimana kami mengundang mereka ke Jogja, dan kami bisa manggung di Malang. Ini berjalan ke segala arah, termasuk kami main ke Jakarta, Kediri, Surabaya. Di Mes, saat itu yang sering bergerilya biasanya saya, Angki Purbandono, Wimo Ambala Bayang dan Edwin Roseno.
H
Sekian tahun setelah menjadi salah satu penggerak berbagai movement alternatif, apakah masih ada gairah untuk menciptakan pergerakan baru lagi?
W
Oh iya.
H
Kalau sekarang, apa yang coba dilawan?
W
Mungkin kalau sekarang, saya ingin melawan segala kemudahan dalam mendapatkan informasi, karena saya merasa bahwa dengan segala macam kemudahan itu, orang cenderung jadi manja. Saya ingin melawan kemanjaan tersebut dengan menciptakan platform alternatif baru. Agak sulit untuk menjelaskan konsepnya, karena saya sendiri masih mencari cara bagaimana tepatnya perlawanan ini dilakukan. Yang jelas, saya selalu memiliki keinginan untuk meruntuhkan stagnasi, terutama pada bidang yang saya tekuni.
Dalam sebuah obrolan dengan Antariksa, seorang peneliti dari Kunci Cultural Studies Center, ada sebuah poin penting yang saya rasa perlu digarisbawahi. Bahwa ketika sebuah hal sudah mencapai titik tertingginya, maka kita harus siap untuk bergerak ke bawah tanah lagi. Supaya apa yang kita lakukan tak lantas berkembang menjadi sebuah rezim yang tak bisa disentuh oleh anak-anak mudanya. Ini saya rasa adalah prinsip yang cukup penting. Kesadaran ini mulai disadari oleh teman-teman di Mes dan kami mencoba untuk kembali ke grass root lagi dengan nurturing pengetahuan yang kami miliki kepada generasi muda. Memicu regenerasi.
Tapi ini hal yang cukup sulit untuk dilakukan sebenarnya. Anak-anak muda sekarang, terutama di Jogja, mentalitasnya sudah sangat berbeda arahnya. Inisiatif-inisiatif baru berkurang. Mungkin ini ada hubungannya dengan segala kemudahan yang ada diantara mereka. Jadinya budaya yang tumbuh adalah konsumtif, dan kapitalistik. Dulu misalnya, ketika kita memiliki kesamaan minat, biasanya kita akan dengan mudah saling membantu dalam proyek kita masing-masing, bahkan banyak diantaranya yang bekerja secara sukarela. Sekarang, agak sulit untuk menemukan relasi yang seperti itu. Meski mereka tak menyatakan penolakannya secara langsung ketika dimintai bantuan, tapi ketika sudah tergabung, mereka mengerjakannya secara sekenanya saja. Ini justru kontraproduktif. Dan sangat disayangkan sekali. Atau bisa jadi, mungkin saya sendiri yang kesulitan membaca hal-hal baru yang dilakukan oleh anak muda sekarang.
H
Sebagai salah satu bagian dari gerakan seni kontemporer di Indonesia, bagaimana Mas Wok melihat apa yang terjadi sekarang?
W
Yang pasti, seni rupa kontemporer Indonesia arahnya sudah bagus. Tapi ada sedikit masalah ketika pasar seni yang tumbuh pada seni kontemporer lokal kemudian terlalu berpengaruh dalam proses kreatif para senimannya. Keadaan yang demikian akan memperlambat dan menumpulkan perkembangan seni kontemporer itu sendiri. Energi dan keberagaman yang menjadi motor dari perkembangan seni rupa kontemporer akan terkikis oleh pengaruh pasar yang demikian. Seniman akan cenderung nihil dalam hal progresivitas. Ini merupakan masalah.
Saya merasa bahwa sepertinya kurang tepat untuk membiarkan seorang mahasiswa seni tiba-tiba terjun di pasar seni. Ini tidak bagus karena mereka akan kehilangan progresivitas mereka.
H
Jadi, ada dua sisi mata pisau dari eksistensi pasar seni. Satu, mereka bisa menjadi motivasi tersendiri bagi seniman, tapi kalau terlalu penetratif, mereka bisa membuat para seniman menjadi hanya menghasilkan karya “pesanan” dari kolektor?
W
Bisa dibilang begitu, karena di pasar biasanya ada tren atau gaya tertentu yang akan lebih laku dibanding style lainnya. Ini membuat seniman cenderung “main aman” dengan menggunakan gaya yang sudah terbukti laku daripada menjelajahi gaya lain yang lebih sesuai dengan personalnya. Mereka jadi ragu-ragu untuk bereksperimen dalam proses berkarya. Bagi saya, keragu-raguan ini yang harusnya dihilangkan. Karena nyatanya kalau berbicara dalam konteks pasar, para kolektor pun sekarang sudah banyak yang memahami esensi gagasan pada karya yang tak bermain aman dengan menuruti sepenuhnya selera pasar.
Platform seperti Indoartnow adalah salah satu contoh sekaligus wadah bagi seniman yang berada diluar aktivitas pasar. Dan inisiatif semacam sebenarnya mulai banyak dilakukan. Bahkan ArtJog sebagai artfair pun sudah mulai berani menampilkan karya-karya yang sifatnya progresif. Yang penting adalah keberanian pada diri seniman, untuk bisa bergerak melawan arus pasar.
H
Saya sempat membaca sebuah komentar dari Mas Heri Pemad mengenai bagaimana selera pasar sebenarnya tidak menurun, tapi justru jumlah karya yang berkualitaslah yang menurun secara kuantitas…
W
Saya tidak sepakat dengan pendapat ini. Karena pendapat tersebut seperti melimpahkan semua kesalahan pada punggung seniman. Padahal tidak begitu keadaannya. Saya percaya bahwa tanpa adanya pasar sekalipun, seniman bisa hidup. Apalagi di Jogja dengan living cost yang affordable itu. Jadi masih harus dicari alasan sebenarnya dari kenapa pasar jadi lesu. Itu urusan orang-orang pasar untuk membuat area itu jadi bergairah kembali, jangan menyalahkan senimannya dengan alasan bahwa kualitas karya menurun. Saya melihat sendiri bagaimana seniman yang telah teruji kualitasnya, gagasan dalam karyanya masih terus terjaga, terlepas dari apa yang terjadi di pasar. Analisanya harusnya begini, kenapa sekarang para kolektor jadi mengurangi anggaran belanja seninya? Mungkin ini ada hubungannya dengan kondisi perekonomian global.
H
Tentang Jogja sendiri, apa sebenarnya yang membuat kesenian bisa sedemikian hidup disana? Dan darimana datangnya kedalaman dari karya-karya yang datang dari Jogja?
W
Karena kehidupan seni budaya kuat dan mengakar disana. Kita sama-sama tahu bahwa kesenian tradisional sudah menjadi seperti separuh bagian dari kehidupan masyarakat disana. Kondisi geografisnya yang kecil, ini berpengaruh pada bagaimana semua jadi lebih dekat satu sama lain. Selalu ada acara, event dan berbagai aktivitas kreatif untuk semua yang hidup disana.
Posisi Jogja sebagai salah satu tempat wisata utama bagi turis luar negeri juga cukup berdampak. Dimana dari sedemikian banyak turis pasti ada seniman, peneliti, hingga cultural researcher yang kemudian mereka akan bertemu dengan seniman lokal.
Saya tidak bisa memberi jawaban yang spesifik untuk pertanyaan ini. Tapi mungkin ini karena di Jogja kondisi sosialnya sangat berdekatan dengan aktivitas budayanya. Eksistensi komunitas seni yang cukup beragam disana, mulai dari yang akademis seperti ISI, atau yang seperti Kunci ini membuat kesenian disana berkembang dengan sangat dinamis. Dengan demikian banyak ruang yang bisa dijelajahi oleh seniman disana untuk berproses.
Secara kota, Jogja juga bukan kota industri. Kebanyakan ke Jogja untuk belajar, untuk kuliah. Tak terlalu banyak orang yang berangkat ke Jogja untuk bekerja. Ini saya rasa juga membentuk budaya kreatif Jogja lebih dinamis.
H
Di sisi lain, tak terlalu jauh dari Jogja, iklim kesenian di Jawa Timur sepertinya tak terlalu dibicarakan. Tahun 2015 diadakan Jatim Biennale, tapi tak terlalu terdengar gaungnya. Menurut Mas Wok, apakah hal ini karena karakter kota disana memang tak sesuai dengan kesenian?
W
Kota di Jawa Timur, terutama mungkin Surabaya adalah kota industri. Semua orang kesana untuk bekerja.
H
Jadi bagaimana sebenarnya posisi kesenian pada kota industri?
W
Saya rasa, dalam konteks kesenian di kota industri, apa yang dilakukan oleh ruangrupa sudah menyentuh ke area yang tepat. Mereka mampu membuat kesenian tumbuh pada kota yang sangat urban dan industrial. Poin utamanya mungkin disini adalah bahwa seni pada kota industri tidak bisa bergantung pada kesenian tradisional atau juga konvensional. Karena agak susah untuk menarik garis tengah antara kesenian konvensional dengan kehidupan urban. Hal ini bisa dilihat pada seberapa banyak pekerja di kota yang punya lukisan di rumahnya. Pasti angkanya sangat kecil. Lantas seni semacam apa yang dekat dengan kehidupan orang-orang di Surabaya atau Jakarta? Ruangrupa mampu menjawabnya dengan cara mereka sendiri. Misalnya dengan meme, atau dengan pendekatan desain grafis yang diwakilkan oleh tampilan kalender, packaging produk, atau representasi produk-produk populer lain yang memiliki nilai seni disana.
Menurut saya, Surabaya akan cenderung lebih cocok untuk mengambil inspirasi dari Jakarta ketimbang untuk belajar dari Jogja. Seandainya saja, mereka mengundang nama seperti Hafiz Rancajale dari Jakarta untuk menjadi kurator biennale mereka yang akan datang, sepertinya karya yang dihasilkan akan lebih menarik lagi. Kalau untuk scene seni Malang, saya tidak bisa bicara banyak, pasti kondisinya berbeda lagi. Bisa jadi Malang sedikit lebih mirip dengan Jogja karena mereka kota tujuan studi. Tapi untuk mengetahui konsep seni yang pas dengan Kota Malang, harus dilihat lagi bagaimana pola kehidupan masyarakatnya.
Seni konvensional seperti lukisan, dan semacamnya cocok di Jogja karena masyarakatnya hidup diantara kondisi yang sangat kuat secara budaya visual secara tradisi. Saya rasa, lebih banyak warga Jogja yang punya lukisan, atau setidaknya wayang di rumahnya ketimbang di Surabaya atau Malang. Pada umumnya, warga Jogja punya produk-produk seni budaya di rumah mereka masing-masing. Mungkin di kota lain justru penduduknya lebih banyak punya kaligrafi dibanding lukisan. Hal-hal seperti ini yang harus digali dan dipelajari untuk menemukan potensi seni dari berbagai kota di Indonesia.
H
Di tahun 2015, Mas Wok terpilih menjadi salah satu kurator Biennale Jogja, dimana pada acara tersebut Mas Wok mengangkat pendekatan seni yang cukup progresif. Apa sebenarnya Gagasan utama dari kuratorialnya?
W
Sebenarnya, banyak kalangan yang tidak terlalu menyukai event Biennale Jogja. Dimulai dari ketika didirikan Yayasan Biennale Yogyakarta, dimana mereka kemudian menginisiasi seri ekuator pada tahun 2011. Entah kenapa, sepertinya para seniman kurang menyukai dipakainya gagasan ekuator pada Biennale Jogja. Dua edisi Biennale Jogja 2011 dan 2013, ditampilkan karya-karya seni yang sebenarnya bagus, tapi sudah terlalu ‘biasa’ di Jogja. Rata-rata, seniman yang diundang adalah mereka yang namanya telah established di scene seni Jogja.
Pada giliran saya menjadi kurator Biennale Jogja, saya memiliki visi yang sederhana: saya ingin memberi wadah bagi seniman-seniman yang memiliki bentuk karya yang tidak konvensional. Jadi saya ingin Biennale Jogja 2015 adalah tempat bagi seniman yang berani membuat karya di luar konsep kontemporer itu sendiri. Memang tidak banyak. Tapi ada, dan mereka pada umumnya masih berusia muda. Sayangnya, seniman-seniman tersebut jarang sekali diundang pameran besar di Indonesia. Ketika saya menjadi kurator, ini saatnya bagi saya untuk menciptakan ajang bagi teman-teman seniman tadi dalam memamerkan karya yang berbeda tadi. Karena saya sendiri memahami definisi biennale adalah sebuah event seni yang memamerkan progress dari karya seniman dua tahun terakhir, dengan tambahan bahwa saya juga ingin menampilkan progress dalam konteks bentuk atau platform kuratorial yang lain dari biasanya. Saya mencoba berlari dari konsep kuratorial klasik yang bermainnya pada ranah white cube, karya dipasang di dinding, dengan sorot lampu. Dan kemudian menyesuaikannya dengan karya para seniman yang saya pilih.
Maka jadilah seperti itu. Konsep pamerannya semi-open space, dengan atap tapi tanpa dinding dan karya seninya tidak takut terhadap interaksi terhadap publik. Gedung yang saya pilih adalah Jogja National Museum, karena sesuai dengan kebutuhan saya. Secara arsitektur pas, juga tepat secara fungsi, karena ada beberapa komunitas yang bertempat disitu, seperti sekolah alternatif dari TK sampai SMA, ada toko DeMajors disana, juga kantor Jogja Hip Hop Foundation. Jadi meskipun ini ruang seni, publik sudah aware dengan tempat ini dan selalu ada aktivitas sosial disana. Ini sangat sesuai dengan konsep pameran seni yang interaktif dan berbasis aktivitas dan performance. Saya mengangkat art performance disini dengan sebuah misi khusus, yaitu untuk menampilkan karya multidisiplin dari line up seniman yang juga multidisiplin. Ada seniman yang datang dari latar belakang musik, teater, jurnalis, editor buku, arsitek, creative director biro iklan juga. Berbagai latar belakang tadi bekerja bersama dalam menciptakan proyek seni kolaboratif yang bisa dinikmati oleh publik secara kolaboratif pula. Jadi penonton datang dan menikmati karya seni sebagai sebuah kolektif, bukan secara individu.
Pengalaman menonton karya pun saya ubah, dari hanya melihat dan merenung, saya tantang publik untuk mengalami sendiri dan sekaligus menjadi bagian dari karya seni itu sendiri. Tapi dari pendekatan yang demikian, banyak kemudian yang menulis bahwa Biennale Jogja 2015 kemarin sepi secara karya. Tidak ada yang bisa dilihat. Ini sebenarnya tidak salah, karena karya di Biennale Jogja bukan untuk dilihat, tapi dialami. Dan ini sudah kami publikasikan pada setiap pengantar acara.
Segala perubahan pada konsep Biennale Jogja saya buat supaya ada pengalaman lain bagi semua yang menikmati pameran tersebut, baik untuk penonton maupun untuk sang seniman itu sendiri. Juga supaya ada suasana yang lebih guyub pada event tersebut. Intim tapi dirasakan secara kolektif, dan ini sangat Jogja banget sebenarnya.
Dari sisi proses pembuatan karya, saya juga mengambil arahan yang berbeda. Sebagai seniman yang berperan sebagai kurator, saya mengundang sesama seniman untuk bergabung pada project ini. Jadi tidak seperti kurator ke seniman yang top–down relasinya, lebih ke teman ke teman. Untuk menciptakan iklim berkesenian yang kolaboratif, saya mengadakan focus group discussion setiap bulan sekali, selama 6 bulan. Setiap kali bertemu, kami mendiskusikan tema, karya dan saling mengomentari karya rekan seniman. Supaya karya yang dihasilkan bisa saling bertautan satu sama lain sesuai dengan tema yang diangkat. Kolaborasi antar seniman pun kemudian berlangsung secara natural, satu seniman saling membantu dalam menciptakan karya. Saya bisa pastikan bahwa setiap seniman di Biennale Jogja 2015 memahami semua karya yang dipamerkan, beserta landasan pikirnya. Saya rasa belum banyak kurator yang melakukan ini. Karena sering saya menemukan beberapa seniman tak saling kenal, padahal sama-sama berpartisipasi pada sebuah pameran bersama. Ini agak ironis. Hal ini yang saya hindari di Biennale Jogja, bahkan dengan teman seniman Nigeria, kami selalu membangun komunikasi via internet.
Tantangan dari pendekatan pameran yang mengedepankan kolaborasi adalah munculnya konflik personal. Dan ini terjadi di Biennale Jogja 2015. Tapi hal seperti ini yang menguatkan karakter karya yang ditampilkan nantinya. Ketika terjadi konflik, saya hanya menengahi saja dengan mencari akar masalahnya. Penyelesaiannya adalah dengan mengangkatnya ke forum dan mendiskusikannya bersama-sama. Positifnya, semua seniman yang berpartisipasi bisa semakin dekat satu sama lain.
H
Jadi meski banyak yang mengkritik, begitulah konsep pameran yang ideal versi Mas Wok?
W
Iya. Setidaknya dalam pameran kemarin itu, saya berusaha untuk menawarkan konsep kuratorial baru untuk pameran yang melibatkan banyak seniman. Banyak yang bilang karyanya mirip satu sama lain, lalu masalahnya dimana kalau karyanya mirip? Toh tidak ada yang sama persis. Dengan nuansa yang mirip, itu berarti karyanya kohesif dan saling mengisi satu sama lain, seiring dengan tema besar yang saya angkat.
H
Beralih ke musik. Sebagai salah satu pelopor netlabel di Indonesia dengan Yes No Wave Music, bagaimana Mas Wok melihat netlabel sekarang banyak yang telah berhenti merilis karya, dan band-band lokal yang kini lebih memilih untuk merilis secara independen daripada bekerja bersama netlabel?
W
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat dasar pembentukan Yes No Wave Music. Yes No Wave Music didirikan sebagai lembaga non-profit. Jadi tidak ada sama sekali urusan dengan industri musik. Fokus utama kami ada pada budaya itu sendiri. Proyeksi label ini tentu berbeda dengan label lain yang bermain-main dengan industri. Misalnya ketika download rate-nya turun, itu sama sekali bukan masalah bagi kami. Karena kepentingannya adalah untuk penyebaran karya. Kami memposisikan musik yang kami rilis seperti karya seni. Misi kami persis seperti penyebaran budaya. Ketika sebuah karya telah kami sebarkan ke khalayak, maka misi kami telah selesai. Terserah pada pengunduh bagaimana cara mereka mengkonsumsi karya yang kami telah share. Bagi saya, Yes No Wave Music adalah sebuah galeri dimana musik didalamnya adalah karyanya. Semacam art repository untuk karya musik.
Saya sendiri menggunakan term “netlabel” sebenarnya tidak sengaja. Awalnya, positioning Yes No Wave Music adalah “Internet Based Record Label”, tapi setelah mempelajari lebih jauh, saya lalu paham dan mengadopsi konsep netlabel ini.
Ketika term “netlabel” ini kemudian berkembang dan banyak diadopsi oleh pelaku di musik lokal, kami di Yes No Wave Music hanya berfokus untuk mengikuti perkembangan teknologinya saja. Jadi ketika tren netlabel ini gagal berkembang, perhatian kami sama sekali tidak disana. Perhatian kami justru ada pada bagaimana bila nantinya internet akan semakin ketat sensornya, terutama pada musik download yang sering jadi rancu dengan pembajakan, apa langkah yang bisa kami ambil ketika kondisi internet demikian di masa yang akan datang. Ini isu penting yang sayangnya masih jarang jadi bahasan. Salah satu pendekatan yang kami lakukan adalah menggelar offline file sharing pada beberapa acara. Solusi onlinenya mungkin adalah untuk bergabung dengan “deep-web”.
Tentang jika band-band sudah bisa mengupload karyanya secara mandiri, sebenarnya pertanyaannya ada pada konsep music production. Bahwa tidak semua band punya strategi dalam mempublish karyanya. Kalau demikian, maka band tersebut membutuhkan label. Jadi konsep label musik saya rasa akan terus relevan selama label tersebut memiliki kemampuan dalam mengarahkan musik dari rosternya baik secara marketing maupun secara artistik.
Poin utamanya adalah sebagai netlabel, kita harus peka dan dinamis. Ini mungkin alasan kenapa banyak netlabel lokal mulai lesu. Karena mereka hanya membatasi definisi netlabel sebagai portal free download semata. Begitu ada streaming, dan rilisan fisik mulai populer lagi, mereka kebanyakan kebingungan.
H
Sebagai kurator musik dari Yes No Wave Music yang selalu terjamin kualitasnya, apa musik lokal yang bisa direkomendasikan kepada pembaca Whiteboardjournal?
W
Wah ini menarik. Apa ya? Jujur saya tidak terlalu sering mendengarkan musik lokal. Saya lebih sering mendengarkan radio sekarang ini. Jadi mungkin saran saya adalah mendengarkan radio yang sesuai dengan selera. Toh sekarang banyak sekali pilihan apps dan segala macam teknologi untuk melakukannya. Bisa coba dengar radio Triple R dari Melbourne, atau WFMU.
Kalau musik lokal susah nih. Saya tidak bisa menjawab dengan cepat. Senyawa sih palingan. Diluar itu, saya belum melihat progresivitas di musik lokal. Semuanya hanya murni adopsi dari musik luar.
H
Tahun 2016 sedang mempersiapkan apa?
W
Saya sedang merekam sebuah grup paduan suara yang berisi penyintas dan keluarganya dari peristiwa 1965. Saya tertarik untuk merekam mereka karena faktor sejarah, bahwa ada beberapa musik yang dilarang untuk didengar karena masalah politis. Musik mereka disensor bahkan ketika bentuknya masih tulisan notasi, belum direkam dan bahkan sama sekali belum berwujud sebagai suara. Saya ingin mendokumentasikan sekaligus menyebarkannya ke khalayak yang lebih luas. Terutama pada generasi muda, bahwa terkadang kondisi politis bisa membunuh kreativitas terutama dalam aktivitas berkesenian.
Untuk kemasan dari proyek ini, saya akan mengonsepnya sedikit berbeda. Saya akan mencoba membuat strategi artistik yang pendekatannya lebih populer. Sekaligus menawarkan pola komunikasi yang berbeda pada aktivis ’65 yang seringnya terjebak melulu pada nuansa berkabung, karena posisi mereka sebagai korban. Saya berusaha untuk membalik perspektif korban ini, bahwa sekarang ini, korbannya bukan lagi mereka saja. Tetapi justru korban sebenarnya adalah anak-anak muda jaman sekarang yang buta sejarah tentang apa yang sebenarnya terjadi di 1965 itu, dan ini akan terus bertambah dan lahir secara terus menerus.
Untuk Yes No Wave Music, ini juga menarik. Karena grup ini menawarkan genre yang berbeda, juga pengalaman yang unik. Kami belum pernah merekam grup paduan suara. Jadi sepertinya akan seru.
Untuk proyek seni, bulan Juni saya akan pameran solo di Casco – Office for Art, Design and Theory di Utrecht, Belanda. Temanya akan menyasar seputar hutang pada produksi seni. Secara artistik, saya sedang mencari bentuk-bentuk berbeda dari apa yang pernah saya lakukan sebelumnya. Mungkin juga masih akan meneruskan metode dalam karya saya Jakarta ’93 Whiplash (Re-revisited) yang kolaboratif, penciptaan suasana dan lebih mengarah ke bentuk-bentuk performatif. Ini yang ingin saya perdalam lagi, terutama isu tentang ekonomi. Kemungkinan setelah itu, saya ingin membawa pameran tersebut ke Indonesia.