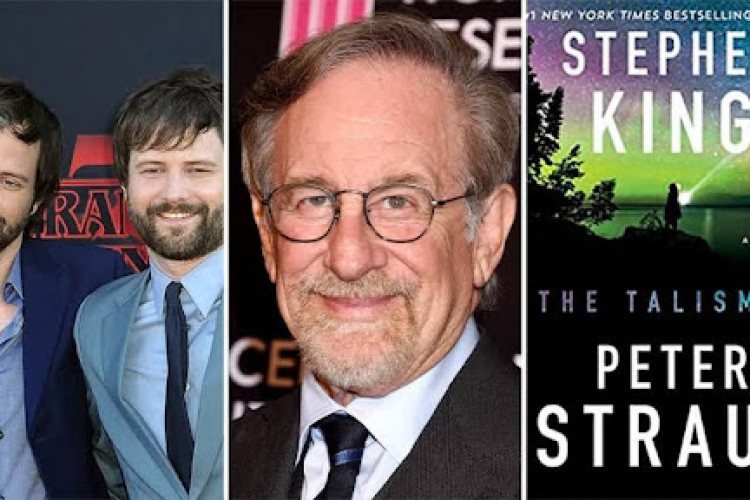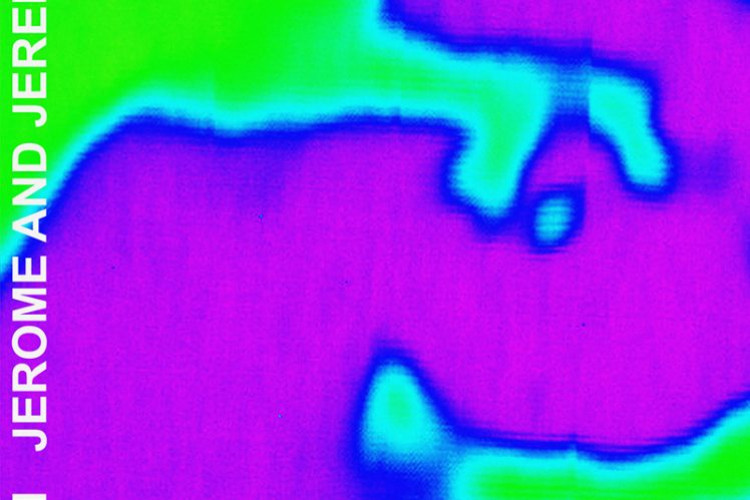Memperjuangkan Kesetaraan bersama Kartika Jahja
Febrina Anindita (F) berbincang dengan Kartika Jahja (K)





















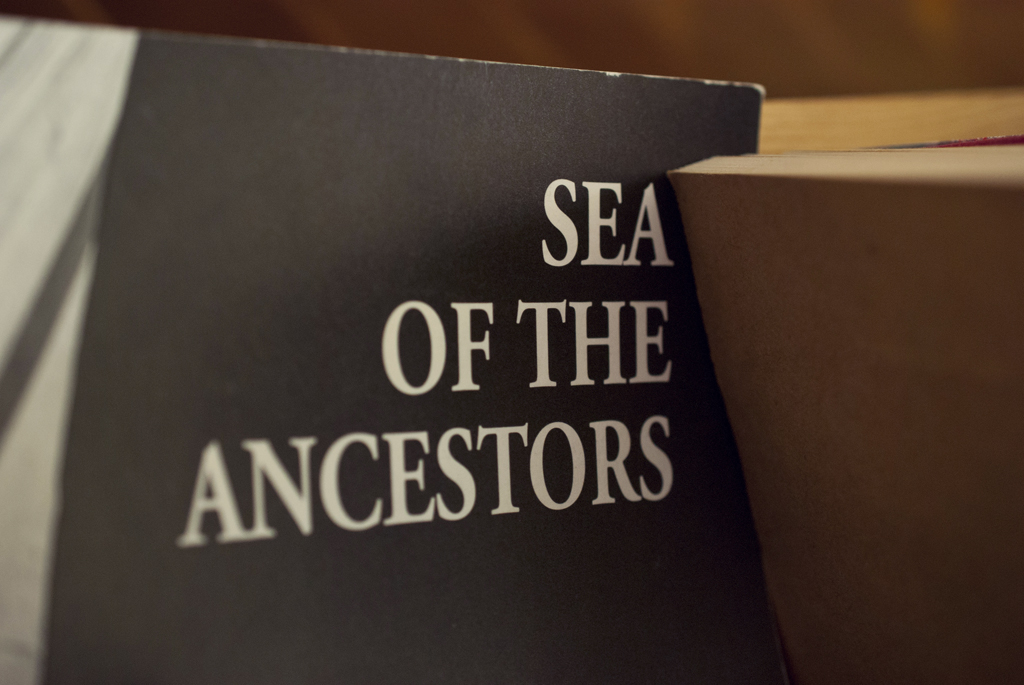



F
Bagaimana perjalanan Tika mengenal musik?
K
Saya tidak mengalami perkenalan khusus dalam mengenal musik. Tapi sedari kecil memang sudah merasa musik merupakan bagian dari diri saya. Sejak umur 5 tahun, saya suka bernyanyi walau orang tua tidak selalu memutar musik di rumah. Dulu waktu SD, saya suka membuat lagu sendiri saat diminta nyanyi di depan kelas karena saya suka dongeng dan lagu. Dari situ saya lihat musik merupakan medium untuk bercerita tentang apa yang saya rasa dan lihat. Lalu mulai kelas 6 SD saya sudah mulai nge-band karena merasa path musik saya memang formatnya band, bukan sebatas penyanyi solo karena dari awal ketertarikan saya dengan musik adalah jamming.
F
Pernah ikut sekolah musik?
K
Tidak, ibu saya pernah bercerita bahwa sewaktu saya kecil saya pernah diajak les piano bareng dengan saudara sepupu, tapi tidak pernah jadi karena saya mudah tertarik dengan hal lain (tertawa). Tapi memang bagi saya, musik lebih jadi medium untuk saya berkenalan dengan orang-orang di luar lingkar sosial saya dan keluarga. Misalnya karena ngeband, saya jadi kenal dengan anak-anak metal yang nongkrong di terminal Blok M. Lalu saya jadi tahu bagaimana penulisan lirik dari sudut pandang mereka. Jadi, pendidikan formal tidak ditempuh tapi justru pendidikan dari orang-orang yang saya temui lewat musik.
F
Apakah melalui musik, orang dapat menyampaikan pesan lebih persuasif daripada medium lain?
K
Menurut saya pribadi, musik punya pengaruh besar terhadap perspektif politik dan gender saya hari ini karena saya belajar banyak melalui musik. Seperti bagaimana saya tertarik feminisme melalui band-band Riot Grrrl tahun 90-an, lalu dari situ jadi sering mendengarkan mereka dan saya jadi tahu kata feminisme pertama kali diucapkan oleh Kurt Cobain, lalu dari situ saya tertarik dan cari tahu sendiri tentang feminisme.
Menurut saya musik punya daya tarik tertentu ke orang-orang yang tidak terpapar dengan isu tersebut, lalu jadi pintu masuk yang membuat beberapa orang tergerak untuk mencari tahu lebih jauh.
F
Kadang musik dinikmati dengan alam bawah sadar dimana perlu didengar dua kali untuk dapat beragam interpretasi, apakah Tika juga merasakannya seperti itu?
K
Iya betul, tapi di satu sisi, memang tergantung musisi yang bisa walk the talk dan bagaimana mereka menjembatani makna liriknya dengan pendengarnya, karena banyak orang yang hanya hapal lirik tapi tidak tahu maknanya, bukan hal berbau political atau social change, tapi hal-hal personal saja juga luput. Contohnya lagu Amy Winehouse – Rehab yang sering dinyanyikan banyak penyanyi di café atau mall dengan pembawaan ceria padahal liriknya tentang adiksi yang dialami Amy. Saya merasa itu tugas kita musisi dan pendengar, bagaimana membahas lirik implisit agar bisa lebih dipahami.
F
Selain band, Tika juga sering menjadi vokalis untuk pertunjukan jazz dengan nama-nama besar seperti Henning Sieverts dan Sri Hanuraga. Mengapa jazz yang menarik bagi Tika?
K
Buat saya jazz punya feel jamming dan chemistry antar pemain yang jauh lebih erat. Jazz juga memaksa saya untuk mengembangkan musik saya. Karena saat saya main dengan band-band keren yang fokusnya tidak hanya di musik; seperti attitude, saya bisa mendapatkan respons baik walau performa saya jelek, padahal untuk berkembang, saya harus lebih kritis terhadap kualitas saya sebagai musisi.
Misalnya, saat bermain bersama Aksan Sjuman, Aga Sri Hanuraga, Nikita Dompas dan Indra Perkasa, mereka memang dalam prosesnya tidak memecut saya dalam bermusik, tapi ketika saya bermain bersama mereka, saya merasa harus tampil lebih baik lagi. Berbeda ketika saya berkolaborasi dengan band-band di skena indie, dimana respons yang didapat tidak tertebak. Misal, saat saya dan band sudah latihan, respons yang didapat oke, sedangkan saat kami tidak latihan, lalu tampil apa adanya pun dapat respons bagus juga dari penonton, jadi rasanya kurang berkembang. Makanya saya dan teman-teman di Tika & The Dissidents memasang standar tertentu yang bukan hanya buat lagu bagus yang bisa mengajak orang untuk bernyanyi dan penampilan yang biasa saja.
F
Menulis lagu mulai dari lirik dan aransemen, dalam prosesnya, bagaimana Tika memposisikan diri? Apakah sebagai pendengar atau representasi diri sendiri?
K
Saya pribadi agak susah dalam memposisikan diri sebagai pendengar dalam membuat suatu karya, tapi memang pendekatan tersebut perlu dipertimbangkan. Karena selama ini, kalau saya mencoba untuk menakar kemauan pendengar pada akhirnya selalu gagal dalam prosesnya, karena walau sudah berangkat dari kerangka tertentu, tapi saat mengembangkan musiknya, ya kembali lagi diolah seperti musik yang biasa dibuat oleh saya dan band.
Jadi, pada saat menulis lagu memang semua anggota band The Dissidents itu egois karena semua hal yang dituangkan sesuai dengan selera mereka sendiri dan kebetulan seleranya berbeda, jadi band ini seperti melting pot. Kalau dari segi lirik yang memang saya tulis, saya menulis hal-hal yang saya tahu tanpa disengaja atau diagendakan, misal saat saya membahas isu berbau politik,ya itu karena saya hanya menulis topik yang ada di kepala saya serta penting saat itu.
F
Isu kesetaraan gender dan hak perempuan sudah lama jadi perhatian Tika, dan Tika membuat yayasan Bersama Project yang berfokus pada isu kesetaraan gender untuk mendukungnya. Hal apa yang menjadi trigger bagi Tika untuk beraksi menyuarakan kegelisahan tetang masalah gender ini?
K
Saya selalu tertarik dengan isu perempuan karena saya pribadi adalah perempuan dan ada banyak hal dalam hidup saya yang dirasa terhambat karena gender saya tadi, hingga ada hal-hal tertentu yang tidak bisa saya lakukan karena saya perempuan. Tapi dalam hidup saya, saya diuntungkan dengan lahir di keluarga berkecukupan yang bisa menyekolahkan saya, membuat saya bisa traveling dan lain-lain. Jadi saya selalu mengidentifikasian diri sebagai feminist tapi tidak melakukan hal untuk perempuan lain, dengan dalil bahwa, kalau saya bisa membuktikan diri, berarti orang lain bisa mengikuti apa yang saya lakukan. Ternyata, saya lalu menyadari bahwa ada yang luput dari perhatian saya, yakni mengenai adanya persoalan perempuan jauh lebih luas dari persoalan pribadi saya, karena saya memiliki beberapa privilege yang tidak dimiliki oleh sebagian besar perempuan.
Tahun 2013, saya pertama kali mengikuti One Billion Rising Indonesia (kampanye global perlawanan terhadap kekerasan seksual) dan di situ pertama kali saya membuka status saya sebagai penyintas kekerasan seksual yang pernah saya alami. Dari situlah banyak perempuan yang datang bercerita ke saya tentang pengalaman kekerasan yang mereka alami. Dari situ pula saya mulai sadar bahwa ini adalah persoalan global yang dialami semua perempuan, terlepas dari kelas hingga pendidikannya dan bahwa ketimpangan gender benar-benar ada.
Dulu saya hanya melihatnya sebatas realisasi diri dalam karir, sekarang bahkan saya sudah tidak mengaitkannya ke karir. Akhirnya saya mulai belajar dan jadi pendamping untuk korban kekerasan sampai sekarang, lalu dari proses belajar yang masih berlangsung sampai sekarang ini, saya jadi lebih memahami bahwa penting bagi perempuan untuk sadar dengan haknya dan memperjuangkannya tanpa harus jadi aktivis yang turun ke jalan, tapi cukup dengan menjadi aktivis untuk dirinya sendiri. Selain itu saya mulai selfless, dengan tak lagi berpikir “kalau saya bisa, berarti semua perempuan harus bisa,” karena adanya perbedaan kondisi keluarga atau lingkungan yang dialami banyak perempuan.
Misal ada keluarga yang tidak mampu menyekolahkan ketiga anaknya, tapi hanya dua dari mereka dimana ada 1 perempuan dan 2 laki-laki. Biasanya yang diutamakan adalah laki-laki karena dianggap akan jadi kepala keluarga – di situ perempuan sudah mengalami ketidakadilan, akhirnya anak perempuan itu dinikahkan dalam usia muda dan ternyata ia mengalami kekerasan dalam hidupnya dan tak bisa ke mana-mana karena tak punya pendidikan dan pengalaman kerja. Hal seperti itu yang membuat beberapa perempuan yang hidup dengan privilege lebih merasa bahwa gerakan perempuan tidak diperlukan lagi. Padahal sebenarnya kita atau bahkan mereka bisa saja mengalami seksisme di aktivitas sehari-hari, tapi dilumrahkan karena perlakukan yang demikian dianggap hal yang wajar.
F
Apakah hal tersebut muncul karena kita salah memahami konsep toleransi? Dimana kita cenderung mewajarkan banyak hal, padahal ada beberapa titik yang kita harus beri batasan yang jelas?
K
Iya, menurut saya titik normal kita sudah sampai di mana kita melumrahkan kekerasan, atau diskriminasi karena budaya dan policies yang ada di negara kita memang menempatkan perempuan di posisi itu. Sering sekali perempuan mendengar kata-kata seperti “memang sudah tempatnya perempuan untuk diperlakukan seperti itu” atau bahkan perempuan menyalahkan perempuan lain. Contohnya bisa kita lihat di komentar pada platform social media, misalnya ada perempuan yang memakai baju mini lalu banyak komentar sexist, hingga komentator saling berantem dan sesama perempuan memaksakan ide untuk mengikuti standar yang membelenggu bahwa kalau paha saya terlihat berarti menawarkan seks padahal bisa saja memakai baju mini karena gerah. Jadi titik normal sudah bergeser jauh. Benar atau salah sudah judgemental dan dilanggengkan secara turun menurun.
F
Dalam merilis video “Tubuhku Otoritasku”, Tika bersama kawan-kawan dari lintas disiplin membuat kolektif bernama “Mari Jeung Rebut Kembali” yang berisi Savina Hutadjulu, Ika Vantiani, Teraya Paramehta, dan Shera Indra. Bagaimana cerita dibalik pembuatan komunitas ini? Apa yang ingin ditunjukkan?
K
Kami sama-sama punya ketertarikan di feminisme dengan gaya berbeda, kebetulan konsep feminisme seperti itu kurang banyak di Indonesia. Saya juga punya yayasan Bersama Project, Shera punya Aliansi Laki-Laki Baru dan kami masing-masing digerakkan tapi jadi 2 hal yang terpisah, antara kegiatan saya di musik dengan isu kekerasan terhadap perempuan. Menurut saya, kebanyakan feel isu yang digerakkan cenderung nuansanya sangat LSM, dimana poster atau bentuk kegiatannya kurang menarik untuk saya dan orang-orang seperti saya.
Jadi, awalnya Vina mengajak membuat kegiatan untuk Hari Perempuan Internasional dan akhirnya kami berkumpul lalu saya menawarkan single “Tubuhku Otoritasku” yang memang mau dirilis, untuk dijadikan medium kampanye sekaligus mencoba untuk bicara isu tubuh kepada masyarakat luas yang tidak mau mengikuti gerakan feminisme, tapi merasa bahwa tubuh perempuan mendapat banyak tekanan besar.
Lalu kami bereksperimen membuat video dan acara, ternyata responsnya bagus dan berkelanjutan. Banyak yang menawarkan program jangka panjang hingga mau membawanya ke sekolah dan kampus. Dari situ saya sadar kalau bicara tubuh jauh lebih mudah daripada langsung bicara tentang kekerasan terhadap perempuan dimana banyak orang yang berpikir kalau kekerasan identik dengan perempuan dipukul atau diperkosa, padahal banyak bentuknya, salah satunya adalah kekerasan verbal atau tekanan terhadap tubuh perempuan. Setelah saya secara spesifik membicarakan hal itu, banyak orang mulai mengutarakan ceritanya, hingga dari situ bisa dibahas lapisan-lapisan kekerasan berikutnya yang selama ini dianggap tabu oleh banyak orang.
F
Bagaimana penyebaran informasi kesetaraan yang digalakkan Tika sejauh ini?
K
Dari beberapa tahun ini, saya merasa tahun 2015-2016 terasa perbedaan respons yang diterima jika bicara tentang isu perempuan. Pandangan terhadap feminisme mulai berubah karena banyak orang mencoba pendekatan feminisme melalui dunia kreatif, desain dan seni musik sehingga terlihat lebih menarik bagi semua orang, serta sekarang orang bisa bilang bahwa dirinya feminist. Pandangan feminis sekarang pun tidak selalu sama dengan anggapan umum yang melihat semua feminist radikal, dan lain-lain. Meskipun radikal atau tidak adalah pilihan karena mereka yang memperjuangkan haknya dengan memakai emosi, pasti memiliki alasan dibalik aksinya.
F
Bicara tentang kesetaraan, situasi dan kondisi seperti apa sebenarnya yang ideal bagi Tika?
K
Titik idealnya masih jauh sekali sih sebenarnya, jadi sekarang saya masih belum melihatnya (tertawa). Kalau bicara yang tidak idealnya adalah anggapan umum bahwa kesetaraan berarti perempuan mau mengambil semua peran laki-laki atau seolah kami menciptakan keadaan dimana perempuan harus melawan laki-laki. Menurut saya, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki terwujud ketika dua gender tersebut bisa bekerja sama dan tidak dibatasi oleh peran-peran gender yang kaku. Hal yang membagi-bagi peran perempuan dan laki-laki seperti batasan di mana tempat yang cocok untuk perempuan itu di sini sedangkan laki-laki di sana, membuat ketidakadilan terjadi karena ada hirarki disana. Menurut saya, selama orang masih memilah hal yang pantas atau tidak untuk perempuan dan laki-laki berarti kita masih jauh dari titik ideal atau anggapan umum tentang feminisme adalah perempuan mendominasi laki-laki, karena selama ini masih banyak orang yang melihat perempuan yang berdaya sebagai ancaman, padahal sebenarnya yang kita perjuangkan adalah hak dan martabat setara dengan laki-laki.
F
Beberapa waktu lalu sempat ada insiden di luar kota dimana sebuah acara yang diperuntukkan perempuan diusik warga setempat. Apakah ini merupakan bukti bahwa perempuan memiliki ruang gerak yang sempit dalam mengekspresikan diri?
K
Kolektif Betina yang menyelenggarakan acara ini awalnya dibuat untuk menyalurkan ide para perempuan dari scene Hardcore/Punk yang kebanyakan didominasi laki-laki. Kami akhirnya menginisiasi kegiatan yang terbuka untuk umum, yaitu Ladyfest di Yogyakarta, tapi ternyata kami diserang oleh ormas yang mengancam kami. Pada dasarnya kolektif ini jadi semakin kuat ketika kami mengalami langsung penekanan terhadap perempuan.
Dari situ saya tercerahkan bahwa kenapa ormas kemarin menyerang acara kami tak pernah menyerang pertunjukkan dangdut atau organ tunggal kalau alasan mereka adalah pakaian kami yang mereka pikir “kotor” dan penampilan kami yang bertato. Bedanya adalah dalam pertunjukkan dangdut, seringkali perempuan dijadikan objek, sementara di kegiatan yang kami lakukan kemarin, perempuan merupakan subjeknya. Pada saat perempuan jadi objek untuk kesenangan penonton yang mayoritas laki-laki hal tersebut dilumrahkan, sementara di Ladyfest dimana perempuan mengorganisir dan membuat pilihan dilihat sebagai ancaman karena mereka melihat bahwa tempat perempuan bukan di situ.
F
Kalau di industri musik sekarang, sudah cukup adilkah dalam memandang peran perempuan?
K
Saya sudah lama tidak berkecimpung di industri karena sekarang sebatas bernyanyi saja tanpa peduli industri musik itu sendiri. Secara umum, saya melihat kondisi musik cukup memprihatinkan, dengan cara perempuan dinilai dalam industri ini. Sejujurnya, saya tidak bisa bicara tentang industri musik hari ini, tapi berdasarkan pengalaman pribadi, kalau dilihat dari jumlah, perempuan yang ada dalam industri ini sudah banyak jumlahnya. Meski akan ada pertanyaan lagi kalau kita membahasnya dari sudut berapa banyak dari sekian musisi yang punya kuasa atas karyanya sendiri.
Ada banyak aturan di musik yang cenderung berbau sexist dan jarang di antara musisi perempuan yang bisa mengambil keputusan sendiri, kecuali mereka yang sudah punya bargaining power yang tinggi, sedangkan faktanya ada lebih banyak musisi perempuan yang masih berusaha untuk mencapai titik itu. Saya melihat di industri ini, perspektif umumnya masih laki-laki bisa menjadi musisi saja dengan memiliki lagu catchy, sedangkan perempuan perlu memiliki penampilan yang bisa “dijual.” Belum lagi mengenai imej penyanyi solo yang selalu tak bisa lepas dari persona penyanyi perempuan itu sendiri.
Keadaan sedikit berbeda di skena di tempat saya bekerja, perempuan lebih memiliki kontrol terhadap musik yang mereka mainkan. Meski memang masih ada standar pasar yang mendikte perempuan untuk sesuai dengan kacamata patriarkal dalam masyarakat yang dijadikan area tempat industri ini berputar.
F
Belakangan mulai muncul beberapa gerakan yang ikut menyuarakan semangat feminisme, tapi di sisi lain juga ada beberapa kalangan yang memandang miring feminisme, bagaimana pendapat Tika mengenai hal ini?
K
Saya rasa mereka yang memandang miring gerakan feminisme kurang membaca mungkin ya (tertawa). Atau bisa jadi mereka memang tidak mau melihat diskriminasi terhadap perempuan, dan dibutuhkan gerakan untuk melawan itu. Dan ini lebih urgent dengan kasus di Indonesia dimana banyak sekali kekerasan terhadap perempuan yang belum terlaporkan. Belum lagi persepsi dimana kekerasan terhadap perempuan dianggap tidak melanggar hukum. Di situ menurut saya, kita sebagai masyarakat harus melawan itu dari sisi perspektif, dan budaya karena sistem hukum kita tidak mengakomodasi itu.
Ada pula yang melihat feminisme sebagai ide asing. Kenapa ada pemikiran yang demikian? Mungkin karena kata feminisme itu sendiri. Tapi kalau kita bicara kata kesetaraan yang maknanya sebenarnya sama, hal itu sudah digerakkan dari dulu. Tapi kemudian ada budaya lain yang masuk beserta faktor-faktor lain yang berpengaruh.
F
Apa solusi real yang bisa dilakukan terhadap kondisi tersebut?
K
Menurut saya dikembalikan ke setiap orang, mereka sendiri yang harus tahu apa yang harus dilakukan untuk dirinya dan orang di sekelilingnnya, karena tidak ada formula baku disini. Misal ada orang yang melawan child marriage dan berusaha untuk memperjuangkan itu ke semua orang, padahal ada keluarga yang kondisinya mengharuskan hal itu dilakukan, dan perlawanannya jadi tidak relevan disini.
Butuh waktu untuk memperjuangkan isu kesetaraan, karena diperlukan program yang bisa menjembatani dari segi ekonomi, kesadaran gender serta pendidikan. Memang ini bukan proses yang instan. Tapi kalau ditanya tentang hal apa yang bisa kita lakukan hari ini dimulai dari penyadaran dari sekitar? Saya tidak akan ada di sini sekarang kalau tidak ada orang yang menegur candaan saya yang sexist, dan dari situ saya mencari tahu lebih mendalam. Kalau saya tidak ditegur, saya rasa saya akan terus di jalur itu. Jadi, saya rasa sangat penting untuk saling mengingatkan dengan cara berdialog.
F
Apa kesibukan Tika sekarang? Apakah ada proyek yang sedang digarap?
K
Sekarang saya sedang menyelesaikan zine untuk album “Merah” dalam bentuk CD karena saya ingin ada cerita dibalik lirik lagunya. Lalu saya sedang surat-menyurat dengan teman dekat saya yang juga akan dimasukkan ke dalam zine itu. Surat menyurat itu saya harap bisa menjadi cara lebih personal untuk membagi perspektif.
Lalu saya sedang merencanakan agar konten lagu di album “Merah” bisa jadi kampanye jangka panjang yang bisa dibawa dari panggung ke panggung dan maunya ada tur “Tubuhku Otoritasku” bersama band-band yang sepaham dan sepemikiran.