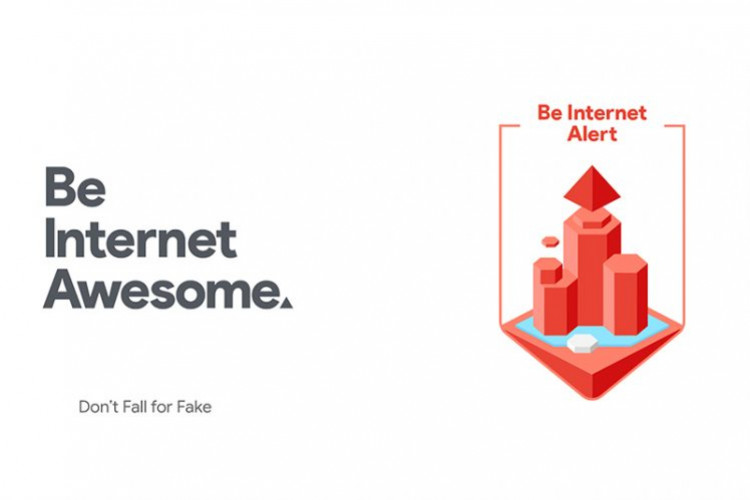Seni dan Kritik Sosial Bersama Anti-Tank
Soni Triantono (S) berbincang dengan Seniman dan Aktivis Anti-Tank (A).
by Ken Jenie



























S
Mana yang lebih dulu, minat pada desain visual atau minat pada aksi protes sosial-politik?
A
Kalau seingat saya, ketertarikan saya semasa kecil lebih condong ke visual. Memang dari kecil saya sudah suka menggambar, walaupun banyak anggota keluarga yang sampai hari ini masih bertanya, ”Kamu dapat dari mana pengaruh berkesenian itu?” Karena tidak satu pun anggota keluarga saya yang pernah bersentuhan dengan hal seni.
Saya ingat dulu mulainya sekitar tahun 1998 atau 2000-an—kalau tidak salah saat saya kelas 3 atau 4 SD. Saya punya seorang om yang bekerja di Kompas, dan beliau membawakan sebuah buku dengan banyak karikatur tentang Suharto buatan karikaturis Kompas. Waktu saya melihat gambar Suharto itu, saya berpikir ini gambarnya menarik tapi temanya politis. Itu adalah impresi pertama saya melihat karya visual yang begitu kuat.
Sampai di bangku SMA kemudian ketertarikan itu sudah mulai terbentuk. Waktu itu, seorang teman meminjamkan buku panduan HAM untuk pemula yang berisi ilustrasi dan penjelasan mendasar tentang HAM itu seperti apa. Dari situ saya makin bisa melihat fungsi karya visual dalam bahasa politik dan visual.
Saya tidak begitu ingat kapan saya tertarik melihat isu sosial, karena keluarga saya bukan keluarga yang mengalami kesulitan dalam hidup. Bapak-ibu saya adalah guru, dan sejauh ingatan saya, orang tua saya selalu bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Saya ingat, ketika itu saya tak tahu kalau kemiskinan itu ada. Bahkan, saya pernah bertanya ke mereka, “Pak, lapar itu bagaimana sih?” Karena dari TK sampai SMP, saya selalu diantar-jemput.
Ketika kecil, saya malas makan. Suatu ketika, ibu saya menyuruh kami makan sepulang sekolah, lalu saya berpikir lapar itu rasanya bagaimana? Secara personal saya tidak pernah melihat permasalahan ekonomi dI keluarga, walau belakangan saya tahu ternyata keluarga saya juga tidak kaya. Tapi hebatnya, mereka bisa mengondisikan keluarga sekondusif mungkin. Jadi yang memang paling saya ingat adalah gambar karikatur Suharto, reformasi, dan sebagainya. Nah, tarikannya dari masa SMU itu akhirnya saya berlanjut ke wilayah punk.
S
Berarti minatnya ke seni rupa dulu?
A
Iya, tapi waktu itu saya tidak tahu istilah seni rupa. Tahunya ya menggambar. Bahkan saya tidak terbiasa memakai pensil. Kan yang kita tahu menggambar sketsa itu ya pakai pensil dan baru ditebalkan pakai bolpoin. Di waktu SMP, ketika saya sudah mulai belajar anatomi dan sebagainya, saya tetap tidak bisa pakai pensil, tidak tahu ada teknik menggambar, definisi seni atau apapun. Yang saya tahu ya menggambar Dragon Ball, Kungfu Boy, atau Tiger Wong. Jadi istilah kesenian atau bahkan semacam graffiti dan street art itu tidak pernah tahu. Walaupun kala itu sudah main pilok dan menulis “punk’s not dead” di mana-mana. Tahunya ya coret-coret itu punk. Bukan seni rupa.
S
Sebagai seniman yang mengutamakan pesan di dalam karya, bagaimana Anti Tank memposisikan estetika?
A
Saya sebenarnya tidak pernah berpikir terlalu serius definisi estetika dalam karya saya itu seperti apa. Terlebih sekarang banyak orang yang gambar dan karyanya lebih canggih dan bagus. Bagi saya, yang lebih penting adalah keterlibatan langsung, fisik, atau pikiran di tengah orang-orang yang terkena dampak masalah sosial. Karena ada tarikan dan hubungannya di situ. Seandainya masyarakat yang Anda pikir penting itu bisa mengerti karya yang Anda hasilkan atau menganggap karya Anda menjadi bagian dari mereka, maka disitulah estetika itu terjadi. Saya tidak bisa menjawab apakah karya itu harus canggih atau terlihat pintar, tapi yang saya kejar adalah kalau masyarakat atau siapa saja yang saya pikirkan bisa mengerti dan menganggap karya saya sebagai bagian dari mereka, di situ fungsi estetika karya saya terwujud.
Bentuknya bisa apa saja. Di isu Papua ini khususnya, saya selalu meng-update statement dan informasi di media sosial, lalu ada teman yang berkomentar, ”Saya menunggu karya Anti Tank tentang isu Papua!” Saya pikir ini bukan tentang bikin karya atau tidak. Saya pikir kalau kita berbicara di luar atau di media sosial, atau malah dengan datang ke asrama (mahasiswa Papua di Yogyakarta), itu sudah merupakan perwujudan karya. Karena bagi saya konsep “karya” itu diproduksi di alam pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah ada di tengah-tengah masyarakat, ya itulah karya kita. Walaupun memang membuat karya adalah tugas seniman, tapi bagi saya, itu bukan harga mati, dimana sebuah karya harus berbentuk karya seni. Sikap, kadang juga merupakan karya.
S
Berbeda dengan penyampaian pesan lewat musik, apakah menurut Anda poster kritik sosial memang sebaiknya tidak memberi ruang tafsir yang terlalu bebas pada audiens?
A
Bagi saya, jawaban semacam “Biar masyarakat yang menilai” adalah jawaban yang abu-abu dan tidak mempertegas kenapa seseorang membuat karya. Itu seperti kita melempar sesuatu pada seseorang, dan ketika ditanya ”Kenapa kamu melempar?” Anda menjawab, “Ya terserah kamu kenapa aku melempar batu ke kamu.” Saya pikir begitu. Misalnya kita ingin melempar batu ke orang lain, ya kita harus melempar dengan ukuran batu, sasaran dan alasan yang jelas. Kalau alasannya “Biar masyarakat yang menilai,” ya lalu kenapa kita membuat karya? Tapi kalau ada orang yang menjawab seperti itu, itu hak mereka. Mungkin mereka punya alasan tersendiri. Tapi itu bukan jawaban saya. Karya saya harus bisa menunjukan keberpihakan dalam karya saya. Jadi wilayah abu-abu itu tidak ada. Wilayah multitafsir tidak akan mungkin bisa saya ambil dan saya toleransi. Saya memiliki tujuan yang jelas, tentang kemana saya berpihak.
Apakah bisa disebut sebagai kegagalan bagi sebuah konten berkesadaran politis dalam seni rupa ketika tidak ditafsirkan oleh audiens sebagaimana dimaksud oleh
sang seniman?
Mungkin begitu. Tapi yang lebih penting bagi saya sebagai pembuat karya adalah kemampuan untuk meyakinkan atau menunjukan dulu di awal bahwa maksud kita adalah membicarakan ‘A’. Jadi kalau yang orang tangkap dari karya kita adalah ‘B’, itu masalah yang kita bisa diskusikan. Mungkin publik memahaminya sebagai ‘B’ karena alasan tertentu. Poin saya disini adalah ketika kita menyampaikan bahwa pesan kita adalah ‘A’, maka pesan kita tak akan sebias kalau kita berkata “terserah publik yang menangkap maknanya apa”. Dari awal memang harus disampaikan maksudnya secara spesifik. Kalau publik menangkap makna yang berbeda, mari kita diskusikan, ini menjadi koreksi bagi saya sebagai pembuat.
S
Jika kesuksesan karya rupa di galeri bisa ditakar dengan laku tidaknya karya atau jumlah pengunjung, apa indikator dari keberhasilan sebuah karya street art?
A
Itu berbeda bagi setiap orang. Tapi bagi saya, hal ini bisa diukur dengan umur karya itu bertahan di suatu tempat. Ini bukan tentang seberapa tinggi—walau saya melihat itu juga pencapaian, saya selalu hormat dengan teman-teman yang bisa naik ke mana-mana. Ada yang pernah bilang, “Meski karyamu jelek, tidak apa-apa, niatmu bisa sampai ke sana itu patut dihargai. Nggak semua orang punya nyali seperti itu” [tertawa]. Karena dari beberapa kasus di karya saya dan beberapa karya street art lain, ada banyak faktor yang bisa membuat karya itu bertahan lama di jalan atau tembok.
Salah satu yang menggembirakan itu ketika orang di luar senimannya ikut merawat karya kita. Misalnya, seorang seniman menggambar di tembok, lalu ada orang yang iseng menempelkan poster iklan di sana dan poster itu dicopot tapi gambarnya dibiarkan oleh orang lain. Atau ada orang yang mencorat-coret karya kita, lalu coretan itu dibersihkan. Saya pikir itu salah satu cara mengukur keberhasilan karya di jalan. Karena kalau ada orang selain saya yang ikut merawat karya saya, berarti karya itu berarti dan memberikan sesuatu bagi mereka.
S
Berbeda dengan galeri, jalanan juga tak punya ruang interaksi langsung antara senimandan khalayak. Sulit untuk melihat respons dan mengontrol efek karya. Bagaimana Anda melihatnya?
A
Salah satu yang paling mudah memang pameran di galeri. Saya tidak mengharamkan teman-teman street art untuk ikut pameran di galeri. Bagi saya, itu tempat yang berbeda. Galeri adalah tempat yang kondusif dan bisa mengakomodasi keinginan kita untuk diskusi dan membicarakan karya ini di jalan. Ruang-ruang ini yang jadi relevan untuk terus dikembangkan. Walaupun memang kerja konkritnya di jalan. Jangan sampai kemudian seniman jadi lupa berkarya di jalan gara-gara terlalu sering pameran di galeri. Kan sekarang kita lagi ngomongin street art, sementara galeri hanya wadah untuk memperbincangkan hal yang tidak bisa kita bicarakan di luar.
Nah, galeri adalah salah satu wahana untuk mempertemukan antara pembuat karya street art dengan publik dan masyarakat. Kita bisa menemukan banyak perspektif dan hal yang tidak terpikirkan sebelumnya, termasuk tentang pendapat orang mengenai karya kita.
S
Artinya jika tidak masuk galeri memang tidak bisa melihat respons?
A
Nah, saya pikir itu pilihan si seniman. Kalau ia tidak mau pameran, biasanya seniman tersebut cenderung tak mau tahu pendapat publik. Kalau ada orang bikin street art dan masih mau tampil di pameran, workshop atau diskusi, berarti seniman tersebut mau mendengar pendapat lain di luar dirinya. Memang ada banyak karakter-karakter dari seniman street art. Ada yang sangat tertutup, semi, sangat terbuka, dan macam-macam. Tapi memang begitulah adanya, karena tidak ada peraturan di street art.
S
Seperti apa posisi karya street art sebagai medium pesan di era di mana meme, quotes, sampai poster digital kian marak dalam budaya anak muda?
A
Saya melihatnya sebagai pertaruhan politis. Ini seperti semacam perebutan ruang. Berusaha untuk mengembalikan wujud komunikasi manusia dalam bentuk yang semanusiawi mungkin. Misalnya ada karya di jalan yang terletak di tempat yang sangat tinggi posisinya, orang yang melihatnya akan berpikir “Ini ngapain sih orang menghabiskan energi, dan membahayakan nyawanya? Nggak takut apa ya?” Takut itu kan perasaaan manusia. Ketika itu dimunculkan, akan mengingatkan kita bahwa kita manusia, bukan mahkluk digital.
Kita berkomunikasi secara langsung, bukan komunikasi abjad di kode elektronik. Komunikasi ini yang harus terus dipelihara dengan banyak cara. Tidak harus lewat street art. Misalnya bikin acara festival kampung atau melangsungkan sebuah momen di depan publik dan publik bisa menilainya dari berbagai faktor dan perspektif. Itu yang tidak kita dapatkan di platform digital. Karena kita tidak bisa menyentuh, melihat dan intim disitu. Kalau kita melihat karya di jalan yang mungkin tidak sempurna, luput atau terkelupas, ya itu manusiawi. Pencitraan manusiawi itu ada di ketidaksempurnaan karya street art, bukan di karya digital.
S
Kemajuan teknologi seharusnya memudahkan proses kerja street art . Namun, apakah kemudian ada laku kontraproduktif yang dihasilkan olehnya?
A
Kecenderungannya menguntungkan karena memang pada akhirnya ide street art semakin dinamis. Sekarang sudah tidak bisa lagi dikotak-kotakan, dan sulit untuk membatasi. Artinya karya street art muncul di karya digital. Karya digital muncul di jalan. Batas-batas itu mulai hilang. Tapi poin yang menarik adalah platform digital memperpanjang usia karya street art di jalan. Karena kalau dulu yang mengerti sebuah karya hanya orang yang lewat atau bermukim di situ, nah karena adanya platform digital, seluruh orang di dunia bisa tahu ada karya seperti ini sebelumnya. Jadi membantu dalam hal memperpanjang isu pesan dari karya itu.
Tapi kerugiannya pun pasti ada, karena kita hampir tidak bisa lagi menemukan atau melihat militansi street art. Karena yang dikejar di media sosial adalah citra sebagai street artist. Dulu seorang teman pernah bilang, “Ah karya street art Indonesia mah bagusnya cuma kalau di Instagram doang. Aslinya biasa aja.“ Hal ini bisa saja ada benarnya, karena platform media sosial memang tipu-tipu. Kita bisa manipulasi cahaya dan hal lainnya. Disitu kita cenderung menciptakan ekspetasi berlebihan. Di satu sisi hal ini menciptakan citra yang buruk bagi konsumen street art maupun bagi pelakunya. Kencangnya arus informasi perkembangan karya dari luar kemudian juga secara mentah dipakai di sini. Menulis nama yang orang tidak tahu siapa dan bacanya bagaimana karena diadopsi di New York. Saking cepatnya, kita juga tidak ada saling koreksi atau proses pengendapan. Dan sekarang anak SD dan SMP sudah pegang cat semprot di mana-mana. Jadi sama seperti anak SD naik motor, ya nabrak ke mana-mana. Semakin mudah orang membuat karya yang melibatkan banyak orang. Tapi dengan kesiapan mental dan pengetahuan yang seadanya ya terlalu dini. Itu yang menjadi penyakit.
S
Seperti apa riset lokasi yang Anda lakukan dalam membuat poster?
A
Kalau tempat, saya pikir yang utama adalah harus mudah diakses, visibilitasnya harus tinggi. Karena karya ini menuntut untuk dilihat dan didengar. Semakin ke sini saya juga semakin sensitif melihat tempat yang berhubungan dengan karya. Misalnya di suatu tempat yang tidak terlalu perkotaan dan urban, saya bisa menempatkan karya yang temanya masih berhubungan dengan iklim masyarakat di sana. Saya tidak mungkin juga memaksa menempatkan isu perkotaan di pedesaan. Begitu juga sebaliknya.
Tapi selama ini memang saya lebih banyak memakai tempat-tempat yang sudah lazim digunakan oleh teman-teman street art. Karena untuk menggunakan spot atau lokasi yang belum pernah dipakai, pertaruhannya juga serius . Jangan sampai karya yang saya bikin malah menjadi masalah di sana. Biasanya untuk lokasi yang sudah biasa dipakai, urusan pendapat atau perspektif itu sudah rampung dan final. Karena masyarakatnya beragam, jadi karya itu mungkin tidak membawa masalah. Tapi kalau wilayahnya itu belum terlalu beragam, saya harus bisa menyesuaikan. Ada juga pertimbangan teknis seperti tidak boleh di sekolah, menutupi rambu lalu lintas, dan area rumah ibadah. Yang pasti juga tidak merusak karya orang lain.
S
Bagaimana Anda memandang tata ruang Yogyakarta dibanding kota lain dalam melakukan aksi kerja street art?
A
Beda banget. Saya pernah ke Malang. Di sana ada mural dan graffiti tapi tidak seliar di sini (Yogyakarta). Di sana hanya area-area tertentu. Waktu itu pas pemilu 2014, saya membawa karya ke sana dengan tema partai politik, lalu saya tempel di sekitar sepuluh lokasi. Seingat saya tidak ada karya poster di sana. Kita pulang, bulan depan ke sana lagi, sudah ada banyak poster tapi temanya Arema Malang. Ada masalah sepertinya, dan fans-nya ini mengkritik dengan poster. Jadi poster saya ditempelin poster itu. Kemudian juga saya dikabari teman di sana, “Kamu dicari Panwaslu Malang, karena ada karyamu yang seruan golput. Mereka akan cari siapa yang nempel itu.” “Kok bisa? Kan itu hak untuk bersuara?” ”Ya iya, itu di Jogja. Di Malang kayaknya belum sampai ke sana.” Nah, kotanya beda banget dengan Yogyakarta. Seolah tidak ada masalah.
Saya bisa membaca dengan jelas ketika suatu kota bermasalah tata ruang, iklim politik atau kesenjangan politiknya, pasti akan muncul karya street art. Wujudnya bisa apapun. Tapi kalau kota yang cenderung kondusif dan stabil masalah sosialnya, tidak ada pertikaian atau perang politik, biasanya tidak akan muncul karya street art. Artinya, street art adalah ekspresi yang paling alami dari warga kota. Di Jakarta misalnya ada banyak karya di ruang publiknya karena memang ada keharusan bagi warga kotanya untuk mengekspresikan dirinya di tengah keadaan kota yang nggak memungkinkannya untuk bersuara. Street art punya posisi di situ. Walaupun wujudnya secara definisi kesenian sulit kita baca. Misalnya tulisan “Budi love Tina”. Meskipun begitu, itu juga bentuk ekspresi masyarakat. “Dilarang kencing di sini” pun adalah ekspresi bahwa ada masalah di sana, yakni banyak orang kencing sembarangan. Street art punya peran komunikasi. Begitu tata ruangnya berantakan, pasti akan muncul banyak karya street art.
S
Anda beberapa kali juga mengeluarkan pernyataan kritik sosial politik via media sosial. Kapan Anda merasa perlu menyampaikan sesuatu lewat teks tertulis langsung?
A
Banyak orang juga yang menanyakan itu. Khususnya saat masalah Art Jog kemarin. Ada teman yang bilang, ”Sudah kemarin kamu dicari GPK (Gerakan Pemuda Ka’bah) dari kanan, sekarang ngomongin Art Jog jadi kamu dimusuhin seniman dari kiri. Kanan dan kiri musuhmu. Kamu mau berkoalisi dengan siapa?” Saya lalu menjawab, “Saya akan berkoalisi dengan langit dan gunung” [tertawa]. Buat saya, seni itu cuma cara. Yang paling penting itu sikap. Nah, sikap itu output-nya bisa beragam: bicara di publik, mengeluarkan statement, atau bikin karya. Tapi di masa-masa tertentu, saya juga berpikir “Apa iya sih sebegitunya? Karena saya tidak merasa memusuhi mereka.”
Mungkin, sebabnya karena saya masih muda. Saya percaya anak muda harusnya bikin banyak kesalahan. Karena jika ketika tua kita masih membuat kesalahan, itu bodoh dan keterlaluan namanya. Kesalahan bisa dilakukan harapannya agar bisa melakukan pembelajaran dan koreksi. Itulah yang saya pikirkan sekarang. Saya masih muda dan masih berhak marah-marah atau bicara banyak hal. Karena ketika saya tua, saya akan bicara persis seperti saya bicara ke orang tua, “Kalian ngapain aja sih sebelum 1998? Kok sekian tahun kalian membiarkan Suharto macam-macam? Lalu ketika harga-harga naik setelah 1998 kalian menyalahkan anak muda dan mahasiswa karena mengacaukan Jakarta.” Saya takut hal seperti ini akan ditanyakan oleh anak saya nantinya. Itu yang saya kerjakan sekarang.
Artinya, ada saatnya saya menyampaikan sesuatu yang bagi saya sangat penting diketahui orang terkait bagaimana sikap saya. Saya rasa sikap seperti ini agak susah untuk diterapkan si Jogja. Mungkin karena saya tidak lahir di sini, melainkan di Sumatera. Di sana kami diajari untuk bisa menunjukan ekspresi sikap yang jelas. Kalau suka bilang suka, tidak suka bilang tidak suka. Di sini sepertinya sulit. Saya sering bertemu teman-teman yang mengatakan,”Sebenarnya saya tak setuju dengan ini, tapi saya tidak mau bicara. Nanti ribut, ricuh, dan nggak ayem tentrem.” Saya tidak bisa mengerti itu. Ya mungkin saya masih belajar memahami pikiran orang. Tapi saya tidak pernah menyesali apa yang saya ucapkan. Saya tidak bisa mengerti kenapa saya tidak bisa mengucapkannya. Karena omongan adalah sikap, dan sikap harus jelas untuk diketahui orang lain agar mereka bisa mengerti dan memahami keadaan yang lebih luas ketika seseorang bersikap bagaimana, dan seseorang lain bersikap bagaimana lagi. Di Art Jog kemarin memang paling kelihatan. Banyak orang yang tidak mau bersikap dan mengajukan pendapatnya seterang mungkin. Memang harus ada yang bicara keras soal itu. Dan sebenarnya bicara keras dan tegas kan biasa aja. Yang tidak biasa adalah respons orang.
Begitu pun isu Papua ini. Setelah pengepungan itu, isu yang ada sekarang bukan lagi isu separatis atau menentukan hak sendiri, melainkan isu rasial. Selalu mengungkit-ungkit orang Papua itu bau, suka berantem dan mabuk, atau naik motor tanpa helm. Padahal banyak orang juga begitu. Orang GPK juga suka nggak pakai helm, padahal kepala mereka nggak lebih kuat dari orang Papua. Abdi Dalem juga tidak pakai helm. Kalau bicara tentang pemabuk, memang ada pemabuk yang ketika melebihi batasnya nggak berbuat macam-macam? Kalau kita mau membicarakan kejelekan suku, Suharto itu orang Jawa tapi membunuh banyak orang. Saya pikir butuh banyak orang non Papua yang bicara dan menunjukan solidaritasnya pada orang Papua. Tapi di Jogja banyak yang diam. Malah banyak dukungan dari Jakarta. Mungkin gara-gara kita punya trauma dengan sikap teman-teman Papua yang nakal-nakal itu. Tapi kalau kita mau fair ya sudah berapa juta transmigran Jawa yang ke Papua, yang mereka bukan tinggal sementara saja untuk kuliah tapi memang tinggal beranak pinak di sana? Apakah orang Jawa di sana tidak menghancurkan Papua? Semua orang sekarang saling menghancurkan. Tapi yang kita bicarakan adalah ada orang yang ingin didengar dan kita harus dukung. Nah, posisi saya di situ. Saya menuntut kita harus mendengar orang Papua setelah puluhan tahun direpresi. Masak sekarang kita ikut-ikutan merepresi mereka hanya gara-gara mereka ingin didengar? Saya ingin mengajak orang lain meresponsnya. Itu yang saya sampaikan lewat statement saya dengan bahasa yang harapannya bisa mengajak orang lain untuk bersuara juga. Karena kita semua korban ketidakadilan negara.
S
Masalah kota ini (Yogyakarta) yang terbesar memang toleransi ya? Atau itu adalah masalah negara secara utuh?
A
Iya, toleransi. Sudah rahasia umum. Presiden Indonesia kalau bukan orang Islam ya orang Jawa. Itu saja sebenarnya sudah menjawab. Itu sudah intoleransi. Kalau bukan walikotanya Islam mana boleh? Mana mungkin orang Batak. “Sudah Batak, Kristen, nggak pernah ke gereja, kafir, nggak mungkin jadi presiden!” Apalagi Cina. Ahok saja sudah dimusuhi banyak orang. Kita bukan lagi fokus ke kinerjanya, tapi ke latar belakang etnisnya. Itu pertanda siapa sih yang rasis sekarang?
S
Terkait Art Jog, ada yang mempertanyakan kenapa Anda baru melontarkan kritik dua minggu setelah pameran itu berlangsung. Apa tanggapan Anda?
A
Saya sebenarnya menunggu sejak hari pertama. Saya lihat di undangan Art Jog sudah ada barisan sponsor di belakang. Saya belum bicara ke siapa pun karena saya ingin dengar bagaimana respons seniman. Di hari pembukaaan, sama sekali tidak ada yang bicara, lalu di minggu-minggu pertama baru diserukan oleh band Dendang Kampungan. Mereka main di sana dan Fitri (vokalis) bicara jika mereka mengesalkan dukungan Freeport di Art Jog. Waktu itu katanya ditonton banyak orang. Respons penonton biasa saja dan konsernya lancar. Kemudian ada teman kita yang juga main, Kota dan Ingatan. Mereka juga bicara mengesalkan Freeport, dan nggak banyak yang merespons. Kemudian Saut Situmorang juga ngomongin Art Jog di Facebook, dan nggak banyak yang bereaksi.
Nah, dari perhitungan saya, Art Jog itu digelar sebulan, berarti saat yang tepat adalah dua minggu karena pertengahan. Saya masih menunggu reaksi dari orang lain dan ternyata tidak ada keributan atau perbincangan serius tentangnya. Akhirnya saya bikin statement dengan perspektif saya sendiri. Saya tidak menghakimi Art Jog, tapi hanya mempertanyakan sikap seniman. Kenapa saya tidak menghakimi Art Jog? Ya karena bagi saya sudah selesai dengan bahwa Art Jog itu bisnis dan pasar. Yang saya kejar adalah teman-teman seniman, terutama yang karyanya selama ini membicarakan isu sosial politik. Ini yang saya pikir butuh penjelasan dan publik perlu mendengar ini. Bagaimana kita menalar ini? Orang selama ini karyanya ngomongin isu Papua, tapi ikut acara yang didukung Freeport. Saya tidak bisa memahami pola nalar disitu.
Akhirnya pecahlah polemik itu dengan dinamikanya. Saya dan teman-teman punya istilah, “Akhirnya para pahlawan berguguran satu persatu”. [tertawa] Akhirnya semua menunjukan belangnya. Itu jadi peta bagi saya untuk membaca “Wah, dia yang biasanya ngomongin isu minoritas, tapi ternyata kemudian nggak peka dengan minoritas yang lain. Seniman yang ini ngomongin isu sosial dan kebhinekaan, tapi ternyata gagal memahami konflik Papua.” Itulah pahlawan-pahlawan yang gugur. Beginikah watak masyarakat seni kita?
Saya juga cukup concern melihat reaksi kejadian setelahnya. Seperti saweran yang akhirnya tidak jelas. Drama apa lagi ini? Ngapain bikin saweran? Kenapa tidak senimannya saja yang bicara? Karena sudah jelas. Heri Pemad bilang bahwa dia tidak akan memutuskan kontrak dengan Freeport. Ya kenapa juga kita memberi uang ke Pemad kalau beliau tidak mau memutuskan kontrak dengan Freeport? Akhirnya kejadian juga, ada teman-teman yang bikin saweran, uangnya terkumpul 16 juta dengan sasaran 100 juta. Tapi uangnya ke mana ya kita tidak tahu. Sejak awal saya pikir itu drama. Sama seperti drama penutupan logo Freeport dengan lakban. Kenapa kita mengurusi tembok sponsor dan panitia? Itu bukan hak kita. Mendingan pulang saja lalu bikin statement, selesai kan? Itu yang saya ingin lihat. Karena reaksi-reaksi itu yang bisa dijadikan sebagai penilaian kualitas masyarakat seni kita.
S
Anda tak jarang mengkritisi ormas, militer, dan elit negara. Namun, yang Anda kritisi kemarin adalah kalangan Anda sendiri. Apakah tidak terbesit untuk sedikit berkompromi?
A
Sebagai manusia yang lahir di era 90an, kompromi pasti ada. Tapi sampai titik mana kita bisa kompromi? Kalau sampai kita bisa kompromi dengan isu Papua, itu berarti kita sudah mengkhianati banyak hal. Kita mengkhianati kemanusiaan, dan bahkan diri kita sendiri. Bagi saya apa yang terjadi di Papua juga terjadi di Sumatera. Banyak perkebunan yang dijajah negara, dan hutan rakyat serta adat di sana direbut. Jadi apa yang terjadi di Papua berhubungan dengan saya. Masyarakat di sini harusnya juga bisa melihat itu. Apa yang terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan ada faktor yang mempengaruhi seluruh orang Indonesia, bahkan dunia. Makanya kompromi seperti apa yang kita bicarakan? Kompromi yang mereka ambil itu sudah bersinggungan dengan banyak sekali hal yang sangat urgen dan darurat. Jadi kompromi bisa dilakukan, tapi pasti ada batas yang harus kita hargai dan meminta kita untuk sensitif melihatnya.
S
Apa kekhawatiran terbesar ketika aktivitas seni mulai disokong kapital oleh kolonialis secara terang-terangan?
A
Kekhawatiran saya adalah kita tidak punya produk adiluhung, atau produk kebudayaan manusia Indonesia. Kalau semua tunduk di bawah kapital Freeport, lalu kita mau memproduksi kebudayaan apalagi? Untuk memahami sebuah kesalahan yang mendasar saja kita sudah gagal, mau membicarakan apalagi? Membicarakan yang sudah paling jelas kejahatannya saja kita gagal, bagaimana memahami hal-hal yang sepele? Itu yang saya pikir memalukan. Sebagai manusia bumi yang katanya berkebudayaan manusiawi, bagaimana kita melangsungkan produksi budaya yang baik kalau kita harus membunuh kebudayaan yang lain? Saya pikir itu kegagalan, dan itu dilaksanakan oleh seniman.
S
Apakah tuduhan “kritik tanpa solusi” adalah relevan?
A
Saya pikir kalau semua orang di dunia mengamini itu, tidak akan ada orang yang bicara. Harus ada orang yang melemparkan api dulu, baru kemudian semua orang yang punya otak rembugan membahasnya. Itu yang punya otak ya? [tertawa]
Solusi itu juga harus dibicarakan. Solusi yang saya tawarkan belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Kalau ide saya bisa diterima semua orang, kenapa ada kewajiban kritik harus ada solusi? Justru katanya kita punya budaya musyawarah dan gotong royong? Itu harus dipakai. Ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak pas di hatinya, semua orang harus mendengar dan menyampaikan pendapat masing-masing dengan cara damai. Dari situ baru kita bisa menemukan waktu untuk mencari solusi. Saya tidak tahu, siapa sih yang menemukan istilah “kritik tanpa solusi?” Jangan-jangan kapitalisme atau komunis? Jangan-jangan Stalin [tertawa]? Supaya kita jangan berpikir kritis.
S
Mengingat sifatnya temporer dan tentu tidak collectible, karya street art membutuhkan aksi dokumentasi yang mumpuni. Bagaimana Anda melihatnya?
A
Sebenarnya tidak cuma street art. Semua kebudayaan manusia memang harus didokumentasikan. Seperti—kalau tidak salah—orang Jerman yang mengumpulkan semua bibit tanaman di seluruh dunia di Antartika untuk mengantisipasi jika dunia akan hancur akibat perang nuklir. Jadi mereka sudah menyelamatkan aset-aset bumi seperti tanaman untuk diselamatkan. Nah, itu juga suatu bentuk dokumentasi.
Itu kita rasakan sekarang ketika muncul foto-foto sebelum 1945 yang ada gerbong kereta tulisannya “Merdeka atau Mati” dan “Ayo Bung Rebut Kembali!”. Kalau saja dulu tidak ada yang memotret, mengarsipkan, mengumpulkan, merawat dan mempublikasikannya, kita tidak tahu ada sejarah itu. Itu yang penting untuk dikerjakan terus dalam kebudayaan. Seperti juga semua benda pusaka Jawa yang asli ternyata malah banyak di luar negeri. Yang kita punya hanya replika. Itu menunjukan ketidakberdayaan kita sebagai bangsa yang berbudaya. Kalau kita tidak bisa memelihara dokumentasi kebudayaan kita, ya kita akan kewalahan di masa depan untuk menunjukan pencapaian kita di masa sekarang. Karena kita bisa belajar dari kesalahan kalau sudah tahu kesalahannya apa. Dan kita melakukan banyak sekali kesalahan hari ini yang harus kita tulis, rawat, dan dokumentasikan. Biar orang lain besok di masa depan bisa mempelajari itu.
Sejauh apa realisme sosial dan lingkungan Yogyakarta yang secara historis punya keterkaitan erat dengan gerakan “seni untuk rakyat” (Sanggar Bumi Tarung, Lekra,
Taring Padi) mempengaruhi karya Anda?
Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk menarik ke perspektif itu ya, semacam “seni untuk rakyat”. Saya mungkin agak berbeda pandangan dengan orang-orang di masa itu. Mungkin karena beda generasi, bahan bacaan, dan pengaruh. Saya masih melihat kesenian itu hal yang biasa aja. Mungkin seperti katanya Andy Warhol bahwa seniman itu sama saja dengan profesi yang lain, tidak ada hal yang khusus. Fungsi kesenian dan seniman harus bisa hadir di tengah kehidupan masyarakat yang normal. Jadi seni bagi saya bukan sesuatu yang sangat mulia. Ia juga punya jam kerja dan aspek-aspek lain.
Kalau ada pemikiran di Jogja bahwa pengaruh seni kerakyatan sangat kuat, bisa jadi karena dari awal memang masyarakatnya sudah dekat dengan kesenian. Jadi ketika seni modern ikut nebeng di situ ya cuma numpang saja. Mungkin di daerah lain kita masih bisa diperdebatkan, artinya tidak seserius dan semasif di Jogja di mana kesenian bisa hidup dan tinggal di masyarakatnya dengan sangat dinamis. Kalau di kota lain mungkin agak sulit karena keterputusan generasi yang membuat bentuk-bentuk kesenian tertentu punah. Akan tetapi, kalau di Jogja kan kesenian tradisionalnya masih hidup. Akhirnya seni modern numpang di situ. Ibarat aspal, jalannya sudah mulus, mereka tinggal mengikuti saja.
Mungkin memang itu kemudian memberikan pengaruh di karyaku. Tapi yang lebih berpengaruh adalah keterbukaan Jogja terhadap karya seni, bukan disiplin-disiplin seninya. Lebih ke iklim masyarakat Jogja yang terbuka terhadap bentuk –bentuk kesenian dan kebudayaan yang baru.
S
Apa proyek mendatang?
A
Tidak tahu ya terhitung proyek atau bukan, tapi ini menarik. Teman-teman di Parangkusumo akan digusur pada akhir bulan ini. Lalu teman-teman mengajak saya untuk membuat semacam eksperimen di sana. Bayangan konsepnya adalah membuat rumah-rumah yang berpotensi digusur dengan gambar Pancasila dan Sultan Hamengkubuwono IX. Karena dua simbol itu sangat magis di Jogja, harapannya rumah itu kemudian tidak akan digusur dan dirusak. Sebabnya, pernah ada kejadian menarik dari teman-teman (Wahana Tri Tunggal) WTT Kulonprogo yang menolak pembangunan bandara. Mereka membawa spanduk bergambar Sultan Hamengkubuwono IX sekitar 3×3 meter, tulisannya “Tahta untuk Rakyat” ke DPRD, dan ditinggal di situ selama seminggu. Ternyata tidak ada yang berani membuang dan mencopot. Bahkan birokrasi masih melihat simbol itu sebagai sesuatu yang magis yang harus dihormati dan dijunjung. Nah, teman-teman di Parangkusumo dan Watukodok akan melakukan itu.