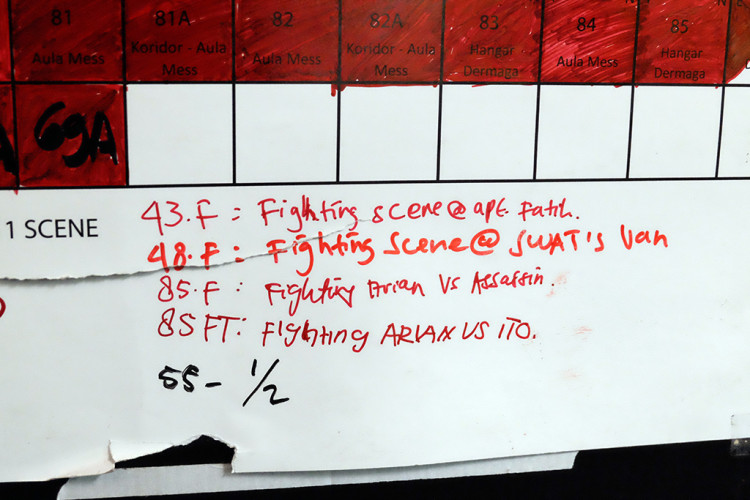Movement Musik bersama Indra Menus
Soni Triantoro (S) berbincang dengan Indra Menus (M).



S
Bagaimana Anda pertama kali berkenalan dengan musik underground?
M
Pertama kali saya menonton konser Green Day di televisi saat SMP, saat itu sekitar tahun 1994 atau 1995. Dari situlah saya semakin tertarik mengulik musik. Sebelumnya, saya mendengar musik dari radio seperti Geronimo FM yang kemudian membentuk taste awal musik saya. Tapi kalau di luar musik underground, sejak kecil saya banyak mendengar musik dari ayah saya yang suka musik heavy metal era 70-an. Tapi waktu itu tidak begitu nyantol ke telinga saya. Baru ketika SMP, saya menemukan musik-musik saya sendiri dan bukan karena diracuni orang. Waktu itu saya diberi hadiah ulang tahun berupa radio dan tape player Panasonic. Lewat itu, saya tiap malam mendengar radio dan menemukan musik rock. Selanjutnya, one thing leads to another.
S
Anda menggiati banyak bidang: organizer, musisi, zinemaker, pemilik label rekaman, penulis musik, hingga pelapak. Bagaimana cara mengelola semuanya sekaligus?
M
Saya melihat bahwa semuanya punya inti yang hampir sama. Seperti ketika saya membuat musik, lalu bikin band (To Die, pada 1998), untuk merilis album saya tersebut, saya membutuhkan record label. Dari situ saya membuat Relamati Records. Kemudian saya membuat zine (Mati Gaya, Menghamba Mesin Fotokopi, DAB). Diawali membuat band, membuat album, dipromosikan melalui zine, setelah itu tahapan selanjutnya tentu tur ke luar kota dan luar negeri. Dengan begitu akhirnya saya juga jadi organizer gig. Jadi sebenarnya semua itu berakar pada nafas yang sama.
Karena pada awalnya tidak semua orang mau membantu ketika pertama kali saya merilis album To Die. Akhirnya saya bikin sendiri, tapi dari situ saya belajar DIY (do it yourself). Saya tidak mau tergantung dengan orang lain. Pun ketika sekarang bekerja di Doggyhouse Record sebagai general manajer, saya tidak bakal bisa mengerti tugas atau cara membuat album dan merilisnya kalau saya belum pernah melakukannya.
Saya bukan tipikal orang yang terlalu berharap pada orang lain untuk melakukan tugas saya. Karena kadang ketika saya memberi tugas pada orang lain, ternyata kinerja mereka tak secepat yang saya bayangkan. Tapi ketika saya pegang sendiri, ternyata bisa cepat selesai. Saya juga jadi tahu timeline dan kebutuhan-kebutuhan tugasnya. Ya sebenarnya ini juga bicara passion sih.
S
Adakah bidang lain yang membuat Anda tertarik, namun secara sadar memang merasa belum atau tidak mampu melakoninya?
M
Sebenarnya saya sedang ingin belajar mixing dan mastering. Beberapa karya saya sudah saya kerjakan dengan proses mixing-mastering, tapi masih di level sederhana seperti memakai audacity. Tidak terlalu profesional.
Karena saya punya label, saya ingin menghasilkan sound yang memang saya suka. Saya sering mengirim tugas mixing dan mastering ke orang lain, dan ketika saya dengar hasilnya memang awal-awalnya oke, tapi lama-lama mulai terasa seperti ada yang kurang. Karena saya tipe orang yang gampang sungkan kepada orang, akhirnya ada yang saya tambahin sendiri, terutama untuk karya To Die. Di LKTDOV, rekaman multitracking, kalau yang To Die saya live recording, sehingga tidak terlalu ribet dan masih bisa saya edit dan tambahi dengan software.
Saya ingin memproduseri musik noise yang sound-nya memang oke. Bukan yang sekadar kencang. Karena itu, kemarin JNB juga membuat workshop rekaman noise. Ke depannya, kita punya rencana membuat kompilasi musik noise, tapi direkam dengan pantas. Karena selama ini kita cuma rekaman di rumah dengan software seadanya. Kita ingin seperti orang rekaman di studio dengan hasil berbeda yang ketika didengarkan bisa menjadi enak.
S
Seperti apa batasan istilah “musik underground” di era sekarang? Atau memang ada istilah yang lebih tepat untuk mewakili wilayah kiprah Anda?
M
Sekarang memang semua sudah seperti upperground. Band metal dan punk bisa bermain di acara besar dengan sponsor mainstream. Padahal menurut saya, ketika kita bicara underground, seharusnya mereka tidak “kelihatan”. Tapi sekarang semua “kelihatan” berkat teknologi dan media sosial. Saya tidak melihat bahwa underground menjadi sesuatu yang eksklusif lagi. Semua sudah mapan.
Saya tahu underground pasti masih ada. Tapi sekarang memang susah, bahkan musik noise saja bisa dipanggil ke FKY (Festival Kesenian Yogyakarta). Menurut saya, underground itu ketika yang tahu hanya circle of friend saja. Ketika saya memutuskan untuk intens di kancah musik noise, saya melihatnya seperti dulu saat saya melihat hardcore punk. Jadi mereka masih eksklusif. Tapi sekarang noise juga sudah diulas di mana-mana. Ya mungkin nanti saya bisa menemukan tren undergound yang lain lagi. Karena tren seperti itu terus berputar. Noise juga bukan sesuatu yang baru, sudah ada sejak 1920-an. Di Indonesia juga sudah lama muncul, tapi orang tidak terlalu memperhatikannya karena mereka pikir tidak bisa dijual.
S
Seberapa peduli Anda dengan komodifikasi dalam wilayah musik itu?
M
Saya punya dua pendapat berbeda untuk melihat posisi saya sendiri. Di satu sisi, ketiadaaan komodifikasi seperti membuatnya eksklusif dan hanya kita yang tahu. Merasakan dunia yang hanya kita sendiri yang tahu itu rasanya menyenangkan. Di sisi lain, kalau itu bisa dikomodifikasi, kita bisa hidup dari situ. Dan akan lebih menyenangkan ketika kita bisa hidup dari hobi—dengan catatan—tanpa harus mengorbankan idealisme. Itu kenapa saya bilang ada dua sisi yang harus diterapkan dalam dua kasus berbeda.
Dalam satu hal, saya ingin stay eksklusif di circle of friend, tapi di sisi lain, saya ingin tetap konsiten di situ, dan untuk konsisten, saya harus punya sesuatu yang menghidupi. Itulah salah satu alasan saya mengambil pekerjaan di Doggyhouse Records. Itu menyenangkan karena bekerja di sana juga hal yang saya suka. Artinya memang kita harus melihat per kasus. Tapi di Indonesia memang kebanyakan melihat dalam sudut pandang yang dikotomis, hitam ya hitam, putih ya putih. Padahal setiap kasus mesti punya different point of view.
Dulu saya orangnya saklek, tidak mau bermain di acara sponsor bersama To Die. Tapi kemudian ketika saya membuat LKTDOV—yang awalnya cuma band iseng dan side project—ternyata kita bermain di acara-acara kampus dan sebagainya. LKTDOV bolehlah, tapi saya tetap tidak mau kalau untuk To Die. Ketika bersama To Die, saya menerapkan pendirian yang saklek karena saya mastermind di situ, sementara LKTDOV punya banyak kepala sehingga kami harus banyak ngobrol dulu.
S
Dalam karya “The Shape of Punk To Come”, Refused menyatakan bahwa punk dan hardcore tak lagi dapat menentang kemapanan dengan hanya lirik revolusioner lewat musik yang sudah diambil korporat. Perlu ada wujud musik yang juga revolusioner. Bagaimana Anda melihatnya?
M
Ketika To Die pertama kali mengubah musiknya menjadi lebih eksperimental, awalnya kita juga terinspirasi dari “The Shape of Punk to Come.” Ketika anak hardcore ditanya punk itu apa, mereka menjawab punk is a way to life atau punk is more than music. Tapi ketika ada orang yang bereksperimen dari konsep musik punk yang sudah mapan tadi, mereka bilang “Ini bukan hardcore dan punk!” Menurut saya itu lucu. Kalau dibilang punk bukan sekedar musik, tapi ketika ada orang yang berada di luar kemapanan itu, justru ditolak, ini jadi kontradiktif.
Kalau kita melihat pentolan hardcore/punk lawas dari Amerika Serikat, mereka memilih di antara dua hal. Antara mereka kembali ke roots, atau membuat eksperimen. Seperti Henry Rollins yang sempat membuat pernyataan bahwa dia melihat musik noise dan eksperimental seperti bagaimana ia melihat musik hardcore punk di era awal. Saya menemukan artikel yang memberitakan itu ketika To Die mengubah musiknya menjadi lebih eksperimental. Saya sudah melihat itu sebelumnya. Beberapa musisi juga melakukannya, seperti drummer Snapcase yang membuat band noise dan eksperimental. Dari kancah lokal ada Acum (Bangkutaman) yang juga anak hardcore punk. Drummer Shaggydog (Yoyok) dulunya juga drummer band hardcore.
Ketika sesuatu sudah mapan, lalu kita ingin beralih berkarya dengan sesuatu yang lebih eksploratif, itulah punk. Saya melihat punk bukan sekadar musik, tapi juga roots character and attitude. Sound musik kita boleh berubah sedrastis apapun, tapi yang terpenting adalah roots character attitude-nya masih tetap punk.
S
Apakah Anda merasa punya selera musik yang unik, atau malah punya pandangan tertentu tentang selera musik?
M
Menurut saya, selera musik saya biasa saja. Tapi memang setiap orang punya sesuatu yang personal. Yang menurut saya unik, bisa jadi biasa untuk orang lain. Begitu juga sebaliknya. Tapi saya rasa, saya memang seorang music snob yang mendengar banyak jenis musik. Saya bukan tipe yang mendengar satu jenis musik secara detil. Saya punya seorang teman yang bisa benar-benar fetish, menyukai satu jenis musik dengan sangat mendalam dan bisa bercerita tentang sebuah band, beserta detail informasi tentang personelnya. Tapi sisi negatifnya, teman saya tadi jadi menganggap musik bergenre lain itu jelek.
Saya tipikal orang yang mendengarkan banyak jenis musik, tapi mendalaminya cuma setengah-setengah. Namun, kalau mau ngobrol dengan saya, mungkin saya bisa nyambung dalam berbagai topik bahasan. Ini mungkin urusannya dengan pekerjaan saya juga. Ketika kita menjadi jurnalis atau pegiat musik, mau tidak mau harus jadi music snob. Toh kita tak harus menyukai, tapi setidaknya kita harus mendengarkan. Ini penting, karena bagaimana kita bisa mengasah insting sebagai jurnalisme musik atau kerja di label rekaman jika referensi musik kita terbatas?
Kadang saya merasa aneh kalau ada orang yang berpikir bahwa label rekaman Shaggydog tempat saya bekerja pasti hanya menampung musik ska. Kebanyakan rekaman demo yang dikirim biasanya cenderung berkutat di musik ska, rocksteady, dan sebagainya. Padahal kalau dilihat secara rilisan, Doggyhouse Records memiliki roster yang beragam, seperti Sangkakala, Libertaria, dan lain sebagainya yang jauh dari ska. Pekerjaan saya membuat saya harus mendengarkan banyak musik dan mengekplorasinya. Ya mungkin itu yang membuat banyak orang merasa selera saya unik. Sama seperti Wok The Rock yang sebenarnya lebih snob dibanding saya. Mungkin band yang saya suka sekarang sudah dikenalnya sejak lima tahun yang lalu.
S
Bagaimana Anda menilai kualitas musik noise? Mengingat ada sifat dekonstruksi di dalamnya?
M
Saya lebih suka melihat musik melalui performa live-nya. Karena menurut saya, noise adalah tentang proses bagaimana mendapatkan suara itu. Noise dalam bentuk rekaman itu sama, kita mungkin hanya bisa melihatnya dari kualitas sound atau rekaman. Tapi cara mendapatkan sound itu seperti apa? Menariknya di situ. Bukan dari output yang sudah jadi yang bisa dipoles di studio. Tapi kita bisa melihat proses itu dalam performa live. Kecuali kalau konteksnya memainkan musik noise pakai laptop ya.
Masalah sound juga kalau kita bisa mendengarkan secara detail itu sebenarnya berbeda. Makanya gig noise seharusnya justru menggunakan sound yang bagus, karena detil itu penting. Untuk pegiat noise yang lama itu justru sangat memikirkan detil sound. Ketika mereka merilis rilisan atau kaset, label noise yang serius justru tidak merilis kaset biasa, melainkan tape 2 yang biasa untuk master. Mereka tidak ingin kehilangan detil sound-nya.
Makanya jangan dipikir bahwa musisi noise itu asal-asalan. Saya malah banyak bertemu dengan musisi noise yang lebih rewel soal sound dan audiophile dibanding band biasa. Kalau mau memperhatikan, kita bisa mendengar perbedaan antara band yang serius memikirkan sound dan yang asal noise. Bahkan, di Amerika Serikat, ada beberapa musisi yang bisa bermain sama persis dengan di rekaman. Seperti band bernama Sickness. Mereka bermain persis dengan rekamannya di CD.
S
Selain FKY dan RRRECT Fest, apakah Anda pernah mencoba membawa musik noise ke panggung yang lebih populis dan tidak terlalu tersegmentasi?
M
Saya biasanya tidak pernah memasukan proposal ke acara untuk meminta mengundang kami. Tapi kalau seumpama ada yang mengajak kami bermain di panggung-panggung populis. itu bukan masalah bagi kami.
S
Tapi apakah ada keinginan untuk memperkenalkan noise ke publik umum?
M
Tidak ngoyo sih. Selama ini respons yang didapat sudah berlebihan. Ketika kita bisa bermain diundang di FKY dan RRRECT Fest, lalu direkomendasikan oleh Indra Ameng untuk program TV Finlandia di mana kru TV nya datang ke sini itu sudah beyond expectation. Padahal kita jarang menawarkan dan mempromosikan diri. Kita sekadar membuat sesuatu lalu promosi di media sosial saja, dan kemudian menunggu feedback.
Nah, feedback-feedback itu ternyata jauh di luar ekspetasi. Kita dulu hanya berpikir untuk direkam dan masuk Youtube. Tapi ternyata bisa dapat e-mail untuk main di sana dan sini. Misi memperkenalkan itu tidak ada. Kita tidak pernah kepikiran untuk main di luar negeri atau masuk majalah The Wire. Saya saja kaget ditelpon Ameng dan diundang ke RRREC Fest untuk main setelah Polka Wars dan sebelum Efek Rumah Kaca. Apa ini? (tertawa)
S
Dari pengalaman Anda bergaul dengan banyak pegiat kancah musik underground Asia, seperti apa posisi kancah musik Indonesia di mata mereka?
M
Pertama, kalau dari kancah noise, banyak orang luar negeri melihat Indonesia sebagai scene tertinggal. “Bukannya Indonesia masih primitif ya? Tapi kok ternyata ada yang bikin synthesizer ya? Lalu ada Senyawa. Bagaimana bisa bikin musik seperti itu?” Mereka berekspetasi bahwa Indonesia hanya bagus secara budaya dan eksotisme, padahal ternyata ada juga yang kontemporer seperti itu. Mereka kaget dan tidak menyangka. Saya beberapa kali mendapat e-mail yang bilang bahwa mereka tidak menyangka ada musik seperti itu, yang mereka lihat dari beberapa media, termasuk The Wire. Wok The Rock pun ketika residensi ke luar negeri juga mengatakan bahwa banyak yang mengira Indonesia masih tradisional.
Sementara untuk musik secara general, saya melihat tidak banyak eksperimentasi. Mereka tidak kaget kalau ada musik metal dan punk di Indonesia. Mereka sudah tahu kedua aliran itu besar di sini. Apalagi di luar, musik punk dan metal juga telah menjadi sesuatu yang biasa. Di sana mereka punya venue sendiri dan bisa hidup dari situ. Di luar, ada venue-venue yang dijalankan oleh pemerintah, seperti youth center yang dikelola punk. Saking mapannya, sudah taken for granted. Kalau di sini kan kita masih berjuang.
Tapi itu mungkin membuat tidak ada lagi sesuatu yang baru di sana. Lalu ketika ada Senyawa yang membawa eksperimentasi yang di-mix dengan khasanah lokal atau Jogja Noise Bombing yang back to the street, maka mereka kaget. Saya pikir tren itu berputar. Mereka sudah berputar dua kali, kita baru berputar sekali. Sebenarnya yang ada di sini sudah ada dulu di Eropa, tapi karena mereka selalu melihat ke depan, maka kadang mereka kaget ketika ada sesuatu yang kuno. Misalnya seperti bagaimana synthesizer sudah mapan di sana. Moog menjadi pabrikan.
Dulu masih DIY di sana, dengan alat yang gede dan penuh kabel. Sekarang sudah kecil dan elektronik banget. Ketika mereka menengok ke Indonesia, maka kagetlah. Padahal alat-alat itu sudah ditinggalkan, tapi ternyata masih ada yang bikin di sini. Kita sebenarnya kalah, tapi karena mereka terlalu maju, mereka tak berpikir untuk menengok ke belakang. Begitu ada yang beda dan lawas, tapi diperbarui dengan kemasannya, mereka pun tercengang.
Selama ini ketika saya berbincang dengan orang Eropa, Australia, Amerika, atau Jepang, ternyata mereka mengaku sudah stuck. Mereka sudah bisa hidup dari noise. Mereka punya radio noise. Makanya ketika kita muncul ya terkesan terbelakang, tapi malah menarik karena sudah tidak ada yang mengulik itu lagi di sana. Misalnya ketika Bob Ostertag melihat alat-alat saya, ia pun bingung, “Masih ada yang pakai seperti ini?”
S
Terkait dengan motif berdirinya YK Booking, apakah memang banyak keluhan sebelumnya tentang kesulitan band luar untuk menggelar konser di Jogja?
M
Awalnya adalah obrolan teman-teman yang punya organizer atau label sendiri yang pernah bikin gig, entah untuk tur band atau acara senang-senang. Kita punya masalah yang sama, yakni venue dan budget. Ini kita bicara gigs yang kecil ya, skala 50 sampai 100 orang. Dari situ kita iseng ngobrol di Impact Studio yang berfungsi sebagai gig. Tapi masalahnya, untuk menggelar acara di sana, kita harus buka sepatu, dan tidak bisa bawa sepatu ke dalam. Lalu muncul sebuah ide untuk mengumpulkan duit membuat karpet. Lalu kita iuran, dan bikin karpet yang dipasang di studio agar penonton bisa datang pakai sepatu. Nah, itu adalah sesuatu yang kecil tapi antusiasmenya bagus. Maka, yuk kita tingkatkan lagi.
Kita sempat mengobrol juga dengan Sean Stellfox. Dia orang Amerika Serikat yang bekerja di sini dan turut membantu Jogja Noise Bombing. Dia menawarkan ide dan cerita bahwa ia punya beberapa teman yang tertarik membantu proyek ini. Tapi muncul pertanyaan tentang apakah kita akan menyewa venue atau membeli alat. Keuangan kami tidak memungkinkan untuk memilih keduanya. Jadi harus ada salah satu yang dipilih dulu. Kita juga berpikir bahwa tidak ada dari kita yang berpengalaman mengurus venue, dan di Jogja juga tidak banyak juga venue yang bertahan lebih dari lima tahun. Jadi kita memilih opsi kedua untuk memilih alat. Akhirnya kita mulai mencari dana. Awalnya kita membuat merchandise. Kita mengontak teman-teman band dan menawari mereka untuk membantu proyek kita dengan cara mereka memberi kita artwork untuk kita buatkan t-shirt yang dijual demi dana pembelian alat. Awalnya mereka kurang antusias karena kita kurang punya konsep yang jelas.
Lalu saya mengobrol dengan John Ying Ling. Ia punya program bernama The World Underground, di mana ia keliling dunia untuk shooting skena musik. Ia kebetulan sempat ke Jogja selama sebulan. Ternyata programnya berasal dari crowdfunding di internet, yakni Indiegogo. Kalau di luar negeri, crowdfunding Indiegogo itu hal yang biasa. Mereka tidak melihat apakah proyek atau band itu worth it untuk mereka. Kalau di sini kan mindsetnya,”Kamu itu siapa, ngapain kamu crowdfunding?”
John Ying Ling lalu memberi tahu bahwa untuk bisa menjalankan sistem ini dengan benar, kita harus menjelaskan dulu latar belakang dari proyeknya dan tujuan kita, lalu apa langkah-langkah yang akan kita jalankan. Dan mau tidak mau juga kami harus mencari nama. Awalnya kita tidak mau memakai nama, karena takutnya jadi organisasi yang saklek, padahal masing-masing dari kita sudah punya organisasi sendiri. Lalu kita sepakat memakai nama YK Booking, karena isinya orang-orang dari skena musik Yogyakarta dan aktivitasnya adalah booking band. Kita menginginkan proyek ini cair dan berjalan kontinu lanjut generasi. Jadi tidak ada konsep tentang siapa yang memimpin dan siapa yang menjadi anggota. Yang ada hanya koordinator yang kita sebut sebagai project manager. Kita juga ada istilah volunteer karena semua orang bisa masuk di situ. Saya tidak mau YK Booking identik dengan saya, atau saya dianggap ketua. Saya ingin YK Booking berdiri sendiri, mandiri, dan berkembang, jangan sampai menjadi eksklusif karena orang-orangnya selalu itu-itu saja.
Kita juga membuat media sosial agar orang tahu perkembangannya sampai mana, termasuk dalam hal pengeluaran dan pemasukan. Setelah itu kita mengajak band-band lagi untuk mengirim artwork. Uniknya, banyak band-band yang mau terlibat tanpa harus kita tawari. Dari situ orang mulai notice dengan YK Booking. Akhirnya banyak orang berpengaruh dari Jakarta dan Bandung mulai mendukung hingga sekarang kita bisa membeli alat lengkap. Masih cukup sederhana tapi lebih dari cukup.
S
Apakah ada pengaruh dari eksistensi YK Booking dengan kuantitas band luar yang menggelar konser di Jogja?
M
Sebenarnya entah ada atau tidaknya YK Booking, band luar tetap akan banyak menggelar konser di sini. Karena urusannya kemudian lebih ke banyaknya band yang mulai tahu tentang scene musik Indonesia. Sebelumnya, band yang melakukan tur paling setahun cuma ada dua. Tapi kemudian tersebar dari mulut ke mulut, mereka memberi tahu ke temannya tentang keinginan bermain di Indonesia. Nah, Jogja dikenal menjadi semacam tempat untuk rileks, seperti di Bali. Jadi sekarang sebulan bisa sampai 3-4 kali band tur ke sini. Tapi akhirnya kita membatasinya juga menjadi sebulan 2 atau 3 kali saja, karena kalau dituruti bisa kacau juga kita.
Memang pada dasarnya Indonesia menjadi sorotan. Karena untuk scene di Amerika atau Eropa, mereka sudah mapan. Mereka butuh sesuatu yang baru seperti gold, gospel and glory. Selayaknya orang jaman dahulu yang naik kapal untuk menemukan pulau baru. Mereka merasa lebih wah kalau bermain di tempat yang orang tidak tahu. Ada beberapa band yang berpikir, “Kita band pertama yang bermain di Purwokerto!”
S
Bagaimana karakter venue konser yang ideal untuk konser musik berbasis DIY?
M
Saya tidak bisa melepaskan jawaban ini dari selera personal. Saya suka venue yang kecil, maksimal 100 atau 150 orang, tapi intim dan tidak ada jarak sehingga bisa berinteraksi langsung dengan band. Band yang main juga sedikit tapi bisa main puas. Karena kalau dulu seringnya masing-masing cuma punya jatah 15 menit dan serasa tidak cukup. Di luar memang band terbiasa main satu-dua jam. Di sini paling cuma 15 menit. Setengah jam saja sudah teler dan capek. Untuk masalah alat sih yang standar saja, karena jika venue kecil maka tidak butuh yang wah.
S
Harga tiket di acara-acara musik Yogyakarta tergolong murah, mengikuti daya beli masyarakatnya. Apakah Anda melihat ada masalah di situ?
M
Sebenarnya ticketing itu memang jadi salah satu permasalahan karena sudah kebiasaan murah di Jogja. Dulu malah sempat gratis. Padahal sebenarnya tidak benar-benar gratis. Awalnya dulu kita terbiasa membuat acara harus besar, weekend, dan memakai venue seperti auditorium yang mahal. Ini menjelaskan kenapa yang band yang main itu banyak. Sebabnya adalah karena harus iuran, jadi semakin banyak band akan semakin bagus. Kita biasa menampilkan 30 band dan porsi mainnya 15 menit di waktu weekend.
Lalu muncul konsep acara yang lebih kecil, dengan daya tampung sekitar 150 orang, ketika mulai ada band-band luar menggelar tur ke Indonesia yang tidak harus weekend, tapi weekdays. Akhirnya kalau mau bikin acara di auditorium akan susah karena otomatis venue di weekdays banyak terpakai untuk acara lain, sementara harga sewanya juga tidak lebih murah dibanding weekend, padahal yang menonton tidak akan seramai saat weekend. Maka kita mulai mencari tempat-tempat lebih kecil yang menampung 100-an orang. Kebanyakan deal yang kita dapat adalah kita bisa menggunakan tempat secara gratis dengan catatan acaranya juga gratis. Dari situ mulai banyak digelar acara di kafe-kafe kecil tapi gratisan, karena pihak pemilik kafe ingin acaranya gratis biar banyak yang datang. Lalu ini mulai jadi tradisi, seolah tiap gig harus gratis.
Dulu saya memang termasuk salah satu yang sering membuat acara seperti itu. Tapi saya tidak menyangka bahwa pada perkembangannya akhirnya menimbulkan mindset bahwa gigs kecil harus gratis. Padahal kalau kita bisa menerapkan ticketing ya bakal kita lakukan. Yang jadi masalah adalah kemudian banyak yang mengharuskan organizer membayar sewa, tapi tetap dipaksakan acaranya harus gratis. Akhirnya ini baru terpikirkan setelah kafe-kafe itu tutup. Mulai ada kafe lain dengan deal yang berbeda. Karena yang menonton sudah terbiasa gratisan, begitu modelnya ticketing pun lalu yang acara menjadi sepi penonton. Padahal kalau kita menjual memang murah. Dulu pada tahun 2001, saya membuat acara di JNM (Jogja National Museum) dengan harga tiket cuma seribu. Sementara di kota lain sudah mencapai 3 ribu sampai 5 ribu rupiah. Bahkan, di Purwokerto saja sudah seharga 3 ribu, sementara kita masih seribu dan justru kami ada bonus stiker.
S
Apakah musisi lalu mengeluhkan hal ini?
M
Tidak. Dari awal, musisi Jogja sudah terbiasa membayar biaya registrasi, untuk ikut menanggung biaya sewa alat dan venue. Tapi kebiasaan itu juga menjadi salah kaprah. Padahal awalnya kita menekankan istilah kolektif karena artinya semua band dan panitia ikut mengurusi acara itu. Ada perwakilan dari band juga, termasuk iuran uang untuk membantu panitia. Kalau ada keuntungan dari konser, band juga akan mendapatkannya. Itu sebagai sebuah usaha kolektif, makanya namanya kolektif gigs. Tapi lalu ini dimanfaatkan menjadi registrasi. Jadi band membayar, lalu setelah itu band tidak ikut membantu dan uang keuntungan jadi milik panitia. Kadang ada juga pantia yang nakal, yang sebenarnya sudah mendapat uang dari sponsor tapi tetap membuka registrasi.
Nah, ini sudah menjadi tradisi. Kita tidak bisa langsung menerapkan tiket seharga 20 ribu untuk mengejar ketertinggalan. Dari awal, mindset-nya sudah gratisan atau tiket murah. Kalau kemudian langsung dihadapkan dengan tiket 20 ribu atau 30 ribu ya kurang tepat. Harus step by step. Misalnya, YK Booking tidak menerapkan yang namanya iuran band. Ketika ticketing selling-nya oke, menghasilkan keuntungan, band juga akan mendapatkannya. Makanya ketika saya mengajak sebuah band untuk bermain, selalu masih ada yang bertanya,”kolektifnya berapa?”. Makanya saya pikir memang butuh step by step.
Tidak secara langsung seperti di Jakarta dengan tiket puluhan ribu dan band dibayar semua. Kita butuh menyesuaikan. Sementara di Jogja masih di kisaran 10 sampai 15 ribu. Mungkin tahun depan bisa kita tingkatkan menjadi minimal 15 ribu sampai 20 ribu. Tentu saja terkecuali jika band kita terkenal, seperti Barasuara kemarin yang memasang harga tiket 50 ribu. Itu untuk ukuran Jogja sudah mahal sekali, tapi orang tetap menonton. Kalau di YK Booking, band-bandnya tidak mendatangkan massa. Kita sadar akan hal itu juga. Kalau kita kasih tiket mahal, malah tidak ada orang datang menonton, jadi kasihan bandnya sendiri.
Saya mendukung bahwasanya gigs itu harus bisa menghasilkan, pun band dan organizer dibayar. Tapi selama ini ketika beberapa kali kita meng-organize acara, kenyataannya tidak menghasilkan uang, bahkan kita malah keluar uang lebih. Dalam kondisi seperti itu apakah band tetap dibayar? Kita bicara kontinuitas. Saya bisa saja sekarang bikin gig lalu band yang bermain akan saya bayar semua, tapi duit saya akan habis, dan selesai, organizer-nya mati.
Saya sering melihat organizer yang baru dan berduit banyak berakhir seperti itu. Mereka ingin mencari nama, lalu akhirnya jor-joran, membuat acara besar dan membayar band-bandnya, tapi dua tahun kemudian menghilang. Saya sering mengantar band-band tur bersama mereka. Saya sering bilang, “Bikinlah yang sesuai dengan kemampuanmu, band tidak dibayar tidak masalah”. Makanya teman-teman Kongsi Jahat masih tetap jalan sampai sekarang karena kita tidak memakan apa yang tidak bisa kita kunyah.
Itu harus dipahami karena ini tidak bisa disamakan dengan kota lain. Keadaannya beda. Apa yang dilakukan YK Booking sekarang ini tidak bisa diterapkan di kota lain. Mungkin kita bisa membuat gigs berbayar dengan band mendapat bayaran semua di Jakarta dan Bandung. Tapi di Jogja butuh proses. Itu sempat jadi sebuah obrolan di Deathrockstar, tentang ticketing secara umum. Ketika itu dikatakan harus diterapkan di Jogja, saya pun bilang “tidak”. Saya mengatakan kenyataan dan fakta di lapangan. Kalau orang dari luar Jogja merasa tahu, mungkin mereka pernah membuat acara di Jogja dan menguntungkan karena baru membuatnya sekali atau dua kali. Coba mereka bertahan di sini lima tahun, apakah masih bisa seperti itu terus menerus? Saya sempat berdebat terkait masalah itu. Karena ada satu orang yang mengaku pernah bikin acara ticketing di Jogja dan sukses. Apakah mereka bisa bertahan tiap bulannya membuat acara seperti itu dan membayar bandnya? Saya bilang begitu karena YK Booking membuat acara di tiap bulan.
Apa yang diterapkan di sana tak bisa diterapkan di sini. Begitu pun sebaliknya. Saya sempat ngobrol dengan anak-anak Jakarta, dan mereka mau membuat sesuatu yang seperti YK Booking. Susah kalau mau dibikin persis. Karena dari awal kondisinya beda. Jogja dan Jakarta adalah kota yang berbeda. Keadaan kota mempengaruhi orang-orangnya. Semua harus diterapkan sesuai kondisi kotanya. Kalau YK Booking lebih seperti crowdfunding tanpa kepemilikan, mungkin di Jakarta lebih cocok membuat iuran per label, dan ada share-nya seperti saham.
S
Kegiatan yang Anda jalani banyak berbasis etos DIY dan budaya komunal, semisal patungan, kerelaan main gratis, dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat para pegiat musik memahami kebutuhan ini?
M
Nah, itu enaknya di Jogja. Band-band yang ada kebanyakan adalah band anak kampus yang selo. Mereka membuat band, lalu begitu kelar kuliah pun mereka pulang. Jadi mereka tidak berpikir apakah bandnya akan jadi profesional atau tidak. Mereka cuma ingin bersenang-senang, dan namanya bersenang-senang ya keluar duit pun tidak masalah. Membuat album itu adalah rencana jangka panjang. Band Jogja mulai gencar merilis album itu cuma ada belakangan ini. Lima tahun lalu tidak ada yang kepikiran bikin album. Adanya cuma band membuat musik, mencari panggung, bayar pun tak apa, lalu menyebarkannya lewat komputer. Dulu bahkan ada sistem distribusi lewat warnet. Jadi memang sengaja lagunya ditaruh di warnet biar disebarkan. Saya banyak menemukan demo band-band Jogja di warnet. Mereka tidak berpikir jauh bahwa bandnya bisa jadi gede atau menghidupi. Makanya mindset itu tidak bisa disamakan dengan Jakarta-Bandung.
Sekarang, band Jogja yang bisa benar-benar hidup dari musik cuma ada tiga. Lainnya masih hanya bersenang-senang saja. Bagaimana cara mempromosikan bandnya saja belum banyak yang tahu. Kalaupun mereka merilis album, tidak tahu juga cara menyebarkannya. Saya sempat punya teman satu band yang dia malah marah ketika kita rilis album dengan promosi sampai koran,”Kenapa sih harus promosi di koran dan radio?” Saya juga tidak suka, tapi itu promosi. Bagaimana kita menjual 500 keping CD ini kalau tidak promosi? Di Jogja banyak yang masih berpikiran semacam itu. Beberapa label rekaman dulu itu punya duit untuk merilis CD tapi tidak tahu cara menjualnya. Jadinya hanya menumpuk sampai seribu CD. Mereka belum siap ke industri musik, otomatis tidak banyak terpikirkan kalau main harus dibayar. Bermain band hanya untuk menghabiskan waktu luang. Baru-baru ini saja adanya band Jogja yang banyak manggung dan mulai menetapkan harga. Itu pun diikuti dengan gosip tidak enak dari band-band lain. Kondisi kota memang mempengaruhi orang-orangnya.
Band di Jogja itu jumlahnya banyak. Ketika semua orang punya band, siapa yang menonton dan membeli CD? Misal kita sama-sama punya band, belum tentu kamu akan beli ketika saya merilis CD. “Ah teman sendiri, nanti minta copy lagunya saja”. Di satu sisi memang solid ketika punya banyak teman, tapi kalau mau bisnis menjadi susah. Apakah sempat terpikir kalau itu adalah salah satu masalah juga? Saking banyaknya band Jogja, sampai tidak ada market-nya. Kebanyakan rilisan band Jogja lakunya di luar kota. Enaknya lingkungan di Jogja itu santai. Saking santainya sampai seperti itu. Mau rilis album tidak jadi-jadi, eh bandnya keburu bubar. Banyak sekali kasus seperti itu.
S
Sejumlah pihak mengatakan bahwa rilisan fisik dewasa ini harus berjibaku menghadapi tren digital. Padahal, bisa saja sebenarnya kini memang sudah jaman digital di mana justru rilisan fisik yang seharusnya kita sebut sebagai tren. Bagaimana menurut Anda?
M
Tren itu berputar. Dulu adalah eranya fisik, dan kemudian saling memakan. Dulu setelah vinyl muncul, ada tape. Tape memang tidak begitu merusak pasaran vinyl sih, tapi itu menjadi musuhnya. Lantas ada CD, dan yang menghancurkannya adalah budaya unduh. Itu nanti ke depannya akan ada lagi. Saya tidak melihat itu sebagai masalah. Menurut saya sebenarnya fisik memang tidak pernah hilang. Rilisan fisik selalu ada, tapi media tidak membahasnya. Padahal vinyl saja masih ada dan tidak pernah hilang, tapi orang tidak melihat realitas itu karena tidak diangkat media.
Sekarang ketika media mengangkat rilisan fisik, kaset, dan sebagainya, seakan back from the dead. Padahal memang tidak pernah mati. Saya masih mengoleksi rilisan fisik, sementara koleksi download juga ada. Yang mengangkat tren adalah media dan kemudian orang memakan tren itu. Rilisan fisik itu selalu ada, dan tidak perlu mengatakan only rilisan fisik is true. Ngapain? Berlebihan. Paling dia juga mengoleksi rilisan fisik baru beberapa tahun lalu. Ada juga yang merasa rilisan digital lebih bagus daripada rilisan fisik karena tidak ribet. Ya setiap orang punya referensi sendiri-sendiri. Orang tua cenderung lebih memilih rilisan fisik, tapi yang modern akan memilih digital. Sesuai preferensi saja.
Saya rasa vinyl juga akan tetap ada sampai beberapa tahun kelak, walau mungkin tak akan sebanyak dulu jumlahnya. Karena akan ada perubahan. The only constant thing is change. Kita tahu orang Indonesia adalah tipikal yang harus dramatis. Padahal ini bukan sesuatu yang harus dijadikan pro dan kontra. Saya kadang malas, karena secara general, di Indonesia ini ledakan demokrasi baru dimulai dari 1998. Demokrasi seolah harus ada pro-kontra. Orang berlomba-lomba menjadi kritis tapi ujung-ujungnya ribut.
S
Seberapa percaya Anda dengan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dalam mengembangkan kancah musik DIY?
M
Kalau mau bertahan, kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Kalau tidak kita akan mati. Ketinggalan. Kita harus beradaptasi dengan halus. Mengikuti teknologi sih oke, tapi jangan sampai teknologi menjadi tuan. Misalnya gara-gara sekarang rilisan fisik sedang laku, lalu semua band merilis vinyl. Maka band seakan harus merilis vinyl padahal secara keuangan memang tidak mampu. Akhirnya malah tidak laku.
S
Dari sederet aktivitas Anda tadi, kira-kira mana yang sekiranya akan tetap Anda lakoni pada 20 -30 tahun lagi?
M
Seperti pertanyaan di awal, bahwa semua yang saya lakukan sebenarnya berhubungan. Jadi kalau saya berhenti satu ya mungkin akan berhenti semua. Kalau saya berhenti menjadi record label, siapa yang akan merilis album saya? Kalau saya berhenti main band, record label saya akan merilis apa? Mau tidak mau itu harus kulakukan. Tapi karena saya menganggapnya sebagai hobi, ya lebih santai. Tahun depan saya tidak harus begini atau begitu. Hobi ini seperti memelihara burung. Banyak orang tua memelihara burung dan keluar duit banyak, tapi tidak terasa. Jarang ada yang mau menjual hewan peliharaan mereka. Kalaupun dijual juga tidak setimpal dengan pengeluaran yang sudah dilakukan. Kalau orang punya hobi memelihara burung, ya berarti hobi saya adalah musik.