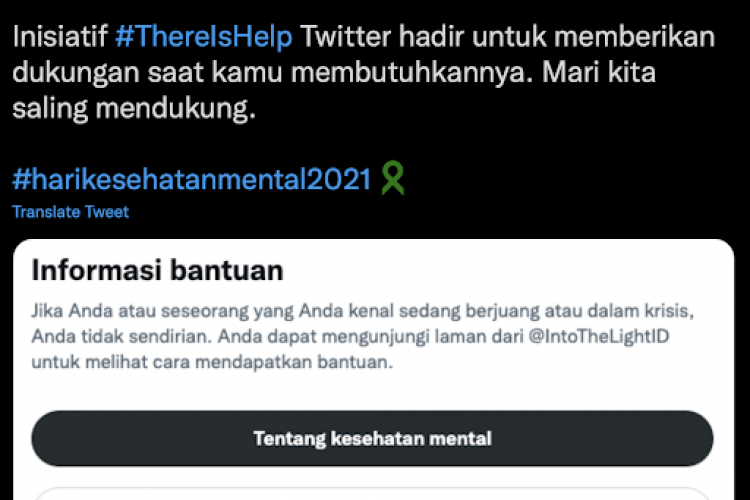“All or Nothing”: Sisi Buruk yang Berbahaya sebagai Seorang Perfeksionis
Mungkin ini pengingat untuk kalian si “hobi revisi”, ternyata menjadi seorang perfeksionis bukanlah suatu penanda kesehatan mental yang baik.

Foto: Texas Tech University
Teks: Marsha Huwaidaa
Maraknya hustle culture tentu saja melahirkan suatu budaya dan kebiasaan baru. Salah satunya adalah perfeksionisme. Banyak dari kita percaya bahwa perfeksionisme merupakan hal yang positif. Namun, ternyata para peneliti menemukan bahwa perfeksionisme sangat berbahaya dan tergolong sebagai salah satu dari masalah kesehatan mental yang masuk ke dalam daftar urgensi dan isu yang terus meningkat seiring berjalannya waktu.
Pasalnya, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh West Virginia University “sebanyak dua dari lima anak dan remaja adalah perfeksionis”. Bahkan, sosialisasi mengenai isu ini mulai digencarkan mengingat hal ini akan menjadi epidemi dan masalah kesehatan masyarakat. Meningkatnya perfeksionisme bukan penanda bahwa generasi selanjutnya akan menjadi lebih berprestasi. Bak dua belah mata pisau, perfeksionisme juga dapat merugikan kesehatan mental dan kepercayaan diri.
Standar yang dipegang oleh para perfeksionis bukanlah suatu hal yang realistis, penuh dengan tekanan dan seringkali tidak mungkin dicapai. Ketika seorang perfeksionis gagal mencapai kesempurnaan, timbul rasa bersalah yang berisikan kritik keras serta perasaan gagal. Bahkan, apabila pekerjaan selesai sesuai dengan target awal, pasti ketidakpuasan dan tuntutan akan kemampuan untuk mendapatkan hal yang lebih akan terus berdatangan. Menurut Tracy Dennis-Tiwary, PhD, seorang profesor psikologi dan ilmu saraf, seorang perfeksionis memiliki prinsip fundamental yaitu “all or nothing” kamu bisa menjadi pemenang atau kamu bisa menjadi orang yang gagal tanpa ada yang lain di antara dua kemungkinan tersebut.
Wanita rentan terhadap lereng landai perfeksionisme
Sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, wanita cenderung dibesarkan menjadi “little miss perfect”. Keberhasilan dan pencapaian yang diraih akan selalu menuai kritik dan pujian. Apalagi, penampilan dan perilaku terkadang masih menjadi suatu takaran sebuah pendapat dari orang lain. Nah, yang awalnya ‘hanya pujian dan kritik’ akan berubah menjadi ‘standar sukses yang berakhir menjadi beban’. Lalu, jika sudah begini, mulai bermunculan tekanan dan keinginan untuk bisa mendapatkan versi sempurna dari diri sendiri walau abai terhadap kesehatan mental.
Faktanya, hanya ada sedikit sisi positif dari perfeksionisme. Pengejaran tanpa henti untuk menjadi sempurna dapat menghasilkan kurangnya kepercayaan diri, gangguan kesehatan mental, kecemasan, dan stres yang tinggi dalam menghadapi kegagalan. Akibatnya, sang perfeksionis seringkali berakhir dengan pencapaian yang tidak pernah cukup, selalu lebih sedikit daripada yang mereka cita-citakan karena perkara perfeksionisme, giving yourself a high-pressure is the real competition.
Perfeksionisme adalah gerbang menuju burnout
Dalam sebuah meta-analisis tahun 2016 oleh Hill dan Curran di York St. John University, dari 43 studi tentang perfeksionisme dan burnout, ditemukan atlet, karyawan, dan siswa tidak mendapatkan manfaat dari aspek penerapan standar yang tinggi. Hal ini merupakan representasi implisit bahwa manusia yang menerapkan perfeksionisme mengalami lebih banyak burnout secara signifikan. “Perfectionism isn’t a behavior, it’s a way of thinking about yourself,” ungkap Hill dalam studinya.
Perfeksionisme bukanlah sebuah perilaku. Ini adalah cara berpikir untuk diri kita sendiri. Bekerja keras, berkomitmen, dan memiliki target yang tepat merupakan suatu fitur yang diinginkan. Namun, seorang perfeksionis akan lebih fokus terhadap hasil yang dicapai daripada proses yang dilakukan. Pada akhirnya terciptalah standar yang tidak realistis. Katanya, perfeksionisme kadang bersembunyi di balik ‘healthy-hustle’. Sehingga, para perfeksionis pasti merasakan setiap ‘gundukan jalan’ dan sangat sensitif terhadap stres. Paling tidak, perjalanan yang seharusnya dinikmati akan terkesan lebih menyulitkan dan banyak stresnya kalau kamu adalah sang perfeksionis. Karena pasti takut gagal dan cemas.
Menurut World Health Organization (WHO), jumlah anak muda yang mengalami penyakit mental mencapai rekor tertinggi. Penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan perfeksionistik mempengaruhi tingkat depresi, kecemasan, dan stres. Yes, it is true that we are each our own worst critic, menjadi kritis terhadap diri sendiri dapat menyebabkan tekanan dan kecemasan berlebih, tetapi gejala itu kemudian dapat memperburuk kondisi kepercayaan diri dan akan selalu kembali ke restless never ending cycle.
Dengan mengatasi kebutuhan akan kesempurnaan ini, penting untuk berpikir realistis. Dimulai dari diri sendiri sebagai salah satu pengingat paling jitu bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang dekat dari takaran kesempurnaan. Terkadang, kamu perlu mendapatkan berbagai perspektif. Ketika tanda-tanda burn out mulai terlihat, jangan lupa meminta bantuan kepada orang-orang terdekat. Berdirilah untuk dirimu sendiri. Kalau kamu kesulitan untuk berkata “tidak” dan mulai merasakan stres dari perilaku micromanage, perlu disadari bahwa setiap orang memiliki takaran cukupnya masing-masing.
Tetapkan waktu untuk beristirahat, luangkan waktu untuk diri sendiri ketika kamu mulai merasa kewalahan. Bacalah buku, berjalan-jalan, tidur siang, dan yang paling penting, ingatlah untuk memahami sinyal dari tubuhmu. Menjadi perfeksionisme bukanlah suatu jalan keluar dalam hari-hari penuh tekanan, then be kind to yourself, notice what you need instead of chasing what you want.