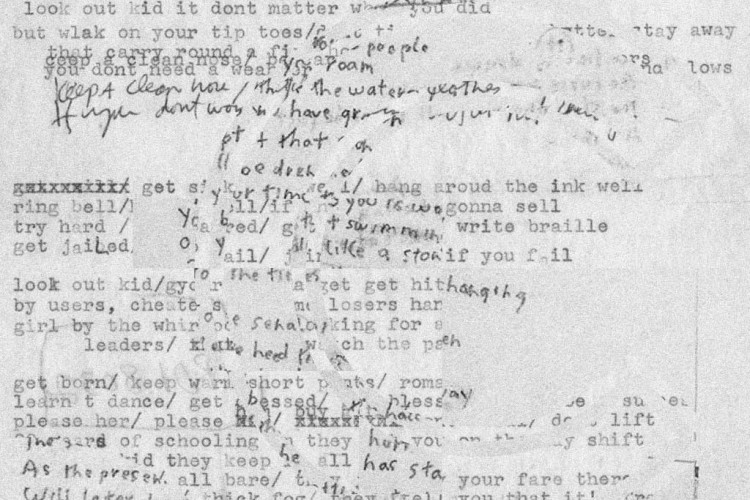Hujan Kelas Tengah Jalan
Bagian Pertama dari Seri What If There's No What If

Jalan Sultan Iskandar Muda, Gandaria. Setengah tujuh malam.
Ari bersungut-sungut di tengah hujan yang tiba-tiba turun, “Padahal helmku baru dicuci,” ujarnya sambil mendengus bau wangi dari busa di sisi kanan dan kiri kepalanya. “Halah, kamu itu. Tadi pas kamu ngasih helm ke masnya, aku justru pengen lihat muka masnya, pasti mereka ngempet ketawa, ya elah helm busuk gini aja dicuciin,” seloroh Widya yang duduk di boncengan belakang sambil memainkan matanya genit di spion. Bangga Ari kemudian menyusut pelan. Bau helmnya yang tadinya wangi, kini terasa sama saja dengan pengharum laundry 7000 ribu sekilo yang menyengat dari tumpukan baju di lemari.
“Minggir yuk, pake jas ujan. Nanti kamu masuk angin lagi lho…”, kata Widya sambil menarik kemeja Ari dari belakang. Melihat tak ada tanda-tanda cerah di arah pulang, Ari menurut. Motornya dipinggirkan di pinggir gerbang perumahan mewah di daerah Pondok Indah. Setelah keduanya terbungkus rapat oleh kain parasit berwarna biru gelap, perjalanan dilanjutkan. Kali ini, Widya benar, seperti biasa, sarannya untuk memakai jas hujan benar adanya. Sepanjang jalan lurus itu, air semakin lebat turun, memburamkan kelap cahaya lampu di kanan kiri jalan.
Seminggu ini, sudah lima hari hujan menghampiri. Buktinya bisa dilihat pada jemuran belakang Ari, dua pasang sepatu mamel sambil malu-malu menyembunyikan bau bacin tak kering berjejer diantara handuk kuyup dan kaos kaki lembap. Di kepalanya, Ari bertanya-tanya. Kenapa sampai sekarang tidak ada temuan baru yang bisa mengupgrade kecanggihan jas hujan. Bentuknya gitu-gitu aja dari dulu. Kalaupun ada variasi, palingan hanya seputar warna yang sering justru menggelikan. Totol-totol hitam putih berkibaran di tengah jalan jelas bukan inovasi yang patut diapresiasi, belum lagi tentang jas hujan berjamaah yang memiliki dua lubang kepala, jatuhnya malah seperti barongsai rebus yang gagal manggung. Terpikir kemudian harusnya jas hujan seharusnya bisa dipakai dengan lebih praktis, yah setidaknya tanpa harus berhenti lalu memutar kunci motor ke arah mati.
“Din! diiiiin!”, belum selesai lamun Ari tentang inovasi seputar ponco, nyaring klakson dari mobil di sebelah membuyarkannya. Dan seketika itu pula, Ari tersadar. Ada sebuah alasan yang demikian nyata tentang kenapa perkembangan seputar jas hujan seperti terabaikan. Alasan itu berdiri pada empat kaki, dan terbentang memenuhi badan jalan hingga perempatan di depan, menyisakan ruangan sempit di sisi kiri untuk pasukan jas hujan menyempil sambil berhati-hati supaya tidak menyentuh bodi mereka. Mobil. Yah, kalau sudah ada kap atas, kaca depan, samping dan kursi empuk yang menjamin pengendara kedap air, buat apa repot-repot ngulik kain buat bikin mantel anti mamel?
Terhimpit bemper angkuh Toyota Furtuner hitam di sisi kanan, serta abang gojek di belakang dengan muka yang seperti sudah tak kuat menahan hasrat untuk menggencet klakson kencang-kencang, Ari hanya bisa melihat ke depan. Sambil melihat peluang untuk melipir maju pelan-pelan dan melewati bongkah beton trotoar yang mencuat itu, Ari kemudian teringat sebuah esai yang kemarin ia baca di kantor sehabis makan siang. Ditulis oleh salah satu pemikir lokal idolanya, tulisan itu membahas fenomena kelas menengah, sebuah topik yang secara otomatis menarik jari Ari untuk membuka link artikel tersebut. Diunggah di sebuah website kekirian, sang pemikir membagi pendapatnya tentang bagaimana ‘ngehe’ sebenarnya sudah tidak lagi akurat untuk menggambarkan perilaku hipokrit kelas menengah di jaman sekarang.
Meskipun sebenarnya setuju-setuju saja dengan poin yang diulas sang pemikir, perhatian Ari justru terpaku pada bagaimana penulis idolanya tersebut meminggirkan pengendara motor dari definisi kelas menengah. Bahwa pengertian kelas menengah di Jakarta hanya boleh dilekatkan pada mereka yang berkantor di menara tinggi berselubung kaca dan bepergian dengan mesin berbahan minyak dan beroda empat. Motor-apalagi yang bukan vespa matic kekinian-oleh sang pemikir dikategorikan sebagai kelas bawah. Membuat Ari seorang pekerja ahensi berkendaraan Honda Astrea Grand keluaran ‘95 sekarang ‘bergumul’ dengan para pekerja kasar dan karyawan bayar murah.
Sirna sudah semua kebanggaan semu Ari yang meski suka mencela perilaku kelas menengah, kadang juga memeragakan aktivitas kelas menengah demi pergaulan dan kebanggaan yang abstrak sifatnya. Ada sesak di dada Ari, bahkan dengan hanya mengingat kalimat dari sang begawan. Sedih juga ternyata dipinggirkan. Apalagi oleh pemikir idola. Di website kekirian pula. Ah, ironinya. Diminggirkan oleh pemikir sosialis kekirian. Lamunan ini semakin menohok pikiran. Sementara, lampu hijau telah datang, namun celah jalan tak juga membentang.
***
Derap lampu yang kini kembali merona merah berhitung mundur dari sembilan puluh sembilan. Membawa Ari semakin tenggelam pada isi kepalanya sendiri. Entah kenapa kali ini pikirnya terbawa ke peristiwa beberapa hari lalu.
***
“Jadi, kamu bakal ‘kerja bakti’ lagi? Gratisan kayak biasanya?”. Bahkan ketika telah belasan kali kalimat ini menghampiri telinga Ari, masih terasa getir disitu. Nyerinya masih sama dengan ketika ia pertama kali bercerita dengan penuh bangga hati kepada orang tuanya bahwa ia mendapat kesempatan untuk mengerjakan desain untuk website idolanya. Benar, tak ada mata uang yang terlibat pada proyek ini, tapi bagi Ari, dengan diberikan keleluasaan untuk menata ulang website yang setiap hari ia buka saja, itu adalah kehormatan yang luar biasa. Saat itu, masih ada energi Ari untuk menjelaskan bahwa saat-saat seperti itu akan membukakan jalan kepada pencapaian di masa depan. Mengenai bagaimana peluang kadang lebih berarti daripada uang.
Tak lelah, setiap kali pertanyaan tersebut datang kembali, Ari akan dengan lantang berusaha membalikkan keyakinan lawan bicaranya. Agak susah juga ternyata memperkenalkan konsep gift economy dan pro bono pada keluarga yang hanya memahami sistem gajian awal bulan ala pegawai negeri sipil. Sempat absen mengungkit, entah karena capek sendiri, seolah-olah memahami, atau hanya berusaha menyenangkan anak lelaki satu-satunya, sore itu pertanyaan seribu juta itu menyeruak kembali.
Agak berbeda dengan biasanya, kali ini ada sedikit gamang pada keyakinan Ari yang ia yakini hakiki sedari masa memakai celana abu-abu yang gombrong menutup kaki. Pertanyaan yang kali itu datang dari Ibu Ari yang sedang berkunjung ke rumah beberapa hari yang lalu terasa menusuk bilik kecil di dada Ari.
Apalagi ketika suasana sedang seperti malam ini. Hujan deras, macet di perempatan, lembap jas hujan sudah mulai merembes ke dalam, istri kebasahan di kursi boncengan. Gamang itu datang beriringan dengan rasa segan kepada sosok yang bersandar pada bahu belakang. Setelah lima tahun masa pernikahan, Ari kadang merasa jengah pada posisi suami yang kini ia tenteng kemana-mana, sedangkan untuk menjalankan fungsi dasarnya saja, ia belum merasa becus. Hampir dua pertiga waktunya selalu tersita pada proyek ‘bantu-bantu’ cuma-cuma demi namanya terdengar di luar sana, meninggalkan hanya sisa-sisa saja untuk menyenangkan Widya.
Meski tak pernah ada keluh dari ucap sang istri, Ari sadar, ia sering lebih bersemangat untuk ikut ‘kerja bakti’ bersama teman bahkan sama yang baru kenalan ketimbang kerja bakti beneran bareng Widya untuk sekedar bebersih kamar kontrakan. Bahwa ia sering lebih loyal pada koneksi tak pasti, ketimbang pada perempuan yang yang telah berjanji padanya setia sehidup semati. Dan, untuk apa? Sejauh ini, hanya satu-dua peluang yang benar-benar bertuah, sisanya lewat-lewat begitu saja. Memang benar, namanya kini lebih dikenal, tapi ternyata hal itu sama sekali tak berimbas pada tawaran pekerjaan yang lebih tinggi. Sehari-hari, ia masih harus menaiki motor tuanya sembari menaham telih di akhir bulan. Jauh dari apa yang terjadi di bayangannya, dan hampir berkebalikan dengan penjelasannya pada Bapak dan Ibu dulu. Di titik ini, Ari bahkan sedikit sebal pada diri mudanya dahulu, yang sekarang terasa naif utopisnya.
Sedangkan Widya yang lurus-lurus saja, justru lebih pesat jalur penghidupannya. Tak jarang, Widya justru kebagian membayar makan malam di akhir bulan ketika uang Ari terpakai pada project bebas bea bersama teman-temannya. Dan ini menjadi pemicu sumpek yang selalu datang di hari minggu ketiga. Kadang, Ari iri pada mas-mas polisi cepek di jalan H. Naim yang bisa terus tersenyum di terik siang dengan upah recehan, sedangkan ia yang bekerja menghidupi passion-nya justru sering susah menampilkan cerah di wajah. Ah, apakah passion itu cuma mitos palsu belaka untuk kaum pseudo kelas menengah seperti dirinya?
***
Perempatan Gandul. Setengah sembilan malam.
Pening mulai menyerang kepala Ari, dihimpit helm yang harumnya telah hilang ditelan kuyup percik hujan, rentetan masalah yang menghantui pikiran sama sekali tak menambah mudah perjalanan. Rasa bersalah, idealisme masa muda yang salah arah, membuat pendiriannya yang biasanya teguh berdiri, goyah. Sembari melirik malu pada spion, Ari bertanya pada Widya, “Kamu basah gak? Aku basah nih, jas hujannya gak ngefek. Padahal baru kemarin kita beli.” “Sama aja, aku juga basah, sepatu udah jemek ampe ke dalem,” kata Widya sambil bergelayut lebih dekat ke pinggang Ari.
Dengan rasa bersalah yang semakin menggebu, Ari segera mengalihkan pandangan ke aspal basah di depan. Kontrakan tinggal 10 menit perjalanan. Satu tanjakan, satu belokan di ujung jalan, sampailah Ari dan Widya di bangunan ukuran 36 yang menjadi saksi bagaimana Widya dengan sabar menemani Ari “mengejar mimpinya”.
Hujan mulai mereda. Menyisakan titik-titik air yang membuat kaca spion Ari berembun buram. Dengan lipatan lengan bajunya, Ari lalu menghapus embun di spion kirinya. Widya terlihat kembali di sudut pandang mata Ari. Sembari melepas helm dan membuat rambutnya tergerai terhembus angin, Widya tiba-tiba menyanyi “Aku.. Cinta J.A.K.A.R.T.A…” sebelum kemudian terkikik sendiri. “Lucu ya lagu itu,” ujarnya sambil merapatkan pegangan pada pinggang Widya. Ari lantas ikut tersenyum. Masalah jas hujan, dan kelas menengah sejenak terlupakan. Tangan Widya yang berada di perut lalu didekap gemas oleh Ari. Sejenak, setidaknya sampai lima menit ke depan, tak jadi kelas menengah tak lagi terasa sebagai masalah.
“Hujan Kelas Tengah Jalan” ditulis oleh:
Muhammad Hilmi
Managing editor and ace journalist at Whiteboard Journal. His passion in music and the arts inspired him to be involved in multiple creative projects, including his own publication and record label.