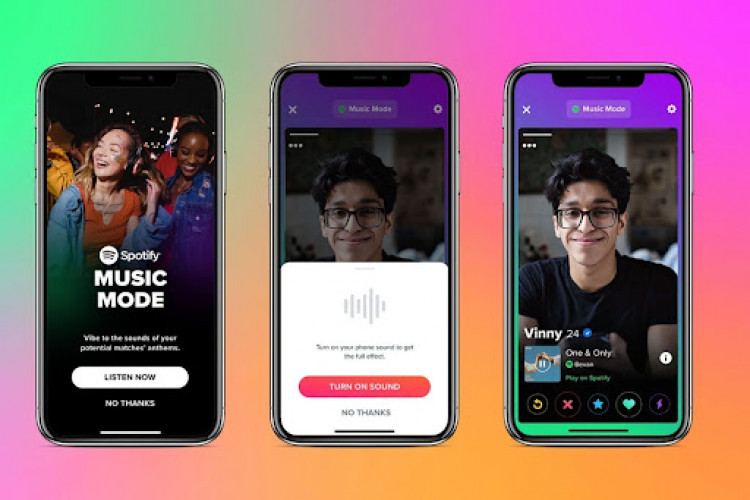Demi Musik Terus Berbunyi
Inisiatif Muda Yang Menjaga Asa Untuk Terus Bersuara






Kalimat berikut ini mungkin ini akan terdengar klise. Indonesia adalah negara yang kaya akan talenta, khususnya dalam hal budaya, namun karena banyak hal, talenta yang ada terbatas perkembangannya. Seklise apapun kalimat tersebut, sayangnya itulah kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Akan sangat mudah untuk menemukan hal menarik yang dibuat oleh anak bangsa. Tak hanya di kota besar, tak jarang talenta yang datang dari kawasan non-kota besar justru lebih terang cemerlangnya. Namun, sering pula, talenta tersebut menguap tak berbekas setelah sekian waktu. Entah karena minimnya platform bagi mereka untuk melakukan showcase, atau juga karena minimnya apresiasi yang mereka terima, semua lantas sirna tenggelam dalam banalnya rutinitas.
Khususnya dalam hal musik, fenomena ini adalah salah satu masalah klasik yang tak kunjung muncul obat penawarnya. Keberadaan infrastruktur musik yang ideal menjadi utopia yang tak berujung. Belum lagi mengenai kegemaran otoritas untuk memberangus inisiatif kebudayaan-musik khususnya, hanya dengan satu atau dua kejadian minor. Sebuah fenomena yang lantas diabadikan oleh Arian 13 dalam lagu “Dilarang di Bandung”, dimana ia bernyanyi,
“Media mengekspos, meredam ekspresi, menyudutkan, beri nama buruk skena. Kau tidak akan menghentikan kami, yang muda dan yang berbahaya. Mereka tak peduli, kekang suaramu, kini terberangus, dilarang di Bandung!”
Lagu ini merekam dengan akurat masalah yang dihadapi mereka yang menjadikan musik lebih dari teman melewati rutinitas keseharian. Di luar acara bersponsor besar, kini semakin banyak masalah yang harus dihadapi untuk membuat acara musik. Selain masalah tempat yang tak terlalu banyak, harga sewa venue yang semakin tak masuk akal, juga izin menggelar acara yang sulit dicari, membuat gigs menjadi sebuah perjuangan tersendiri bagi penggagasnya. Dan ini tentu saja belum mencakup antusiasme publik yang mirip cuaca di kolong langit, tak bisa diprediksi. Kadang acara berbayar mahal bisa dipenuhi penonton, tapi jangan kaget bila acara gratisan tak lantas sukses mengundang orang datang.
Meski berat perjuangan yang dihadapi, nyatanya masih ada nyala api pada gairah untuk bertemu, dan berbagi kebahagiaan diantara deru musik yang menghajar telinga langsung dari amplifier sang musisi. Dan ternyata, sumbu api ini menyala di berbagai sudut kota di seluruh Indonesia. Inisiatif baru bermunculan, dan dengan itu pula musik kreasi anak bangsa terus bergema.
Salah satu diantaranya adalah We Hum Collective. Melalui acaranya, We Hum Collective menyajikan warna baru pada acara musik di Jakarta. Acara mereka tak pernah berskala besar, namun justru disitulah keistimewaan mereka. Di ruangan yang sempit, dengan sound sistem yang tak jarang seadanya, We Hum Collective menjadi tempat dimana batasan antara musisi dan penonton adalah mitos semata. Disini, musisi bukan bermain untuk merasa lebih tinggi dari mereka yang menontonnya. Semua berbaur-dan kadang juga berebut microphone-untuk merayakan keriaan musik. “Kami ingin semua orang bisa bersenang-senang bersama tanpa takut bahwa mereka bakal fit in, tanpa tersekat oleh identitas apapun. Melebur saja.”, ujar Tomo Hartono salah satu co-founder We Hum Collective.
Lebih dari itu, We Hum juga memiliki satu misi lain, “Disini show DIY masih dinominasi cowok. Kami ingin acara kami bisa jadi safe space buat semua yang terlibat. Dengan itu kami melibatkan banyak cewek ke dalam kolektif kami yang cukup diverse anggotanya. Supaya kami bisa menghasilkan space yang tidak eksklusif, jadi semua yang datang bisa merasa nyaman untuk bernyanyi dan bersenang-senang tanpa takut dikucilkan atau dilecehkan,” tambah Tomo lagi.
Sekian ratus kilometer dari Jakarta, semangat yang kurang lebih sama juga hidup pada acara-acara musik dengan semangat DIY di Malang, Jawa Timur. Dalam sebulannya, rata-rata ada tiga atau empat kali acara musik yang tersebar di beberapa venue di kota yang belakangan ini cukup terdengar kiprahnya melalui beberapa band-band menarik yang muncul dari sana. Macam acaranya pun beragam, mulai dari gigs grindcore, noise, juga indie pop. Eko Marjani, salah satu aktivis musik yang telah cukup lama mengikuti perkembangan scene musik Malang melihat bahwa ada energi baru disana, “Keadaannya cukup berimbang, selain beberapa teman lama, ada juga teman-teman baru yang bikin acara. Yang membedakan dari keduanya mungkin dari anak-anak baru ini lalu muncul nama-nama baru dengan materi mereka yang fresh. Bagusnya ini menunjukkan bahwa kesadaran mengenai pengarsipan mulai tumbuh. Ini tentu menyenangkan, melihat bagaimana teman-teman berkontribusi dengan caranya masing-masing untuk membuat scene Kota Malang semakin bergairah.”
Di kota lain, semangat ini muncul antusiasme yang sama, dalam nama yang berbeda. Di Jakarta, selain We Hum, ada Swingger Collective, wastedrockers dan Noise Whore. Malang punya Malang Sub Pop, Surabaya, ada Rumah Gemah Ripah dan Dysania. Di Cirebon, ada Live Forever. Di Bandung ada An Intimacy, Liga Musik Nasional, Maternal dan beberapa kolektif lainnya. Di luar pulau Jawa, musik juga hidup dan dihidupi dengan spirit yang sama, kalau bukan lebih besar, band asal Jambi dan Samarinda mulai menjalankan tur beberapa kota, juga di Pontianak yang aktif dengan berbagai acara musik swadaya.
Di Jogja selain ada inisiatif dari Terror Weekend, juga muncul YK Booking, sebuah kolektif yang tak hanya menjaga eksistensi gigs musik, namun lebih dari itu, mereka menciptakan jalan keluar secara mandiri permasalahan yang mereka hadapi. Melalui crowdfunding, YK Booking membeli beberapa peralatan musik untuk memastikan bahwa gigs di Jogja terus ada dan dimainkan dengan peralatan yang mencukupi. Dalam interview bersama whiteboardjournal, Indra Menus, salah satu inisiator YK Booking berkata, “Uniknya, banyak band-band yang mau terlibat tanpa harus kita tawari. Dari situ orang mulai notice dengan YK Booking. Akhirnya banyak orang berpengaruh dari Jakarta dan Bandung mulai mendukung hingga sekarang kita bisa membeli alat lengkap. Masih cukup sederhana tapi lebih dari cukup.”
Dengan begitu banyak inisiatif, sepertinya keadaan yang ada cukup positif. Meski demikian, bukan berarti semua berjalan tanpa tantangan. Iit Boit, owner dari toko musik Ommunium yang juga cukup sering menggelar acara musik di Bandung berkata, “Kalo buat saya ngeliatnya, semuanya jalan sendiri-sendiri. Jadi ada banyak komunitas, tapi gak saling padu. Tentu setiap komunitas punya kelebihan masing-masing, tapi karena tidak jalan bersama, jadi bisa dibilang band yang menonjol untuk saat ini masih sedikit. Banyak pula yang tidak kelacak radar malahan, karena mereka jalan sendiri-sendiri.”
Dan tentu saja, ini belum menyangkut masalah klasik, infrastruktur, “Ada isu dari pemerintah kota Surabaya, mereka melarang musik punk/metal/reggae/rock untuk menyewa gedung kesenian milik pemkot. Ini sangat menyedihkan. Padahal gedung kesenian milik pemerintah adalah yang paling murah dengan akustik yang lumayan. Jadi kawan-kawan terpaksa menyewa venue milik TNI/swasta yg lebih mahal”, Anitha Silvia dari Rumah Gemah Ripah menjelaskan kondisi yang ia hadapi di Surabaya.
Di Bandung, masalahnya tak jauh berbeda, meski sang walikota telah mendeklarasikan kotanya sebagai kota musik, masih belum ada perubahan yang nyata, “Masih mahal banget. Kalo bikin acara dibawah 100 orang, kita sudah ada di daftar polisi, kitapun harus tetap memberi tahu kalau kita bikin acara. Di Bandung, kondisi gedung pertunjukannya wallahu a’lam.”
Untungnya, jalan keluar juga berada tak jauh dari masalah itu sendiri. Titik cerah itu terbentang dari kemampuan individu-individu ini untuk melihat dan memanfaatkan peluang. Sekecil apapun itu. “Acara kecil tetap harus berjalan. Biasanya acara digelar di halaman toko, warung kopi atau di studio. Antusiasme publik pun lumayan.” Aldiman Sinaga, pegiat musik Pontianak bercerita.
“Jakarta adalah tempat yang ramah kalau kita punya modal, kalau kita tidak punya, memang harus gerilya. Kita memang kekurangan public space. Solusinya harus kreatif memanfaatkan space apapun. Bahkan mungkin sesekali memanfaatkan private space seperti rumah buat venue. Dan ternyata bikin gig di rumah tidak serumit itu, sederhana banget malah. Intinya ya gimana kita komunikasi ke tetangga. Sebenernya perumahan itu potensial banget buat gig soalnya kalau dieksekusi dengan baik, bukan tidak mungkin sebuah gig bisa turut membantu perekonomian warga sekitar,” ungkap Tomo tentang pengalamannya menggelar acara di garasi rumahnya. Tepat di seberang musholla desa, gigs rumahan tersebut berlangsung lancar sampai akhir acara. Dimana alih-alih mengusir, warga sekitar justru menyambut penonton acara dengan senyuman ramah.
Ke depan, rasanya perbaikan dalam hal infrastruktur masih jauh untuk bisa dijadikan tumpuan harapan. Kalaupun ada, harapan itu bukan berada di kuasa otoritas. Justru, asa berada pada tangan dan visi individu-individu yang dengan peluh dan semangat menjaga agar musik terus bernyanyi. “DIY kan solusi atas permasalahan. Selalu ada jalan kok disana, selama kita masih punya teman-teman yang mau menghidupi passion mereka.” Tukas Aldiman Sinaga. Spirit ini pula yang diyakini oleh We Hum Collective, “Pada akhirnya semua kembali pada kemampuan organizernya bikin atmosfer yang menyenangkan. Dimana pun venuenya. Karena bersenang-senang dengan keterbatasan itu sangat mungkin dilakukan,” tutup Tomo.