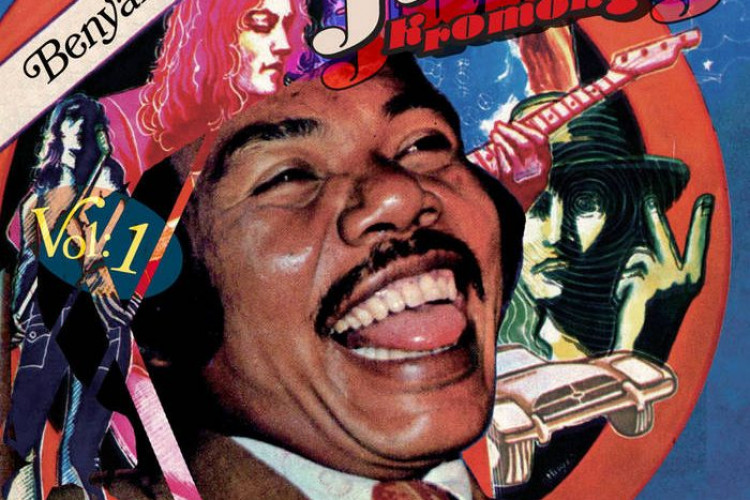Perempuan dan Kemanusiaan bersama Djenar Maesa Ayu
Febrina Anindita (F) berbincang dengan Djenar Maesa Ayu (D).











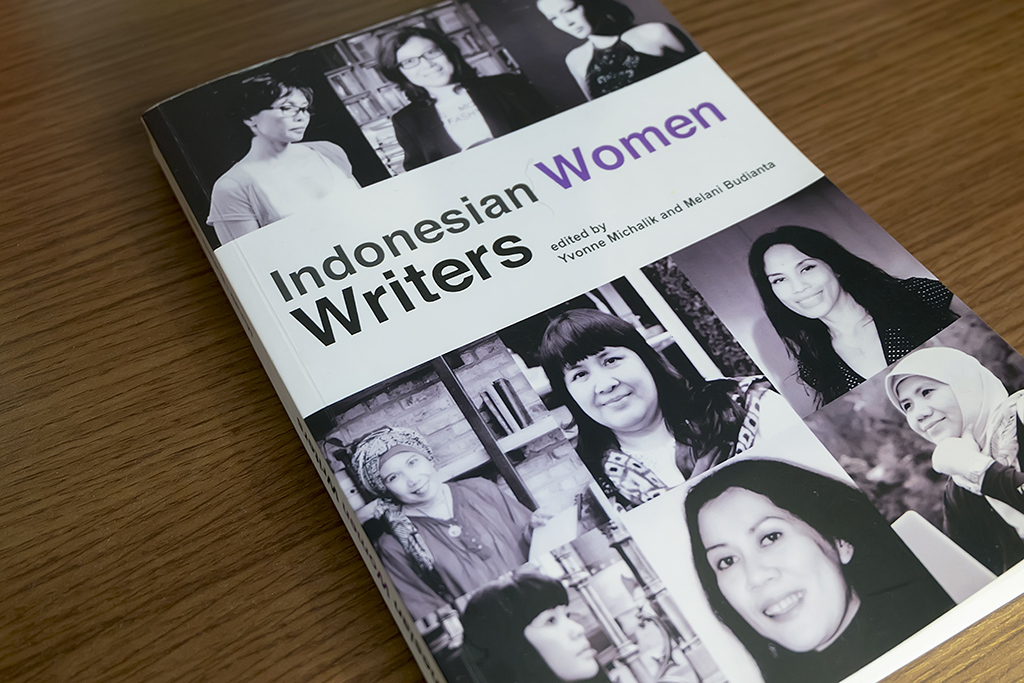
F
Anda dikenal sebagai penulis, screenwriter, filmmaker hingga aktor. Apa sebenarnya yang membuat Anda ingin mengeksplorasi ranah kreatif ini?
D
Tidak tahu ya, sepertinya mungkin karena kultur keluarga. Semuanya, dari orang tua kandung, orang tua tiri, semuanya berkecimpung di dunia seni. Bapak saya sutradara, ibu sampai sekarang masih aktor, lalu ibu tiri adalah seorang penari dan koreografer, dan sekarang kakak-kakak juga koreografer, ada yang musisi.
Jadi sepertinya memang kami tidak tahu ada dunia lain selain seni. Keseharian kami sudah sangat kental dengan itu. Walaupun dari kecil tidak pernah berpikir kalau akan jadi penulis juga, atau jadi apa. Semuanya natural.
F
Nyali adalah impresi pertama yang melekat pada Djenar. Apa yang membuat Anda begitu artikulatif dalam menyampaikan perspektif lewat beragam cerita yang Anda buat?
D
Terus terang, saya sendiri tidak pernah berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang berani, tapi memang begitu, itu adalah sebuah kondisi, cermin sebuah situasi di mana menjadi diri sendiri membuat orang insecure. Dari insecure itu, mereka mengambil keuntungan, dan karena itulah menjadi diri sendiri menjadi seperti bentuk perlawanan, bentuk keberanian. Tapi terus terang sepertinya biasa saja kalau buat saya, mungkin tidak begitu kalau menurut orang lain.
F
Melihat pola pikir masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, terkesan bahwa kita cukup lamban menyerap perkembangan zaman sehingga cenderung kurang open-minded. Terkait hal tersebut, apakah ketika seseorang ingin menyuarakan opininya, medium berupa cerita, selalu diperlukan?
D
Ada banyak cara untuk mengungkapkan pendapat dan opini, salah satunya seni. Kesenian itu direct, lebih direct, dia menyentuh emosi, sehingga dia bisa menjadi senjata atau alat yang lebih jitu ketimbang pisau dan kekerasan. Seni adalah salah satu medium untuk perlawanan juga.
F
Bagaimana melihat intoleransi dalam masyarakat Indonesia?
D
Masalah toleransi ini adalah masalah di mana memang kekuasaan ingin mengatur masyarakatnya, mengatur semua orang untuk berpikiran seragam, yang paling gampang isunya tentu agama dan moral.
Tujuannya adalah itu, menakut-nakuti, membuat persepsi mereka sendiri, aturan mereka sendiri, untuk mengatur kita. Jadi kita memang sengaja diseragamkan agar mudah diatur, mudah dibodohi. Masalahnya mereka bukannya tidak mengerti toleransi, mereka tidak tahu informasi yang benar.
F
Bicara konteks, seringkali kita melupakan hal tersebut ketika menilai sesuatu, misalnya mengenai hal-hal yang dilihat tabu. Bagaimana Anda menyikapi kebiasaan ini?
D
Banyak sekali hal yang ditabukan itu sebetulnya hal yang paling penting untuk dibicarakan, salah satunya seks. Ketika seks itu ditabukan, ia tidak terbuka, orang jadi misinformasi, lagi-lagi salah informasi tentang seks, sehingga kekerasan seksual terjadi. Ditambah dengan kondisi di mana perempuan tidak boleh bicara tentang seks, korbannya juga menjadi semakin banyak. Kekerasan terhadap rumah tangga, pemerkosaan oleh keluarga sendiri, oleh suami sendiri. Perempuan tidak tahu batas di mana bahwa mereka punya hak untuk mengatakan tidak, juga kepada suami. Jadi segala sesuatu yang ditabukan itu sangat-sangat merugikan, padahal itu adalah yang sangat penting
F
Ada kegelisahan pada perempuan yang tidak bisa diutarakan karena terdapat aspek tabu menurut konvensi sosial. Lewat novel “Nayla,” Anda berinisiatif untuk membeberkan hal tersebut, namun masih banyak yang tidak bisa melihat kegelisahan tersebut. Apakah Anda akan terus memperjuangkan isu ini?
D
Iya. Mungkin kasusnya tidak banyak sekali, tapi ada beberapa pembaca atau penonton film atau orang-orang yang mengikuti karya saya merasa bosan. Mereka berpendapat bahwa apa yang saya tulis “Kok sama-sama aja sih? Memang tidak bisa menulis yang lain? Buat apa membahas perempuan lagi, perempuan lagi, perempuan lagi?” Tapi menurut saya selama itu adalah penting dan harus saya suarakan dan saya masih ingin suarakan, saya tidak peduli, dan selama saya masih hidup sebagai perempuan yang masih tahu persis bahwa sulit sekali untuk menjadi seorang perempuan, banyak sekali kegelisahan, banyak sekali ketidakadilan yang harus diutarakan, saya pasti akan tetap menulis hal itu.
F
Selain menulis, Djenar juga seorang filmmaker. Melihat perbedaan medium ini, manakah yang lebih efektif dalam menyampaikan ide atau opini Anda kepada publik?
D
Saya pikir keduanya sama-sama efektif. Masalahnya cuma lebih banyak yang mana. Masalahnya untuk saya, di kedua medium tadi, audiens saya bukan audiens yang besar. Kalau karya sastra saya dikatakan termasuk best seller dengan terjual misalnya 40.000 copy untuk buku sastra, itu adalah sebuah kenyataan yang menyedihkan ketika melihat berapa banyak penduduk Indonesia yang ada ratusan juta jiwa. 40.000 best seller? That’s crazy.
Di film lebih parah lagi, beberapa film saya tidak diputar di bioskop karena lagi-lagi masalahnya adalah lembaga sensor, tidak bisa buat apapun yang kita memang mau buat. Medium visual, kesulitannya mungkin orang lebih mudah melihat daripada membaca, orang tidak membaca, orang malas, paling mereka gosip, “Ah si Djenar, oh iya tuh yang bikin Jangan Main-Main (dengan Kelaminmu),” ah gila itu orang pasti moralnya bejat.” Gampang, tapi mereka malas membaca.
Tapi kalau film, karena itu visual, dia lebih mudah untuk disensor, lebih mudah untuk ditemukan buktinya. Jadi ya, tetap saja penonton saya juga sedikit. Waktu kemarin di bioskop, sepertinya tahun lalu film judul “Nay,” film saya adalah film dengan penonton terendah pada tahun tersebut, mungkin hanya berapa ya, 4000 orang, sepuluh persennya dari buku.
Tapi saya sangat bersyukur, di semua medium kesenian selalu ada wadah-wadah dan selalu bermunculan komunitas-komunitas. Sekarang untuk film, ada banyak sekali komunitas yang memutar film di luar bioskop, di kafe-kafe, Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) salah satunya. Jadi, untuk film yang ke-4 ini yang tidak juga di bioskop, tapi mendapat kesempatan diputar di UWRF. Wah, senang sekali ya.
F
Anda bersama filmmaker asal Singapura – Kan Lume (K) – membuat film berjudul “hUSh.” Isu apa yang mau ditekankan kepada penonton lewat film ini?
D
K: Ada beberapa hal. Saya kenal Djenar untuk waktu yang lama dan melihat bahwa tema yang ia angkat dalam karyanya selalu sama, yakni isu tentang perempuan, mulai dari melawan abuse sampai hak perempuan. Jadi saya selalu mendukungnya sebagai teman dan ketika saya menyadari bahwa kami akan membuat film bersama, saya ingin mendukungnya lebih dari sekadar teman, melainkan menjadi co-director dan co-filmmaker juga.
Buat saya secara pribadi, saya suka membuat film, potret film tentang orang-orang, sama seperti ketika kita ingin melukis potret. Menurut saya, sinema bisa sangat intim dan bekerja layaknya lukisan potret. Jadi, film “hUSh” ini lahir dan terdiri dari kombinasik kedua elemen tersebut, tema yang familiar dalam karyanya dan gaya ala potret dalam filmmaking.
F
Bagaimana proses kreatif untuk film ini?
D
K: Saya secara pribadi menikmatinya sekali. Kami sangat cocok saat bekerja bersama dan tentunya sebelum mulai shooting kami bercanda, “Apakah kita akan bisa bersama juga (secara personal)?” Karena kita tidak pernah tahu, bagaimana kerja bersama sekaligus menjadi teman baik. Jadi, saat produksi tentu saja banyak momen yang menegangkan, tapi saya pikir kami mengatasinya dengan baik. Film ini digarap dengan gaya filmmaking yang tidak biasa Djenar lakukan, dan ia dikenal sebagai filmmaker yang sangat kritis terhadap tiap aspek ketika mengeksekusi sebuah film (tertawa). Saya pikir film ini membutuhkan hal yang berbeda dan tidak biasa untuknya, mungkin ia bergantung pada gaya filmmaking saya.
D: Jadi, waktu itu kami berteman dari tahun 2008 dan selalu bicara, “Mungkin tidak ya kita bikin film?” Sampai suatu saat saya menonton film Kan Lume yang berjudul “The Naked DJ.”
Tema saya selalu sama, perempuan, tapi dalam film dan juga dalam buku saya mencoba untuk menceritakannya dengan gaya yang berbeda. Ketika saya menonton film tersebut, saya berpikir bahwa ini adalah satu struktur bercerita, berkomunikasi yang saya belum pernah coba, dan sepertinya itu lebih direct kepada penontonnya, karena ini dibungkus seperti documentary, tapi ini adalah mockumentary. Jadi saya langsung bilang kepada Kan, saya tahu kita harus bikin apa, “I want to make a film like the Naked DJ.”
F
Film bisa menghibur hingga memicu perubahan sosial. Ketika “hUSh” diputar di Ubud Writers & Readers Festival nanti, respon seperti apa yang Anda harapkan dari penonton – mengingat ini adalah festival bertaraf internasional?
D
K: Saya telah membuat beberapa film sebelum “hUSh.” Saya sudah membuat 8 film dan juga mengajar tentang film. Jadi saya sangat memperhatikan aspek teknis dalam film karena saya merupakan seorang pengajar. Saya membuat “hUSh” dengan perfeksionis, saya melihat hasil final dari film ini dari sudut pandang teknis, tapi kadang ketika saya melihat situasi yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia, saya diingatkan betapa pentingnya pesan dari film ini.
Saya kadang lupa, karena saya pengajar, saya melihat film ini dari sudut pandang teknis, dan ketika saya melihatnya di media sosial, saya melihat dunia yang kita tinggali dan bagaimana seksisme masih menjalar, saya bilang ke Djenar, “Wow, film ini sangat pas dengan kondisi yang sedang terjadi.” Saya rasa, kami berdua perfeksionis dan seperti yang saya bilang tadi, pada aspek teknis, tapi ketika saya melihat apa yang terjadi di sekitar kita, saya bilang ke Djenar, “Wow saya sangat puas kita membuat film ini,” karena tidak cukup banyak orang membicarakan isu ini dan memang isu ini tabu untuk dibicarakan.
D: Kalau buat saya, mungkin karena saya bukan akademisi, dan saya juga otodidak yang tidak pernah belajar film atau sebagainya, saya tidak terlalu peduli masalah teknis. Masalah teknik itu justru muncul ketika memang film yang dikerjakan harus dikomunikasikan dengan cara yang berstruktur seperti yang sekarang kami lakukan di “hUSh”, dan memang harus begitu caranya. Tapi ketika saya menulis, saya selalu ingin berbagi sebuah realitas, dan itulah yang saya lakukan, mudah-mudahan bisa diterima, dilihat oleh lebih banyak orang, karena sekali lagi tema seperti ini tidak menarik bagi para executive producer film.
Kami kesusahan. Saya selalu kesusahan untuk mendapatkan executive producer. Pada film ini, Kan Lume yang menjadi executive producer. Tadinya saya bilang saya tidak mau bikin film kalau pakai uang sendiri atau pakai uang Kan, tapi akhirnya Kan bilang, “Mau nunggu sampai kapan? Gak bakalan, sudah bikin saja.” Jadi untuk itu saya juga grateful Kan menyuruh dan meyakinkan saya untuk terus buat film ini. Paling tidak lebih banyak orang, lebih luas orang yang melihat bahwa realitas ini sedang terjadi dan bagaimana kita menanggulanginya.
K: Memang mudah untuk terjebak dalam segala hal seperti distribusi perfilman. Saya pikir itulah yang saya tujukan ketika saya bilang ke murid saya. Kita bicara tentang film-film sukses dan terkenal. Saya sempat terfokus pada aspek tersebut sebentar, dan ketika saya kembali ke realita dan mendengar bahwa isu yang sedang terjadi, saya membahasnya dengan Djenar dan saya bilang, “Wow, film bisa menjadi lebih dari sekadar hiburan,” dan kami sangat senang menyadarinya.
F
Dengan adanya festival seperti Ubud Writers & Readers Festival yang menyediakan ruang diskusi dan ekspresi untuk penulis maupun pembaca, apakah kita bisa berharap mendapat perkembangan signifikan dalam dunia kreatif lokal?
D
Oh, sangat. Seperti yang baru saja saya sebutkan, untuk melakukan sebuah perubahan, saya selalu percaya bahwa perubahan besar itu harus dilakukan dari segala sesuatu yang mendasar dulu, mulai dari kita sendiri, lalu hal-hal dan wadah-wadah kecil seperti ini, tapi dampaknya menjadi banyak. Saya hadir di UWRF berkali-kali dan sejak dari awal festival ini dimulai, perkembangannya luar biasa, begitu pun dengan animo masyarakat.
Andai saya tidak diundang, saya selalu ingin datang, karena banyak sekali yang bisa kita ambil. Apalagi sekarang festival ini tidak hanya mengangkat penulis, tapi juga ada film. Ada banyak film yang belum saya tonton, tapi bisa ditonton di sini. Saya punya kesempatan untuk bertemu penulis-penulis dari mancanegara dan ternyata masalah atau kesulitan mereka itu juga sama saja, di mana-mana. Kita selalu punya kesulitan di tiap negara untuk menjadi seniman yang benar-benar ingin berkarya sesuai dengan keinginannya. Jadi, ya tentunya sangat membantu.
F
Tahun ini Ubud Writers & Readers Festival hadir dengan tema “Origins”, untuk menekankan toleransi. Melihat tema dan deretan diskusi yang akan ditampilkan nanti, apakah menurut Anda, tahun ini, festival tersebut sudah cukup membahas cakupan isu secara domestik maupun internasional?
D
Ya, karena masalah kita sekarang adalah “Apakah kita manusia yang memiliki perikemanusiaan?” Karena kita sekarang bisa melihat berbagai macam masalah dan tragedi yang sepertinya kadang kita melihatnya, “Itu benar manusia benar bisa melakukannya terhadap sesama manusia?” Jangan bicara apa yang kita lakukan terhadap binatang, sesama manusia saja kita bisa seperti itu.
Jadi, memang sepertinya sekarang kemanusiaan itu harus diangkat kembali kepada kita untuk mengingat sebenarnya kita sebagai manusia maunya apa? Hidup itu bukan perkara menjadi negara apa, agama apa, atau gender apa yang paling utama, tapi ya itu, untuk menjadi manusia saja. Belajar untuk menjadi manusia.
F
Ide atau isu apa yang Anda harap bisa dieksplorasi dari Ubud Writers tahun ini?
D
Saya pikir kalau sekarang memang temanya adalah kemanusiaan, dari sana kemanusiaannya saja sudah luas. Sangat, sangat luas. Jadi pasti akan banyak hal yang bisa diambil dari sana, seperti yang tadi sudah kita bicarakan; masalah agama, komunisme, LGBT, hingga ras. Banyak sekali.
F
Setelah film “hUSh”, proyek apa yang sedang Anda kerjakan?
D
Saya sekarang sedang menulis script, juga sedang menulis beberapa cerita pendek. Saya tidak tahu, mengalir saja nanti jadinya akan film duluan atau mungkin akan ada kumpulan cerpen. Saya tidak tahu.