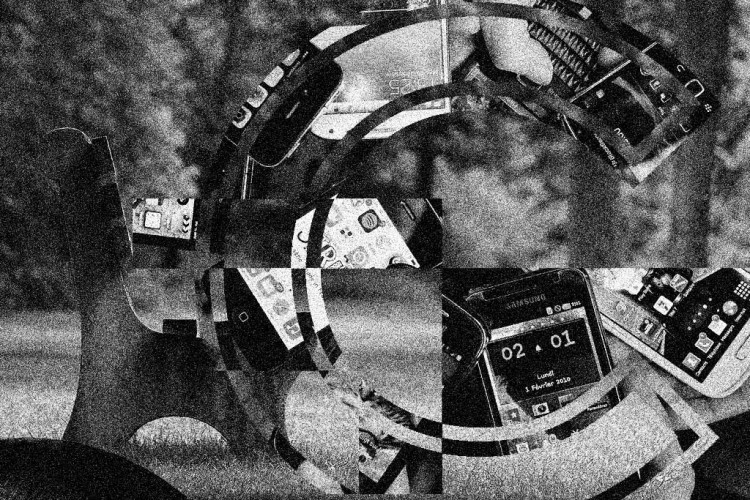Nick Drake: Keajaiban Upacara Pemakaman
Ulasan Buku dan Kisah Hidup Nick Drake

Dalam tradisi pemakaman dan ucapan tentang sosok meninggalkan, kadang ada bias pada kisah yang dituturkan. Kita cenderung mengenang kebaikan, inspirasi hidup dan tentu saja mitos mengenai sosoknya. Hal ini yang ada dalam pikiran saya, saat mengenang kematian Nick Drake, bahwa kisah tentangnya akan tetap menjadi mitos. Cerita tentang dirinya tetap menjadi misteri. Dengan minimnya kisah almarhum dalam wawancara, video dan catatan pribadi.
Kini saya membacanya dalam sebuah biografi. Agak sulit bagi otak saya untuk menggambarkan Nick Drake yang sesungguhnya, apalagi buku ini ditulis 24 tahun kemudian, yakni pada tahun 1998 oleh Patrick Humpries. Namun, ini tetap menjadi referensi baik mengenai musisi underrated, muda, inkonisten terhadap cara pandangnya sendiri, hasrat yang delusional – setidaknya begitulah ia diceritakan oleh orang-orang yang pernah terlibat hidup dengannya.
Nick Drake adalah kisah yang spesial, tentu saja. Ia lebih mudah digambarkan sebagai orang biasa ketimbang sebagai rock star. Kisah hidupnya, menjadi cermin bagi kehidupan musisi yang dekat dengan depresi, terutama berkaitan dengan kehidupan musisi selama ada dalam industri musik.
…
Dave Von Ronk – musisi penting di American Folk revival – percaya bahwa musiknya bukan untuk zamannya, musik masa depan; namanya hampir tidak dikenal di para penyuka musik folk, meski sempat muncul sebagai saksi hidup dan teman dekat Bob Dylan. Mungkin benar, musiknya melampaui pendengaran pada eranya; dia tidak berhenti mengeluarkan album sejak memasuki akhir 1950an hingga tahun 2002, sampai meninggal dunia di usia renta. Pada tahun-tahun awal bergulat di tengah industri musik yang menganak-emaskan rilisan-rilisan country dan gospel, musik Dave Von Ronk adalah anomali yang sulit dijual. Ia pun sempat depresi dan akhirnya berhasil bertahan hidup.
Kisah Dave memiliki kesamaan dengan riwayat Nick Drake, mereka tak di sana saat era folk sedang berjaya. Pun sama-sama memiliki musik yang melampaui apa yang disebut folk hari itu. Musik mereka bernada rendah, down-mood, menenangkan, kental dibalut semiotik, pesimis dan sama-sama pemalu.
Di Amerika Serikat, ketika Dave Von Ronk membuat inovasi penting dalam musik yang membuat jenis musiknya kala itu terdengar asing dengan nada-nada lagu yang banyak mencampurkan genre di tengah budaya musik country dan gospel yang memaknai musik sebagai milik umat, commune, kolektif dan gambaran kelompok masyarakat di era 50an akhir sampai memasuki era 60an. Di Inggris, Nick Drake datang dengan musik yang lebih mudah dinikmati secara privat, ia ada di antara 60an dan baru saja memasuki 70an, di mana orang-orang bersemangat memainkan musik, yang bergema dengan vokal yang terkesan culas, ekspresif, dimabukan oleh bius suara synthetizer, dinina-bobokan mistiknya piano hammond, gesekan melodi bluesy dan atraksi drum yang multi disiplin genre.
Rock ‘n roll masih dalam usia muda, ia memiliki sejarah berbeda dengan folk; mereka hidup identik dengan fantasi, bercerita tentang diri, kebebasan, glamour, flamboyan, hedon, simbol seks dan maskulinitas. Hal ini dekat dengan ciri rock star dekat dengan mitos dan ritual hidup yang diagung-agungkan unik dan ajaib. Stereotipe musisi folk seakan dituntut tajam menganalisis hidup masyarakat, budaya, ekonomi dan kondisi politik.
Era 50 akhir hingga 70an, dunia penulisan dan sastra begitu dekat dengan musisi. Orasi dengan puisi tidak menjadi pertunjukkan langka atau hanya hadir saat pentas seni sastra dan demonstrasi. Mereka masuk dalam performa yang diperhitungkan, terutama selama pasca perang dunia II dan masa perang dingin. Para musisinya pun begitu lekat dengan penyair, syair-puisi dan aktivisme saat itu; nama-nama popular seperti Janis Joplin, John Denver, Joan Baez, Neil Young dan Woody Guthry, meski Woody sudah tidak bisa tampil lagi karena menderita schizophrenia di akhir hidupnya. Nama-nama itu adalah jagoannya, dengan lirik bagai puisi yang lugas menyuarakan kondisi politik dan sosial. Sering pula dibarengi acara-acara di panggung bebas tanpa tiket; di White House, di peternakan, di tengah demonstrasi berbarengan dengan pembacaan puisi. Dunia kepenulisan begitu mempengaruhi lirik-lirik musisi era 60an sampai 70an. Menyuarakan kondisi politik dan sosial secara lugas menjadi pakem folk saat itu. Namun, berbeda dengan Nick Drake. Objek utama bagi dirinya adalah subjek, alias diri sendiri; permasalahan, tentang sepi, tentang kontemplasi diri yang dikemas dalam lagu yang kontemplatif pula.
Maka, tentu Dave dan Nick mendapat tantangan dari tren musik, semangat zaman, belum lagi isu atau tema lirik yang mereka bawa hari itu bisa disebut baru dan asing. Mereka ibarat Nikola Tesla dengan temuannya yang futuristik, tahan lama dan ekonomis; diadu dengan industri elektrik Thomas Alva Edison yang boros energi, tidak tahan lama dan butuh pembaharuan yang lamban agar orang menunggu inovasi perlahan, terus membeli dan mengganti – bentuk yang lebih menguntungkan dan lebih disukai para kapitalis – lagian teknologi Edison sudah semua orang nikmati, tepatnya terlanjur dinikmati. Mengubah selera dan budaya tidaklah mudah jika berhadapan dengan raksasa bernama industri.
Dave Von Ronk dengan bebalnya berkata, “Karyaku adalah musik masa depan, peduli setan dengan tren hari ini.” Sayangnya, hanya segelintir yang menyadari kualitas karyanya, sampai pada titik ia bertemu Bob Dylan di sebuah klab kecil di awal 60an. Kelak Dylan dan Von Ronk menjadi sahabat yang saling memberi kritik dan inspirasi. Ini membuat Dave menjadi narasumber kompeten dan orang dekat Dylan dalam dokumenter “No Direction Home”. Sempat pula difilmkan kisah hidupnya, dengan nama Llewin Davies dalam film “Inside Llewin Davies” (mengambil judul album Dave: Inside Dave Von Ronk).
Pun demikian, Dave Von Ronk pun tidak laku, padahal ia sangat apik mencampurkan country-blues-jazz-ragtime dalam musiknya, cukuplah untuk disebut “folk kafir” hari itu. Nick Drake? Sama, sama-sama membawa warna baru dalam musik folk dan memiliki ide yang hampir serupa. Lalu apa yang membuat kini Nick Drake lebih banyak dibahas ketimbang Dave Von Ronk? Adalah kematian jawabnya.
Kematian membuat Nick Drake dihidupkan lagi oleh kakaknya yang selebriti: Gabriel Drake, ia juga termasuk orang yang sangat beruntung yang banyak sekali dibantu oleh tim rekam yang canggih yang berasal dari pentolan-pentolan band legendaris folk rock kala itu, seperti: Dave Mattack dari Fairport Convention, John Cale dari Velvet Underground, Robert Kirby yang aktif dalam skena country, Mike Kowalsky dari Beach Boys, dan masih banyak lagi. Jadi berterimakasihlah mitos Drake ini dikenalkan lebih luas dipromosikan melalui Gabby (Gabriel Drake) dan orang-orang hebat yang sukarela berbagi cerita tentang Nick Drake dalam buku Patrick Humphries. Sebagaimana musisi hari ini bisa dikatakan bagus, kadang perlu orang yang tepat dan memiliki power dalam skena musik dan media, sesungguhnya Nick Drake telah diberikan kesempatan dan jaringan yang besar dalam proses pembuatan albumnya ketika ia hidup.
Ada satu faktor internal yang membuat karirnya fatal, yakni posisi yang diambil Nick Drake dalam industri musik: komunikasinya yang terbatas, ia yang pemalu, tidak terbuka, mudah kecewa sebab ekspektasi yang terlalu tinggi, hanya mau berada di panggung besar sementara namanya tidaklah populer. Hal seperti ini, mestinya sudah diselesaikan oleh musisi sebelum ia masuk pada industri musik: ia mengetahui resiko, mengenal peta tren musik hari itu, bagaimana ia melihat audiens dan audiens yang bagaimana sih yang ia mau? Dan yang terakhir, bagaimana ia memberikan keuntungan bagi perusahaan rekaman dan untuk dirinya sendiri. Sayangnya, meski cerita ini disusun dengan banyak kontribusi dari musisi-musisi handal era 60-70an, tapi justru menyisakan miris karena para narasumber ini didapat jauh setelah Nick Drake wafat.
Ini membuat saya mengingat kembali kisah tentang wafatnya Kurt Cobain yang membuka perbincangan mengenai depresi, perjalanan musik, pengaruhnya pada anak muda. Kisahnya ada, karena ia cukup sadar perihal pendokumentasian: adanya buku harian, lukisan-lukisannya dan footage yang terawat. Jadi agak mengganggu bagi saya untuk mendapatkan review dan sejarah yang pas untuk Nick Drake, sebab cerita ketika dia hidup begitu sedikit dan justru jadi beranak pinak saat ia tiada, Nick Drake tidak punya buku harian atau rekaman wawancara yang meyakinkan saya, bahwa buku Patrick Humphries ini cukup komprehensif.
Nick Drake tidak punya gimmick yang bisa membuatnya sensasional ketika hidup. Jadi saya pikir, Nick Drake ini bisa jadi dibesarkan oleh sensasi kematiannya yang dilupakan begitu saja, layaknya ucapan memorial upacara pemakaman, inilah gimmick yang akhirnya ditemukan: bahwa di masa lalu, terdapat musisi demam panggung yang juga suka mabuk, perfeksionis, jenius, sempat dibantu band-band legendaris, namun… kok tidak terkenal? Ohya, bunuh diri? Kok bisa?
Buat saya, yang, semisal baru dengar? Wah, menarik sekali! Ya, industri, tetaplah industri, perlu nilai jual yang bombastis bukan?
Kalau boleh membandingkan, pembeda Nick Drake dengan Chester Bennington adalah fakta bahwa Linkin Park tenar ketika hidup. Sedangkan Nick Drake, hidup-matinya senyap dan nyaris tak hadir di majalah-majalah musik dan koran. Chester Bennington cerita hidupnya beredar beberapa jam setelah kematiannya. Sedangkan Nick Drake baru membuat penasaran para jurnalis 5 tahun setelah kematiannya.
Tapi, Chester Bennigton dan Nick Drake dengan kematian dan pengalaman pahitnya memiliki kesamaan. Yakni nilai-nilai baru di diri mereka yang muncul setelah kematian, seolah-olah cemooh, kritik dan perjuangan tetap hidup mereka di atas pengalaman pahit itu kalah oleh kematian yang tragis dan membuat lagu-lagu mereka semakin dimengerti ketika yang membuatnya sudah tiada. Sebagaimana proses pemakaman untuk mengenang almarhum, kita seakan menjadi kenal lebih dekat dengannya. Kedua: musik mereka adalah sebuah data penting tentang depresi yang dialami, musik sebagai goal bahwa musik mampu menyampaikan pesan tentang hal yang rumit dimengerti: depresi. Beserta bonus kisah-kisahnya setelah kematian itu ada. Ketiga: bagaimana musisi bisa melihat industri musik; dukungan, fans, target penjualan dan resikonya; baik terkenal atau tidak secara tepat sesuai dengan keinginan musisi memperlakukan musiknya.
Bagi saya Nick Drake adalah manusia songong, belum sampai tahap Chester Bennington dan Bob Dylan. Sekali lagi, ia belum tuntas menyelesaikan persoalan internalnya sebagai musisi.
Ego seorang seniman mana pun yang gigih dan percaya bahwa musiknya berbeda, layak, bahkan melampaui batas; seringkali angkuh dan delusional. Sebagaimana Kurt Cobain yang dalam wawancara-wawancara lepas menganggap musik musisi lain hanya mengikuti zaman atau mencari aman saja dalam aransemen, bahkan berkata dalam lirik yang pasaran dan tidak idealis, sempat ditujukan pada Peal Jam kala itu. Di era 90an terdapat seseorang yang seperti ini juga di Inggris, Liam Galagher. Dan di 90 akhir dari Limp Bizkit, Fred Durst.
Nick Drake pun ada di antara mereka, seperti musisi-musisi sampai hari ini yang percaya pada musiknya dan memiliki standartnya sendiri. Baik dalam standar tinggi atau hanya memainkan konsep. Ini adalah masalah sosial dan keadaan skena saat itu di mana Inggris ketika itu sedang dimabuk psycheledic dari para musisi setempat dan pengaruh folk rock dari Amerika Serikat. Bagaimana sebuah musik yang baru mampu berkompetisi di dalamnya dan menarik?
Musik seperti Drake adalah “musik lama” yang mengalami evolusi dalam periode transisi tren (ia masih dalam keluarga genre folk yang tengah mengalami percampuran dari tren rock n roll, blues dan psychedelic). Jika saja Drake sabar sedikit saja bertahan hidup, akhir 70’an sampai 80’an awal – yaitu ketika Inggris mengalami goncangan ekonomi yang kemudian memicu gerakan sosial, perlawanan, dan semangat kolektifitas yang lahir dari punk dan di Amerika Serikat represi kebebasan berekspresi oleh Ronald Reagan yang berpengaruh pada budaya populer saat itu justru melahirkan musik-musik kala itu semakin liar – musisi pemalu seperti Drake mulai bermunculan sebab tekanan politik dan ekonomi yang terjadi pada masa itu. Tradisi pertunjukan glamour mulai usai, dan berganti dengan pertunjukan di garasi rumah. Mereka mulai berbicara tentang apa saja, dengan gila-gilaan, dengan depresif malahan, dan dengan konsep musik yang sangat beragam betul akibat tekanan itu tadi – dan dibantu dengan merajalelanya tradisi DIY dan zine, di mana jalur-jalur alternatif terbuka lebar bagi para musisi dengan kepala bebal bisa berekspresi dengan leluasa.
Jika saja Drake sabar sedikit saja bertahan hidup…
Lalu apa yang membuat dia tidak mampu bertahan? Mengapa musisi atau seniman menjadi sorotan depresi? Mengapa bukan buruh pabrik Foxconn yang rentan dengan depresi dan kematian mereka begitu tidak terdengar?
Bicara tentang depresi usia muda pada musisi. Kita bisa lihat depresi tiap dekade memiliki khasnya sendiri-sendiri seperti yang dibahas tadi. Jika kita amati musisi yang dikenal luas hidupnya penuh sensasi dan berakhir naas, seperti: Jim Morrisson, Janis Joplin, Kurt Cobain dan Sid Vicious. Memiliki khas depresinya sendiri, cukup lama dengan dunia musik profesional, bagaimana musisi dieksploitasi dan menyengajakan diri mengeksploitasi diri mereka, belum lagi masalah budaya dalam kehidupan rock star itu sendiri.
Kita bisa melihatnya pada film berjudul “Rock Star”, yang terinspirasi dari band legenda Judas Priest. Dalam kisah di film tersebut, para rock star ini menjalani tur tanpa henti, bertemu orang yang itu-itu saja (manajer, road manajer, groupist, fans) dan yang menjadi hiburan adalah seks dan obat-obatan yang tidak perlu dicari, obat-obatan itu selalu tersedia layak barang legal yang siap kamu pakai sesuka hati. Damn! Ini kan sama saja nasibnya dengan buruh pabrik yang diperas kehidupannya.
Sementara saya terus dihantui pertanyaan, bagaimana dengan Nick Drake? Albumnya tidak laku, belum pernah tour sepanjang Judas Priest tanpa istirahat, dan ia tidak sampai tahap memohon untuk menghentikan tour akibat kelelahan karena jadwal yang terlalu padat dan berkata, “Aku ingin pulang, pokoknya aku ingin pulang!” seperti Bob Dylan dalam film dokumenter “No Direction Home”.
Konsentrasi saya terhadap depresi pada sosok musisi di Eropa dan Amerika, tentu saja berbeda dengan Indonesia yang mana norma sosial dan keluarga begitu lekat. Nilai-nilai liberal yang mengutamakan individu seperti Amerika, pastilah punya kaitan penting bagaimana individu melihat depresi dan bunuh diri. Yang tentu buat saya, budaya sampai situasi politik tidak bisa disamakan di negara lain itu tadi.
Namun, depresi pun bisa menjadi inspirasi yang menjadi lintas budaya, politik dan negara bagi fans bahkan kita yang hanya mendengar dan membaca berita tentang kematian disebabkan bunuh dirinya musisi. Berikut saya ceritakan kisah inspirasi bunuh diri dari mitos urban legend dan berlanjut menjadi teror di Eropa sampai Amerika:
Puisi Laszlo Javor, berjudul “Smoru Vasarnap” atau “Minggu Kelabu” dengan bentuk pertunjukan teaternya bernama: Hungarian Suicide Song. Puisi tersebut dijadikan lagu, diaransemen oleh Rezso Seress pada tahun 1933. Di lirik tersebut diceritakan seseorang yang ingin membunuh dirinya demi menunjukkan rasa cintanya pada kekasihnya yang telah mati. Lagu ini menjadi folklor, urban legend di Hungaria, dan menjadikannya mitos yang diceritakan di radio-radio, bahwa lagu ini memicu keinginan bunuh diri.
Pada tahun 1936 lagu ini digubah dalam bahasa Inggris diartikan menjadi “Gloomy Sunday”, direkam di Inggris oleh Hel Kemp dan lirik oleh Sam S Lewis. Pada tahun 1941 Billie Holliday merekamnya kembali, menjual mitos bahwa Gloomy Sunday bisa membuat yang mendengarnya memiliki keinginan bunuh diri. Maka persoalan bunuh diri melihat sejarah ini menjadi tidak sederhana, ketika tercatat menginspirasi menjadi kenyataan bahwa lagu ini dipercaya mampu membuat seseorang memiliki keinginan tersebut. Konon, banyak sekali orang bunuh diri sepanjang lagu ini pertama kali dibuat sampai era Bjork menyanyikan lagu ini. Inspirasi dan mitos, jika dilihat dari sejarah kelam ini, berbahaya juga.
Sebagaimana Kurt Cobain memutar “Everybody Hurts” milik R.E.M untuk meyakinkan dirinya bunuh diri dalam buku “Havier Than Heaven” yang ditulis Charles Cross. Buat saya, bunuh diri memang sudah ada kaitannya dengan masa lalu dan masalah yang berangsur-angsur hidup dalam diri orang tersebut. Namun, alangkah berbahayanya mitos lagu-lagu ini menjadi sakral sebagai pengiring kematian dan menjadi inspirasi oleh media atau mitos yang beredar dari mulut ke mulut.
Contoh kasus mitos seperti di atas, menjadi inspirasi yang menyesatkan dan merugikan pada penderita suicidal thought. Mitos yang berlangsung lama tersebut, kini banyak beredar kembali, jika dulu dari mulut ke mulut, kini beredar jadi opini di dunia maya: depresi tidak bisa diselamatkan logika dan pengetahuan. Padahal jelas tidak begitu, depression can be cured. Tentu dengan logika pengetahuan. Bisa jadi, banyak penderita depresi sulit keluar dari masalah dirinya, salah satu penyebabnya adalah stigma dan mitos tersebut. Yang membuat para penderita semakin pesimis untuk hidup.
Dalam catatan Dianna Theodora Kenny dalam bukunya: Music Performance Anxiety (2015), tercatat 12.665 musisi populer yang meninggal dalam rentang waktu 1950 sampai Juni 2014, 90%-nya adalah laki-laki, dengan penyebab kematian yang dikumpulkan dari berbagai sumber; kematian sebab jantung, kanker dan bunuh diri adalah penyebab yang paling besar terjadi pada musisi. Sebanyak 4,6% musisi meninggal akibat bunuh diri.
Temuan lain dari Center for Suicide Research, ditemukan bahwa musisi tiga kali lipat tingkat bunuh diri mereka ketimbang orang biasa. Salah satu penyebab terbesar adalah: kreativitas dan lingkungan.
Kebanyakan musisi populer yang bunuh diri menderita manic depression dan bipolar. Kebanyakan memiliki karakter yang sama: perfeksionis dan menderita 2 gangguan mental itu tadi yang membuat musisi ini menjadi rapuh. Perfeksionisme terkait beberapa hal: manajemen, target musik yang ia perkirakan (ekspektasi), kreativitas (aransemen) dan perlakuan orang lain terhadap musik dan dirinya. Perfeksionisme dekat dengan narsistik.
Nick Drake sempat dibahas, bahwa ia pun mengalami depresi dengan penyebab yang sama, yang membedakannya adalah ia belum mencapai tingkat musisi populer ketika memutuskan mati. Sepanjang karirnya ia berhasil membuat 31 lagu yang dirangkum dalam 3 album. Dalam catatan, ia pun frustasi melihat tatahan yang salah pada album “Five Leaves Left”.
Selama proses pembuatan dan pasca album Bryter Layter, Nick Drake semakin perfeksionis, sebagaimana yang diungkapkan Michael Chapman, “Penonton ingin musik yang punya chorus. Nick Drake, bukan musisi macam itu; akhirnya penonton tidak memahaminya. Rasanya sakit kalau dikenang.” Apalagi Nick Drake ini ingin jika penonton menikmatinya dengan keadaan hening.
Dalam sejarahnya, musiknya tidak memiliki kharisma bagi kalangan tertentu, atau memang kharismanya tidak tepat zaman, atau punya standar bahwa musiknya buat kalangan yang mengerti musiknya saja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat SMU Nick Drake, Michael Maclaran, “Nick adalah seorang penampil, meski orang-orang datang menontonnya, dan kebanyakan dalam pengaruh alkohol, di pertunjukkan itu tidak pernah ada nyanyi bareng. Dia tidak memainkan untuk khalayak…” (Patrick Humphries, Nick Drake: Sebuah Biografi).
Ekspektasi besar terhadap musik, tanpa kharismanya ketika di atas panggung dengan alasan grogi menambah alasan untuk frustasi. Selain penjualan album yang melempem dan ambyar membayar tawaran Island Records mempromosikan albumnya di atas panggung. Jelas depresi Nick, bukan hal yang tiba-tiba, namun kekecewaan dan gagalnya mengatasi diri yang terus menumpuk dalam 3 tahun terakhir di kehidupannya.
Tahap depresinya, tidak bisa dilihat dari satu sisi, bahwa ia gagal dalam bermusik saja. Karena dia juga memiliki masalah drugs, yaitu: resep (saran dokter atau psikolog) atau non-resep (sebagai narkotika) yang mana keduanya dikonsumsi untuk mengatasi persoalan depresi, yang malahan menimbulkan depresi baru, yang tentu sedikitnya mempengaruhi ia tidak dapat berpikir jernih dan menemukan solusi. Keterpurukkan ini menjadi hantu tentang kegagalan atau rasa salah.
Gagal menjadi musikus, narkotika dan ekspektasi. Nick pulang, ia tidur lebih awal malam itu dan menenggak amitripyiline sebanyak 30 buah yang membuatnya tidak pernah bangun lagi.
…
Bagaimana pun, Nick adalah orang beruntung yang dikelilingi orang musisi-musisi besar, media-media berpengaruh, berasal dari kaum menengah atas (tidak seperti kebanyakan band saat itu yang berasal dari keluarga menengah ke bawah). Bagaimana pun juga, industri kapital dalam musik, tidak akan berpihak pada musik yang mana musisinya membuat musik yang hanya untuk dirinya sendiri dan menunggu orang untuk mengerti dirinya.
Nick Drake telah menyia-nyiakan bantuan orang lain dalam proses pembuatan album-albumnya dengan komunikasinya yang buntu. Satu hal yang tidak saya temukan tentang Nick Drake: respect untuk menghargai bantuan tersebut, bukan berarti depresinya tidak ada yang menolong, namun ia dibutakan oleh ego dan ekspektasi yang buruk. Ini pun yang menjadi kritik yang semestinya muncul, tidak sekadar ucapan pujian, rasa kasihan dan kata-kata inspiratif saja di dalam upacara pemakaman terhadap almarhum. Ego dan kurangnya respect telah menenggelamkannya sebagai manusia yang dibesarkan kesopanan a la Inggris yang kaku menjadi miskin untuk berterima kasih dan mensyukuri dukungan terhadapnya.
Meski pun tidak dapat dipungkiri, kehidupan bermasyarakat semakin hari membuat hampir semua dari kita ingin mengakhiri hidup sendiri; baik itu memaksa kita lari, berhenti, menertawai atau tenggelam mengasihani diri. Kematian Nick Drake, bisa jadi membangkitkan kesadaran dan kepedulian akan depresi pada kaum muda dalam industri musik menjadi lebih asyik dipelajari bukan sekadar bicara tentang estetika dan hal-hal delusif lainnya. Semoga.
Jika kita banyak dibius oleh keagungan musisi beserta kejeniusannya, buku “Nick Drake: Sebuah Biografi” kita diberikan alternatif yang jarang ditemui di buku biografi lain: musisi muda naif, pandir dan delusional yang tidak jadi rock star.
Selamat untuk Al Mukhlisiddin menerjemahkan buku “Nick Drake: Sebuah Biografi” Dengan penerjemahan yang cermat dan nyaman dibaca.
***
Everybody have a problems; knowledge, logic and respect should be the best healer for us.
Yogyakarta, 27 Juli 2017.
Referensi:.
Patrick Humphries (1998), diterjemahkan oleh Al Mukhlisiddin (2017). Nick Drake: Sebuah Biografi. Jungkir Balik Pustaka.
Dianna Theodora Kenny (2011). Defining Music Performance Anxiety. Oxford Press.
Dianna Theodora Kenny (2015). Music Performance Anxiety. Oxford Press.
Ben Holtzman, C. H. (2007). Do It Yourself…and the Movement Beyond Capitalism. In D. G. Stevphen Shukaitis, Constituent Imagination: Militant Investigations, Collective Theorization (pp. 44-61). Oakland: AK Press.
Ciccariello, Maher. (2016) Building a Commune Radical Democracy in Venezuela. London: Verso
Stepven Shukaitis, D. G. (2007). Constituent Imagination: Militant Investigations, Collective Theorization. Oakland: AK Press.
“Nick Drake: Keajaiban Upacara Pemakaman” ditulis oleh:
Galih Su
Musisi folk – nyaris heavy rock, dengan nama palsu Deugalih. Aktif mengajar di sekolah inklusif Jogja Green School.