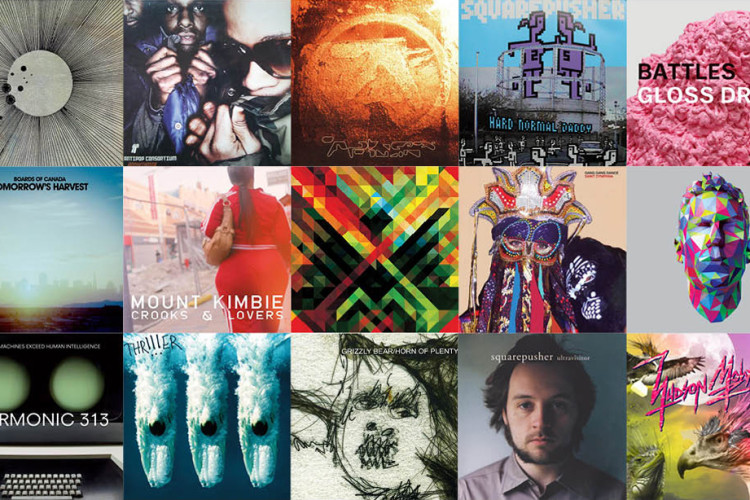Data sensus penduduk Badan Pusat Statistik (2010) tentang jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut pada tahun 2010 menunjukkan bahwa presentase penganut agama Islam di Indonesia terdiri dari 207,176,162 jiwa. Angka tersebut, setidaknya, sudah mewakili 87 persen dari keseluruhan data yang terkumpul, yaitu 237,641,326 jiwa. Hal tersebut ini sekaligus melegitimasi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia.
Sementara itu, dilansir dari laporan tirto.id pada 5 September 2017 yang mengulas tentang hasil sensus penduduk yang dilaksanakan oleh Department of Population, Ministry of Labour, Immigration and Population Myanmar pada tahun 2014, jumlah umat Muslim non-enumerated yang berada di negara bagian Rakhine, Myanmar, saat ini diperkirakan mencapai sekitar 1,12 juta jiwa.
Kedua fakta statistik yang tersaji di atas sepertinya dapat sekaligus berperan sebagai premis sederhana yang berujung pada terciptanya aksi solidaritas terhadap etnis Rohingya di Indonesia dengan intensitas yang cukup besar belakangan ini.
Meskipun, bagi Indonesia sebenarnya ini bukanlah kali pertama aksi solidaritas digelar dengan skala yang cukup besar. Dapat kita ingat dengan baik bahwa di setiap kesempatan, masyarakat dan pemerintah Indonesia selalu turut berempati terhadap musibah yang terjadi di berbagai belahan dunia.
Sebagai contoh yang mungkin masih melekat di ingatan kita, Indonesia terbilang sangat proaktif dalam menggelar aksi solidaritas saat terjadi agressi militer Israel di Palestina, tragedi kemanusiaan di Aleppo, serta apa yang sebelumnya terjadi di Mesir. Bagi saya, aksi solidaritas semacam ini sangat perlu disambut baik.
Lebih jauh tentang itu, jika dianalisa secara sederhana, saya percaya bahwa kemunculan aksi solidaritas, khususnya yang menyangkut kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya dan umumnya pada kasus lain yang pernah ada, dapat terjadi karena (setidaknya) adanya dua bentuk keterikatan sosial dimana pemerintah dan masyarakat Indonesia terlibat aktif di dalamnya.
Bentuk yang pertama adalah keterikatan terhadap hukum dan norma internasional. Sikap yang ditunjukkan langsung oleh kepala pemerintahan Indonesia melalui berbagai pernyataan resmi dan tindakan terhadap otoritas Myanmar, merupakan salah satu bentuk manifestasi tanggung jawab negara sebagai subjek hukum internasional yang tunduk pada hukum dan norma internasional yang berlaku, serta turut berusaha mewujudkan kondisi internasional yang stabil.
Hal ini sejalan dengan penjelasan Finnemore dan Sikkink (1998) mengenai konsep norma internasional pada karyanya yang berjudul “International Norm Dynamics and Political Change.” Dalam tulisannya, Finnemore dan Sikkink menjelaskan bahwa norma internasional adalah norma yang sifatnya menentukan apa yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan oleh negara-negara (standard of appropriate behavior). Sementara, norma tersebut lahir dari adanya norma domestik yang secara terus menerus dipromosikan oleh kehadiran sebuah aktor di belakangnya.
Dalam konteks Indonesia, saya rasa hal tersebut sepertinya dapat ditekankan pada kenyataan bahwa, sebagai negara yang pernah dijajah dan sekarang sudah merdeka serta berdaulat, Indonesia tidak menginginkan adanya bangsa manapun di dunia yang masih berada dibawah tekanan penjajahan. Dalam ranah internal, keinginan ini rupanya sesuai dengan apa yang tertulis dalam paragraf pertama pembukaan Undang Undang Dasar 1945, “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”
Kemudian, jika merujuk terhadap konteks yang dibangun pada tiga paragraf pertama dalam tulisan ini, kita dapat melihat bahwa bentuk keterikatan sosial yang kedua dibangun dari adanya kesamaan yang dimiliki oleh Indonesia dan etnis Rohingya dalam aspek kepercayaan (agama) yang dianut. Dimana keduanya sama-sama, secara statistik, didominasi oleh umat Muslim.
Dari kedua bentuk keterikatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan awal bahwa, baik dari segi tanggung jawab negara sebagai sebuah entitas internasional maupun dari segi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, keduanya sama-sama berusaha untuk merangkul sebuah norma moral yang ideal yang mampu mewujudkan kondisi kemanusiaan yang jauh lebih baik bagi etnis Rohingya.
Kedua keterikatan tadi, disadari atau tidak, telah berhasil mengikis batasan-batasan politik dan budaya yang bersifat teritorialitas yang sebelumnya membatasi banyak aspek yang ada di antara publik Indonesia dan masyarakat etnis Rohingya. Keduanya sama-sama ingin mewujudkan kehidupan yang layak bagi etnis Rohingya baik sebagai bagian dari masyarakat internasional, maupun sebagai bagian umat Muslim yang ada di seluruh dunia.
Dalam ranah ilmu filsafat, konsep keterikatan semacam ini dikenal juga dengan istilah kosmopolitanisme (Kleingeld & Brown, 2002). Secara sederhana, istilah ini menjelaskan bahwa seluruh umat manusia tergolong kedalam satu komunitas yang disatukan oleh kesamaan nilai-nilai yang dianut sebagai “warga dunia” (citizen of the world).
Dalam kata lain, asosiasi masyarakat yang digambarkan oleh ideologi kosmopolitanisme diilustrasikan telah melampaui dari sekadar batas status kewarganegaraan. Melainkan, ada hal lain yang, menurut beberapa versi, dapat dijadikan sebagai medium asosiasi seperti nilai moralitas yang dijunjung, struktur politik, kebudayaan, dan hal lainnya yang cenderung bersifat inklusif.
Immanuel Kant (Johnson & Cureton, 2004), salah seorang filsuf yang turut berkontribusi dalam perkembangan ideologi kosmopolitanisme, berargumen bahwa terdapat sebuah prinsip moralitas utama (Categorical Imperative) yang sifatnya harus diikuti oleh negara-negara tanpa terkecuali dalam rangka menciptakan kondisi perdamaian yang abadi (perpetual peace).
Memang terkesan begitu ambisius. Namun, Kant sepertinya ingin mencoba menegaskan bahwa dalam upaya mewujudkan standar moralitas internasional, diperlukan sebuah ketertiban dari setiap pihak (baik negara ataupun individual) dalam mengikuti prinsip-prinsip yang sudah ditentukan sebelumnya.
Di luar itu, kompatibilitas kosmopolitanisme dengan agama mungkin masih menjadi pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Namun, tulisan ini setidaknya mencoba menangkap sebuah sudut pandang dimana kedua bentuk keterikatan yang melahirkan aksi solidaritas di Indonesia, sebenarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi seperti yang dideskripsikan oleh Kant.
Kosmopolitanisme Kontraproduktif
Jika merangkum dari argumen yang tersaji di atas, dapat dikatakan bahwa aksi solidaritas terhadap etnis Rohingya mucul sebagai sebuah hasil dari kehadiran pandangan kosmopolitanisme di tengah masyarakat Indonesia. Namun, apakah niat baik dari aksi solidaritas “tanpa batas” ini selalu akan berujung baik? Hal apa yang dapat muncul sebagai sisi rentan dari gerakan semacam ini?
Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kasus Rohingya, terdapat lebih dari satu variabel yang dapat dikatakan sebagai sumber masalah kasus tersebut. Setidaknya, ada tiga aspek umum yang paling sering dianggap sebagai akar penyebab dalam bentuk analisis masalah; agama, politik, dan ekonomi. Dalam kerangka kerja ideologi kosmopolitanisme, aspek seperti agama, politik, maupun ekonomi juga diposisikan sebagai nilai – nilai yang dibagi (shared values), yang kemudian menjadi titik awal munculnya motivasi bagi sebuah aksi solidaritas transnasional.
Di sinilah yang saya anggap menjadi salah satu kelemahan dari kosmopolitanisme. Jika secara normatif semua shared values memiliki tujuan utama mewujudkan kehidupan yang layak bagi etnis Rohingya dengan mengedepankan prinsip keadilan HAM. Secara praktis, dengan segala keabstrakan yang meliputi sifat manusia, saya tidak melihat adanya mekanisme yang dapat menjamin tujuan normatif tersebut aman dari adanya tumpang tindih ataupun penyimpangan berlandaskan shared values yang justru membuatnya menjadi eksklusif. Misal, jika sebuah kelompok merasa memiliki keterikatan atas dasar kemiripan budaya, maka bisa saja tujuan untuk menciptakan keadilan HAM tergeser oleh tujuan untuk menyelamatkan kemiripan budaya.
Sementara, Thomas Pogge (1992) dalam tulisannya yang berjudul “Cosmopolitanism and Sovereignty” menyebutkan, ada tiga elemen yang dimiliki oleh setiap keadaan kosmopolitanisme; pertama, individualisme, dimana perhatian utama haruslah merupakan manusia (human beings) dan/atau orang (persons) dan bukan merupakan hal-hal seperti garis keluarga, suku, etnis, budaya, komunitas keagaamaan, bangsa atau negara. Kedua, universalitas, dimana perhatian tersebut tidak terkotak-kotak oleh subset seperti gender, kelas sosial, ras, warna kulit, ataupun agama. Ketiga, kemumuman (generality), dimana perhatian ini harus memiliki kekuatan global dan ditujukan untuk semua tanpa dibatasi afiliasi teman sebangsa, seagama, dan yang sejenisnya.
Salah Alamat
Kemudian, apakah dari sekian banyak aksi solidaritas yang sekarang muncul sudah memperlihatkan adanya potensi penyimpangan? Saya menjawab, mungkin saja sudah.
Salah satu yang menjadi perhatian saya adalah rencana gelaran aksi yang berjudul “Aksi Bela Muslim Rohingya” yang dilakukan dengan cara mengundang sejuta umat untuk “mengepung” lokasi Candi Borobudur pada Jumat, 8 September 2017. Digunakan tanda kutip, karena saya belum dapat memastikan apakah aksi ini secara harfiah ingin mengelilingi lokasi Candi yang berluas sekitar 2.500 meter persegi tersebut, atau hanya sekedar ungkapan metaforik saja. Namun jika melihat dari besarnya masa yang diundang, sepertinya memungkinkan untuk opsi yang pertama.
Konon katanya, Candi Borobudur dijadikan tujuan dari aksi tersebut karena merupakan Candi Budha terbesar di dunia. Bahwa dengan melakukan aksi “pengepungan” ini, peserta diharapkan mampu menyampaikan “…ke penduduk dunia STOP PEMBANTAIAN MUSLIM ROHINGYA.”
Namun, kembali, apakah aksi ini tepat sasaran? Atau justru salah alamat? Mari kita perhatikan pernyataan berikut. Dilansir dari laman berita Tempo, 5 September 2017, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian malarang sejumlah organisasi masyarakat yang akan berunjuk rasa di kawasan Candi Borobudur. Ia menegaskan bahwa kasus Rohingya tidak ada kaitannya dengan agama tertenu. Menurutnya, lokasi tersebut bukanlah merupakan milik dari umat tertentu, melainkan sudah menjadi destinasi wisata bagi banyak orang sekaligus warisan yang seharusnya dijaga.
Pernyataan tersebut secara langsung menyentuh beberapa poin penting yang ingin kemudian saya bahas kedalam analisis singkat. Pertama, konflik Rohingya bukan merupakan konflik agama. Mengenai poin ini, setidaknya saya menemukan dua analisis yang menjelaskan akar permasalahan konflik Rohingya.
Siegfried O. Wofl, direktur riset South Asia Democratic Forum (SADF), dalam wawancaranya dengan Deutsche Welle (2015) menjelaskan, dalam kondisi hubungan antar agama yang sangat kompleks di Myanmar, sebenarnya ada aspek ekonomi dan politik yang menyebabkan konflik ini bukanlah hanya merupakan konflik berbasis agama.
Meskipun disebut-sebut memiliki banyak kekayaan alam, Rakhine merupakan salah satu wilayah termiskin yang ada di Myanmar. Ditambah dengan adanya perselisihan politik yang sebelumnya ada (dimana etnis Rohingya tidak mendukung partai politik setempat), hal ini menambah buruk sentimen masyarakat Rakhine terhadap etnis Rohingya, dengan menganggap mereka sebagai beban ekonomi negara yang telah mengambil banyak lapangan pekerjaan dan lahan berbisnis.
Senada dengan Wolf, Saskia Sassen (2017), seorang profesor sosiologi dari Columbia University menjelaskan, ada fakta penting yang ia temukan dari risetnya yang sering kali luput dari perhatian media tentang konflik Rohingya. Hasil risetnya menunjukkan bahwa, dalam dua dekade terakhir, akusisi perusahan terhadap pertambangan, kayu, agrikultur, dan air sedang meningkat pesat di seluruh dunia. Dalam kasus Myanmar, militer telah dikerahkan untuk melakukan perampasan tanah dari para petani Budha dan Rohingya sejak tahun 1990an yang menyebabkan banyak dari mereka terusir dari tempat tinggalnya.
Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan alokasi tanah untuk proyek besar yang mencapai 170% pada tahun 2012, (tahun terjadinya kericuhan berdarah di Rakhine), serta kelipatan dari hanya 7,000 hektar di tahun 2012, menjadi 1,268,077 hektar saat ini. Meski faktanya masyarakat Budha Myanmar juga menjadi korban, sudut pandang persekusi etnis Rohingya akan berfungsi untuk dua hal sekaligus; cara untuk pembebasan lahan dan distorsi fokus dari kesalahan pemerintah ke ranah agama.
Poin kedua, Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi utama wisata Indonesia. Pernyataan ini dapat dikaitkan dengan terganggunya pendapatan wisata. Bayangkan jika ada satu juta orang mengelilingi kompleks Candi Borobudur dalam satu hari, jumlah tersebut sudah hampir menyamai satu pertiga dari total pengunjung pada tahun 2016 yang berjumlah 3,7 juta. Jika setiap satu orang membayar tiket masuk sama, mungkin itu masih menguntungkan. Tapi jika tidak, ini jelas akan mengganggu pendapatan pariwisata Candi borobudur yang mencapai lebih dari 96 miliar rupiah (Badan Pusat Statistik, 2015)
Poin ketiga, Candi Borobudur merupakan salah satu situs warisan sejarah. Selain masuk ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO, Candi Borobudur pun berada dibawah lindungan UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Kalau saja rencana aksi pengepungan kemarin tetap dilakukan mesti tanpa izin yang berwajib, sepertinya akan ada satu juta orang dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.5,000,000, karena sudah “…dengan sengaja mencegah, menghalang – halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.”
Sebagai penutup, sebagai masyarakat yang berpendidikan, ada baiknya jika diwaktu yang akan datang kita dapat melakukan assessment yang lebih jeli dan mendalam sebelum turut serta kedalam aksi apapun. Sangat disayangkan tentunya, jika niat baik kita untuk membantu sesama umat manusia malah dijadikan kekuatan politik bagi pihak-pihak tertentu yang mempunyai tujuan lain.
Akhirnya, tulisan ini hanyalah sebuah opini pribadi sekaligus analisis dangkal yang (mungkin) memiliki banyak ketidakakuratan.
“Rohingya” ditulis oleh:
Iqbal Dwiharianto
Sarjana Ilmu Politik yang tertarik pada dunia jurnalistik.