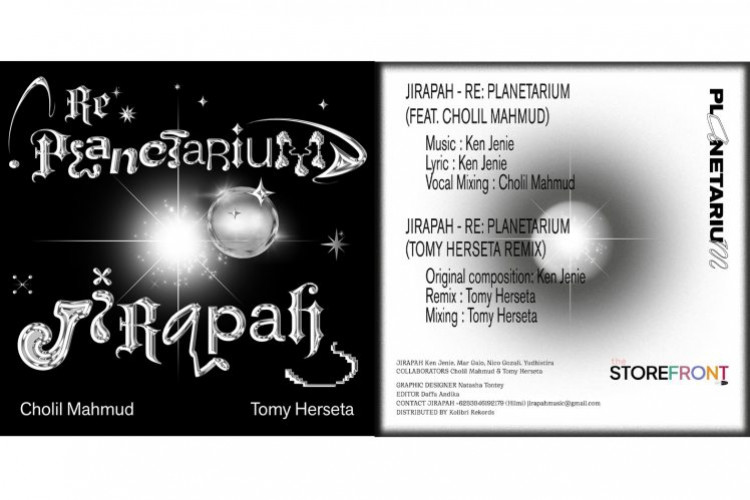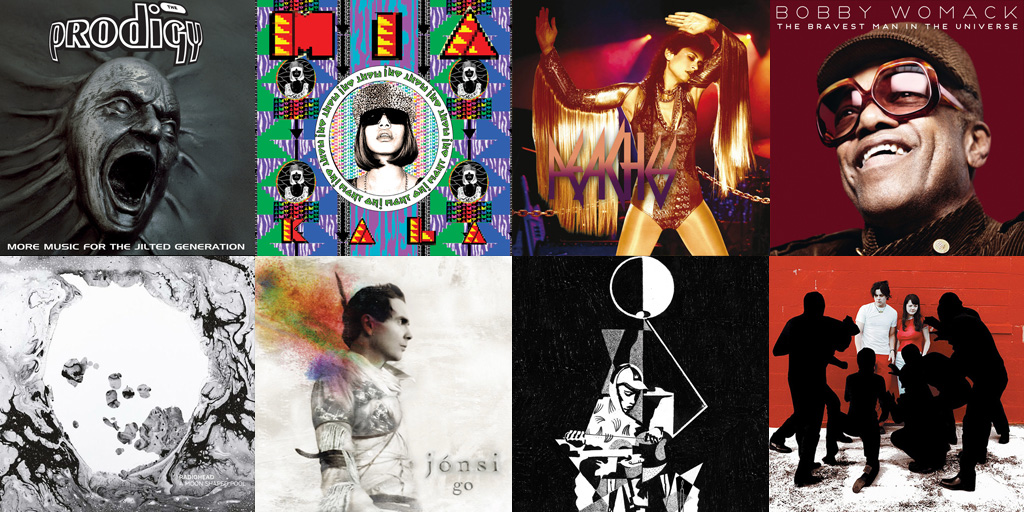
The Prodigy – Music for the Jilted Generation (1994)
Di antara embrio XL Recordings yang mengusung ragam dance, electronic, rave, atau techno, The Prodigy bisa dibilang memiliki karakter kuat dibanding lainnya. Mereka liar, tapi tak seliar T99. Mereka rumit, tapi tak serumit SL2. Mereka berdiri di tengah-tengah; memadukan idealisme berkarya dengan kebutuhan pasar. Soal musikalitas, jangan sangsikan. Ada nuansa beat gelap, harmoni aneh, namun memikat penuh candu. Simak bagaimana “Break & Enter” menyajikan kompleksitas ganjil yang tersusun dari mesin programming Liam Howlett. Atau saat Maxim Reality meluncurkan serangan beatboxing yang abstrak kepada Keith Flint di nomor “Skylined”. Percayalah, album ini merupakan capaian berharga dibanding The Fat of Land yang membuahkan kesuksesan komersial hingga prestasi membanggakan di panggung Grammy.
M.I.A – Kala (2007)
Jika Arular adalah pijakan pertama, maka Kala merupakan langkah yang memberi keistimewaan untuk duduk di atas kursi penahbisan. Kejeniusannya terpampang jelas ketika ia meracik bumbu yang terdiri dari aroma world music khas Sri Lanka, desahan avant-pop milik Madonna, maupun ketukan hip-hop tak tertebak. Rasanya menyenangkan tatkala mendengar dirinya menumpahkan kata-kata lewat “Bamboo Banga”, “BirdFlu”, sampai “Boyz” yang memaksa urat saraf melepaskan jeratan untuk sekadar berdansa bebas. Mathangi Arulpragasam memenuhi albumnya dengan retrospeksi terhadap Asia yang sering diremehkan hingga kemudian tiba masa di mana Rolling Stone dan TIME mengakui kualitasnya.
Peaches – I Feel Cream (2009)
Sebelum dunia mengenal Lady Gaga sebagai persona yang eksentrik, mereka tidak paham bahwa Merril Beth Nisker—atau biasa dipanggil Peaches—sudah meniti jalan serupa sedari lama. Selain tampilan yang kerap mengundang tanda tanya, ia juga berani memasukkan tema seksualitas ke dalam liriknya tanpa tedeng aling-aling. Dua albumnya bersama XL sempat meredup jika tak ingin disebut hancur kapasitas. Namun XL masih bisa bersabar dan memberi kesempatan terakhir padanya. Alhasil, ia tak menyia-nyiakan barang sedikitpun; memacu pedal lantas menghasilkan album yang sarat cerita pribadinya. Terkadang ia menyumpah serapah tapi tak menolak jatuh ke lubang melankolia. Terpenting, kontur electro-punk yang bernas jadi santapan utama.
Bobby Womack – The Bravest Man in the Universe (2012)
Legenda ini berupaya memberikan perpisahan elegan sebelum kepergiannya. Sebuah album penutup yang kental akan pencarian, perenungan, serta penyesalan terhadap memori masa silam. Layaknya jiwa youngster California, ia membantah pengasingan usia serta tenggat kematian yang datang tiba-tiba. Bagi Bobby Womack, tak ada yang lebih nikmat dibanding menyelami lautan terakhir dengan bernyanyi dan terus bernyanyi. Vokalnya masih tebal juga sensual meski di beberapa part terkesan rapuh. Mengajak Lana Del Rey merenungi “Dayglo Reflection” atau menumpahkan narasi teatrikal dengan petikan gitar kasar di “Deep River” tanpa cela ia lakukan. Walaupun energinya tak lagi meletup seperti saat menemani tur Ray Charles maupun kala membuat “Lookin’ for A Gospel” yang megah di tahun 1975, sebelas komposisi rasanya cukup merefleksikan kehebatan sosoknya.
Radiohead – A Moon Shaped Pool (2016)
Tak ada yang pernah meragukan status Radiohead dalam percaturan musik jagat raya. Semenjak Pablo Honey muncul di khalayak ramai, dunia seperti mendapati wahyu yang ditunggu. Menetapkan standar artistik tinggi, mengusung tata konseptual yang rapat, serta merumuskan konjugasi rumit adalah contoh keunggulan mereka. Bagaimanapun juga, fluktuasi kualitas pernah terjadi seiring bergulirnya momentum. Dengan keterpakuan pada kompleksitas krautrock yang dilahirkan dedengkot macam Can sampai Popol Vuh, Radiohead – entah mengapa – terjerumus dalam pusaran tersebut. Ekspektasi ingin meniru, tapi justru berujung keliru. Untuk para fanboy Thom Yorke garis keras seharusnya paham cetak sejarah ini dan mengerti bahwa memaafkannya merupakan keputusan berat. Namun degradasi tersebut sudah berlalu. Lewat A Moon Shaped Pool, Radiohead menjawab selentingan pertanyaan mengapa mereka kehilangan arah. Dan ungkapan syukur wajib dilayangkan saat menyaksikan Yorke tak nampak depresi serta Greenwood kembali nalar lagi.
Jonsi – Go (2010)
Sama seperti Thom Yorke, Jonsi adalah keajaiban. Kejeniusannya berada di atas rata-rata yang memungkinkan lahirnya karya-karya indah lagi menakjubkan. Figurnya yang hemat bicara tidak berbanding lurus dengan isi pikiran yang tersusun dari ribuan ide. Sadar bahwa Sigur Ros mengalami fase stagnansi setelah keluarnya Takk (2005) dan Með suð í eyrum við spilum endalaust (2008), ia mengambil langkah bijak; merealisasikan proyek solo yang entah sudah tersimpan sejak lama. Keputusannya berbuah manis. Go—tajuk album debutnya—memberikan pelangi lain yang tertutup keniscayaan. Senyawa post-Icelandic masih tergambar, tapi tak mendominasi letupan penuh kreasi. Jonsi menghadirkan sosok aslinya yang merangkul banyak warna; bassoon, brass, celeste, clarinet, glockenspiel, ukulele, trombone, sampler, hingga kemegahan choir. Layaknya konduktor, ia memimpin pasukannya untuk membebaskan melodi-melodi yang dibuahi arus orkestrasi. Dan kelak kita akan mengucap syukur karena pernah menikmatinya.
King Krule – 6 Feet Beneath the Moon (2013)
Pemuda berusia 22 tahun dengan tampilan yang lebih mirip begundal turunan Sid Vicious daripada seorang hot-item skena London ini telah membuat terobosan lintas genre mengagumkan. Berbekal perkakas seadanya mulai dari mesin laptop, gitar Fender bekas yang dibeli lewat penadah pasar, sampai kamar pribadi yang pengap akan minimnya sirkulasi udara, Archy Marshall—atau biasa dikenal sebagai King Krule—kembali menyajikan album eksepsional. Secara yakin ia menggabungkan petikan melodramatic yang bernotasi jazz bersama groove berat, intonasi padat, serta ketukan hip-hop yang cenderung mengarah ke darkwave tanpa harapan. Menyumpah serapah tentang rutinitas yang membosankan maupun mengambil respon ketika diremehkan adalah sepasang contoh terkini bagaimana 6 Feet Beneath the Moon berbicara. Apabila A New Place 2 Drown (2015) terdengar ambisius, maka lewat selentingan terbarunya King Krule mencoba untuk larut dalam peliknya jati diri.
The White Stripes – White Blood Cells (2001)
Mengenal Jack White berarti mengetahui seberapa tinggi taraf kegilaannya yang terkadang sulit terkejar nalar sekaligus melampaui batas-batas yang kiranya muskil ditaklukan. Bagaimanapun juga ia adalah sosok musisi yang besar. Baginya, setiap karya merupakan wujud pembuktian yang cepat maupun lambat bakal dikenang; atau justru dilupakan. Dan berbicara soal kreasinya, White Blood Cells bisa disebut sebagai titik monumental yang berpengaruh signifikan. Dibuat semasa meniti petualangan The White Stripes, Jack menciptakan taman bermain lapang yang nantinya dipenuhi oleh sihir rock-garage revival. Bersama Meg White, ia menyusun bangunan minimalis; mengecilkan porsi blues, menihilkan solo gitar panjang, menguatkan distorsi rock and roll, dan yang terpenting menikmati kesempatan sebelum predikat mahabintang disematkan. Album ini mungkin tak sepenting Elephant yang menggondol apresiasi atau Lazaretto yang dirilis pasca perpisahan. Tapi kita paham jika tanpa White Blood Cells, mereka akan biasa saja.