Seni Kontemporer bersama Alia Swastika
Muhammad Hilmi (H) berbincang dengan kurator Alia Swastika (A).
by Ken Jenie












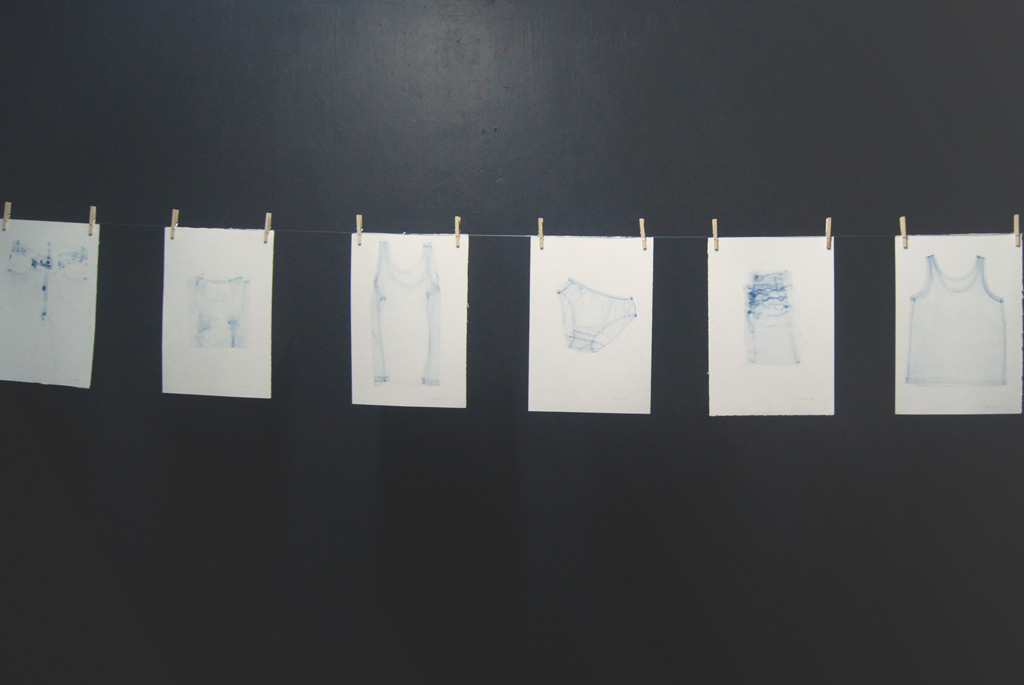





H
Setelah lulus dari Ilmu Komunikasi UGM, apa yang membuat Anda memutuskan untuk terjun di dunia seni rupa?
A
Saya bersekolah di SMA 3 Jogja, kebetulan lokasinya berdekatan dengan Bentara Budaya. Saya bukan tipe murid yang betah di kelas, jadi kalau ada kesempatan saya sering bolos ke perpustakaan atau ke Bentara Budaya tadi. Jadi sejak SMA saya telah ter-eksposure kegiatan-kegiatan seni rupa, termasuk mulai menghapal nama-nama seniman, sekaligus mengikuti perkembangannya. Meskipun memang pemahaman saya akan seni rupa belum sama sekali mendalam, masih sebatas tahu saja. Ketika kuliah, saya masuk di lembaga pers mahasiswa. Sejak saat itulah saya mulai tertarik untuk melakukan peliputan pada acara-acara kesenian.
H
Jadi setelah kuliah Anda langsung bergabung dengan Yayasan Seni Cemeti?
A
Setelah lulus, saya sempat menjadi editor untuk newsletter terbitan Yayasan Seni Cemeti, yang nantinya akan berubah nama menjadi IVAA (Indonesian Visual Art Archive). Setelah bekerja disana selama dua tahun, Cemeti Arthouse membuka lowongan kerja sebagai manajer artistik. Saat itu, saya belum paham seperti apa cakupan kerja manajer artistik. Setelah terjun bekerja di posisi tersebut, saya akhirnya mulai mempelajari benar-benar tentang kesenian, hingga definisi profesi kurator. Sebuah kondisi yang jelas berbeda dengan kondisi sekarang dimana anak-anak muda telah memahami konsep-konsep kurasi di usia belia. Yang saya alami, saat itu konsep kurator sendiri masih cukup abstrak, belum ada definisi pastinya. Saya akhirnya menemukan sendiri definisi kurator melalui pengalaman bekerja saya tersebut.
H
Apakah memang saat itu kurator sebagai profesi memang belum established di dunia seni Indonesia?
A
Sebenarnya mulai ada, dengan nama-nama seperti Jim Supangkat, Asmujo, Risky Jaelani, dan Mieke Susanto yang menginisiasi konsep kurasi di Indonesia. Akan tetapi ketika itu, institusi seni yang ada belum berkembang seperti sekarang, belum banyak juga pameran seni berskala besar yang terjadi disini. Kalaupun ada, maksimal hanya terjadi dua kali dalam setahun. Ada beberapa galeri seni, namun karena belum ada market seni di scene lokal, maka esensi seorang kurator masih kabur. Kurator masih dimaknai sebagai kegiatan iseng yang baru dilakukan ketika seorang teman seniman membutuhkan tulisan untuk pamerannya.
Kinerja Hendro Wiyanto di Biennale Jogja pada tahun 2003 lah yang menginspirasi saya untuk mempelajari lebih lanjut tentang kurasi. Dari situ saya mulai memahami sekaligus terinspirasi bahwa seorang kurator bisa menjadi sosok yang bisa merealisasikan sebuah wacana menjadi suatu hal yang juga berdampak besar kepada masyarakat.
H
Dengan field kurator yang sudah semakin established, apakah ada karakter khusus yang membedakan kurator era dulu dan sekarang?
A
Saya tidak yakin bisa memberi garis pemisah antara karakter kurator lama dengan kurator baru. Mungkin cara belajar mereka yang akan membedakan. Dulu masih cukup susah untuk mempelajari bidang ini. Sekarang, sudah cukup sering diadakan workshop kurator muda, karena semua institusi sudah sadar akan esensinya. Bahkan di titik tertentu, term kurasi sudah mulai agak overused. Dulu seseorang diharuskan untuk mempelajari konsep kurator melalui obrolan dengan para seniman. Saya sendiri sebagai produk dari pembelajaran kurator era lama merasa bahwa saya tidak memiliki kecakapan teori seni yang kuat, dan hal ini mengharuskan saya untuk lebih intens dalam berinteraksi dengan seniman. Akan tetapi, saya selalu menikmati untuk ikut bersama seniman saat proses mereka berkarya. Dari situ saya juga bisa mempelajari berbagai hal, termasuk mengenai teknik-teknik berkarya. Semacam mengejar ketertinggalan pemahaman untuk hal-hal yang memang berada di luar kompetensi saya saat itu. Saya sendiri kurang sepakat dengan mitos lama tentang kurator dengan background non-kesenian yang dianggap kurang secara kualitas dibandingkan dengan kurator yang memang berasal dari disiplin seni. Banyak sekali kurator kelas dunia yang berasal dari lintas disiplin ilmu.
H
Apakah background disiplin ilmu tadi akan menjadi karakter tersendiri bagi setiap kurator?
A
Saya pribadi merasa bahwa background keilmuan seseorang akan sangat mempengaruhi mereka dalam melakukan praktik kurasi. Ada cara pandang yang cukup berbeda dari setiap disiplin ilmu untuk melihat suatu teori.
Sebagai kurator yang mempelajari ilmu sosial, saya cenderung melakukan proses kurasi saya dengan menerjemahkan fenomena, bukan memberi penjelasan estetik. Saya melihat kurator dari disiplin seni cenderung menggunakan teori-teori tertentu untuk memberi bingkai pada pameran yang mereka kerjakan. Singkatnya keduanya memiliki proses berpikir yang berbeda.
H
Apakah sampai sekarang Alia Swastika masih intens berhubungan dengan seniman dalam proses kuratorial?
A
Sering, kesibukan menjadi musuh besar bagi kurator. Dengan kesibukan yang memaksa saya berurusan dengan berbagai urusan administratif, termasuk dalam mengurusi space dan biennale, waktu saya banyak tersita untuk menyelesaikan urusan paperworks. Tapi saya selalu berusaha untuk menyempatkan diri untuk mengunjungi seniman dalam proses berkaryanya. Saya kebetulan memiliki network teman-teman dari luar negeri yang senang datang ke Jogja dan jalan-jalan ke studio-studio seniman, jadi saya punya alibi untuk datang ke studio-studio dan dan mempelajari karya-karya seniman. Di luar segala kompleksitas pekerjaan kurator – menulis proposal, fundraising, dan lain-lain – yang paling saya nikmati memang berada di dalam proses penciptaan, bekerja bersama seniman. Karena itu menjadi prioritas saya, saya selalu perjuangkan. Kalau bisa setengah jam saja datang ke studio saya sudah senang.
H
Anda sempat lama di Jakarta saat bekerja untuk Ark Gallery, selain juga aktivitas berkesenian di Jogja. Apakah mbak Alia melihat perbedaan antara dua karakter kota yang bisa dibilang pusat budaya di Indonesa?
A
Jakarta dan Jogjakarta memang sangat berbeda. Saya sempat mengalami shock di awal pindah ke Jakarta. Ark Gallery lokasinya di Jakarta Selatan, tempat dimana anak gaul Jakarta berkumpul, jadi audiens kami memang sangat spesifik – orang-orang yang datang ke Goods Dept, yang nonton musik-musik tertentu, pergi ke Bengkel Nightclub. Kami harus mengakui bahwa itu adalah audiens utama kami. Di luar itu, saya merasa bahwa audiens di Jakarta itu lebih terbuka, jadi kalaupun ada hal yang aneh-aneh mereka akan berkata “this is cool.” Mereka langsung merasa bahwa mereka bisa relate dengan bentuk-bentuk baru yang eksperimental. Jadi kalau kita bikin pameran video atau karya konseptual mereka akan berkata “Wah, oke banget ya. Kok bisa ya senimannya berpikir seperti itu?” Kadang-kadang hal seperti itu yang tidak saya dapatkan di Jogja.
Di Jogja kadang-kadang audiensnya cenderung lebih tradisional. Hal ini tidak dalam artian bahwa mereka tertutup, tapi mungkin pergesekan mereka dengan budaya-budaya lain bisa dibilang tidak se intens Jakarta, karakter Jogja lebih homogen. Kadang-kadang kalau kita membuat karya yang eksperimental atau high-technology mereka akan bilang “Oh, ini kan hanya persoalan alat. Siapapun akan bisa membuat pameran semacam ini kalau punya alat-alatnya.” Komentar seperti ini tidak pernah terjadi di Jakarta. Tetapi, hal tersebut justru menantang kami untuk membuat program-program yang mengedukasi publik, seperti tentang bagaimana cara menikmati karya video, karya konseptual, karya eksperimental.
Saya merasa bahwa Jakarta lebih kosmopolitan, dan ini sangat membantu orang untuk bersikap terbuka kepada hal-hal yang asing. Di Jogja, orang-orang lebih kritis – hal-hal yang baru akan dipertanyakan dan dilawan dulu, dan setelah ada dibahas dalam dialog, baru akan di terima.
H
Kalau dari seniman-senimannya sendiri, apakah ada perbedaan karakter?
A
Sebenarnya, sewaktu saya di Ark Gallery Jakarta, situasi seni di ibukota tidak seperti sekarang. Jadi kita hanya beberapa kali menampilkan seniman dari Jakarta sendiri, dan setelah itu kita keburu pindah ke Jogja. Saat itu, hampir seluruh galeri dan ruang seni di Jakarta dikuasai Jogja dan Bandung. Baru belakangan ini setelah ada Exis(S)t dan program-program workshop seperti OK Video, seniman Jakarta terlihat secara individual – kalau dulu kan Jakarta lebih terlihat kolektif-kolektifnya.
H
Bagaimana Mbak Alia melihat posisi perempuan di dunia kesenian?
A
Kalau saya sendiri, saya merasa diuntungkan dengan posisi saya sebagai perempuan. Diuntungkan dalam artian ada prioritas-prioritas tertentu, seperti program-program yang mencari kurator perempuan, atau berkembangnya tren mengenai gender identity, jadi seniman perempuan dapat tempat lebih disitu. Tapi memang hal-hal tersebut merupakan keuntungan yang tantangannya tidak sedikit pula. Apalagi saya punya cara hidup yang sangat berbeda dengan kebanyakan perempuan. Saya single dan sangat menikmatinya, saya bisa kerja 24-jam, dan lain-lain. Keuntungannya memang ada tapi harga yang harus dibayar pun juga tidak murah. Kadang saya merasa bingung ketika bertemu dengan teman-teman sebaya yang sudah punya anak, aduh, ngomongin apa ya (tertawa).
Di saat yang sama, memang terasa bahwa dunia seni didominasi oleh laki-laki. Jadi kadang kita cenderung harus nurut dengan dengan dunianya – memang membutuhkan karakter yang unik dari seorang perempuan. Kalau menurut saya, seni adalah pekerjaan yang menarik. Saya bukan mau mengkarakterisasi perempuan dalam stereotype tertentu, tetapi jika kita sebagai perempuan mempunyai cara berkomunikasi yang cukup berbeda dengan laki-laki, hal seperti ini bisa sangat membantu dalam hubungan kita dengan seniman. Contohnya, jika seorang seniman sedang frustrasi, seorang perempuan mempunyai cara dengan bertanya kepada istrinya. Kalau laki-laki mungkin sungkan kalau masuk ke dalam wilayah pribadi, tapi perempuan punya flexibilitas dalam dimensi personal. Bagi saya, hidup profesional ini pada saat yang bersamaan adalah hidup personal saya.
H
Sebagai salah satu anggota biennale internasional, bagaimana Anda melihat posisi biennale di society yang semakin menghargai dunia seni ini?
A
Saya melihat adanya komunitas burgeosi baru yang pergi ke seluruh biennal di dunia – kadang-kadang saya berpikir, gila juga ya orang-orang ini selalu ada di setiap biennale (tertawa). Pada titik tertentu, saya sempat merasa ini fenomena yang sangat elite karena yang bisa mengakses acara seperti biennale hanya orang-orang tertentu – awalnya saya sempat sinis. Tetapi pada saat yang sama, saya merasa bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini penting untuk membuka mata kelas menengah itu. Kalau dulu, saat kelas menengah kita berlibur mereka naik kapal pesiar, pergi ke Yuniani, Spanyol, Italia – mereka hanya menikmati hidup. Sekarang saat mereka mengenal dan mengikuti perkembangan kesenian, mereka mengembangkan turis kesenian. Ternyata jumlahnya banyak, dan untuk saya seni juga penting untuk merubah mindset mereka.
Tadinya kelas menengah tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar dunia mereka. Kemarin membaca kritisisme terhadap snobbisme di Venice sangat menarik. Semua orang datang kesana seolah-olah mereka membaca masalah-masalah dunia, tetapi mereka memakai sepatu seharga 500 Euro, pakai tas Hermes, nginap di hotel mewah – jadi empatinya dimana? Ada kritisisme seperti itu. Menurut saya, dari beberapa orang yang saya kenal, orang kelas menengah yang di dunia seni cenderung merubah perilaku mereka. Kalau tadinya mereka menghambur-hamburkan uang, mereka sekarang merasa bersalah dan cenderung berhenti melakukan itu. Ini memang dunia elite, tetapi pada saat yang sama, pengalaman seperti ini untuk masyarakat dunia ketiga seperti Indonesia bisa memperdayakan kaum elite tersebut juga. Memang, perjalanannya masih panjang untuk titik dimana kaum elite mau merubah sistem sosial, atau menjadikan seni sebagai gerakan budaya. Tapi saya rasa kalau ini terus ditempuh, akan ada perubahan.
Saya merasakan sendiri, pengusaha yang banyak nonton kesenian, dia misalnya jadi lebih tidak tega untuk membayar buruh terlalu murah. Hal seperti ini disebabkan karena seni membahas isu-isu seperti itu, jadi kalau datang ke acara seni dan biennal-biennalnya, semua yang dibahas adalah masalah dunia. Jadi menurut saya, mulai ada perubahan nilai dari kalangan yang sering datang ke biennale-biennale ini.
Sebenarnya ada kritik juga bahwa biennale menjadi alasan untuk meng-gentrifikasi sebuah kota. Kota-kota yang tadinya tidak berkembang seperti Guang Zhou dan Brisbane, pemerintahannya mempunyai kepedulian terhadap seni dan kemudian mem-branding kotanya dengan cap biennale tertentu. Memang, gentrifikasi terjadi dengan cepat karena selalu ada gelombang turisme yang datang setelah adanya biennale. Mungkin di Barat, fenomena ini bisa dikapi dengan sinis karena hal gentrifikasi mempercepat arus kapitalisme yang hanya menguntungkan kaum elit. Tetapi di saat yang sama, bagi kota di negara seperti Indonesia, biennale adalah platform yang bagus untuk merayakan kehidupan. Pertama, kita merasa bersemangat menyelenggarakan sesuatu untuk banyak orang, merayakan dinamika kota kita, dan menunjukan pencapaian-pencapaian pemikiran budaya kita kepada dunia – ada harga diri kota kita disitu.
H
Salah satu garis besar di Biennale Jogja yang akan datang adalah menjalin hubungan dengan negara lain. Apakah ini bisa diinterpretasikan sebagai upaya go international. Dan seberapa penting sebenarnya go international untuk perkembangan kebudayaan di sebuah negara?
A
Saya meletakkannya dalam kerangka yang sama dengan mengapa kita selalu merasa ingin tim nasional kita bisa main di piala dunia, ini adalah impian banyak orang. Di kesenian, saya rasa juga ada semangat seperti itu – untuk menjadi bagian dari pemain kelas dunia. Entah apakah itu dalam kapasitas meneguhkan identitas, atau dalam rangka menunjukan pencapaian-pencapaian kita. Saya pikir, tren go international itu memang banyak dimotivasi oleh hal itu.
Kalau kenapa go international itu penting, dunia sekarang bergerak dengan sangat cepat, ada kompetisi di antara banyak pemain, dan kita harus ambil bagian di situ. Kalau tidak, pemikiran-pemikiran kita di anggap tidak ada, dan mungkin juga punah kalau tidak di hidupi bersama oleh masyarakatnya. Ketika kita punya prestrasi di lingkup internasional, dalam saat yang sama kita meneguhkan komunitas lokalnya, seperti mengundang untuk berpikir – “oh yang kita lakukan ini berharga loh, karena ada yang memandangkannya penting.” Contohnya Borobudur. Dengan UNESCO mengambil alih revitalisasi dan rekonstruksi Borobudur, perhatian dunia menjadi sangat besar, dan lalu membangkitkan kebanggan kita pada negara. Persentuhan kita dengan yang asing bisa membantu kita dalam peneguhan identitas kita sendiri.
Lalu, apakah Biennal Jogja dilihat dalam kerangka go internasional? Saya rasa tidak cuma seperti itu, meskipun itu adalah faktor yang penting, tapi kami juga harus meneguhkan posisi. Kita harus punya strategi – Apakah kita bisa memberi arti pada semua perjalanan kita itu? Saya juga merasa penting untuk membawa dunia melihat kepada kita, – apa yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam konteks biennale Jogja, yakni tentang apa yang terjadi di Jogja sendiri. Dan hal-hal seperti itu memang sangat mengubah banyak pandangan.
Selama mengerjakan dua edisi Jogja Biennale ini, saya merasa ketika orang datang, itu sangat berbeda dengan apa yang ditulis di media atau pandangan orang tentang Jogja. Tahun lalu kami kedatangan patron-patron dari Tate Museum, Mori Museum, dan tahun ini akan ada patron-patron dari Korea. Mereka datang karena mereka mendengar dari orang lain bahwa kehidupan seni di Jogja luar biasa, dinamis, dan menginspirasi, jadi mereka semua ingin datang. Saya rasa ini sesuatu yang positif, bahwa apa yang kita perjuangkan ada artinya, sampai orang-orang ingin meniru kita.
H
Sekarang dunia internasional melihat seni kontemporer di Indonesia. Apakah spotlight ini berdampak pada proses berkarya seniman-seniman disini?
A
Efeknya ada, tapi memang butuh satu jejaring kerja yang lebih besar untuk membawanya menjadi suatu kekuatan kolektif. Saya melihat yang paling maju itu infrastruktur Korea. Semua kelompok disana – swasta, pemerintah, seniman – semuanya ingin membangun infrastruktur seni di Korea. Kalau di Indonesia, sebagian besar di lakukan oleh masyarakat seni sendiri. Memang pemerintah memiliki program-program seni, tapi biasanya apa yang mereka kerjakan sangat berbeda dengan apa yang diperlukan di lapangan. Kita selama berpuluh-puluh tahun memperjuangkan sesuatu sendiri, mencari definisi seni dan perannya di masyarakat – itu semua kita lakukan sendiri tanpa bantuan pemerintah.
Kalau kita ingin maju di masa depan dan menjadi bagian dari masyarakat global, kita tidak bisa bekerja sendiri. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menggandeng pihak-pihak lain. Apa yang kita telah lakukan, dinamika seni kita selama puluhan tahun, itu mengaggumkan, tetapi untuk pergi ke luar negeri dan menunjukan seni Indonesia kepada dunia – itu masih belum cukup.
Ini bukan berarti kita harus mengemis kepada pemerintah. Kadang-kadang pemerintah mempunyai agenda sendiri, agenda yang mungkin sudah kehilangan relevansinya, sementara seniman ingin selalu yang relevan. Tapi untuk membuka obrolan dengan pemerintah itu juga harus selalu dicoba. Apalagi sekarang ada gelombang PNS-PNS baru yang rajin dan tidak lagi mencerminkan pegawai negeri seperti dauhulu.
H
Apa saja proyek Anda di masa yang akan datang?
A
Memang kalau sehari-harinya saya masih mengerjakan Biennale dan Ark Gallery. Proyek baru yang kami kembangkan adalah satu penerbitan/jurnal yang dikembangkan dan dikelola oleh peneliti-peniliti muda untuk menulis tulisan yang agak panjang mengenai sebuah fenomena. Sekarang ini, penulis dan kritikus muda tidak lagi memiliki media yang memungkinkan mereka menulis artikel dengan 3000 kata. Sementara di sisi lain, artikel-artikel 1000 kata sering terlalu pendek untuk menulis tentang fenomena secara lengkap. Jadi saya dan teman-teman membentuk SOUP, kepanjangannya Study on Art Practices. Kami meneliti berbagai fenomena sosial dalam seni dan konteks ekonomi-politik kesenian. Kedepannya, saya harap akan ada sinergi antara penelitian ini dan para seniman. Kadang-kadang seniman harus melakukan riset dari awal tentang ini dan itu, dan jika ada suatu lembaga yang bisa membantu mereka melakukan risetnya atau mempertajam gagasan-gagasannya, saya rasa akan sangat membantu seniman dalam proses berkaryanya.
H
Proyek ini hanya untuk di Jogja?
A
Bisa dimana-mana, tapi memang sejauh ini berbasis di Jogja karena teman-teman yang saya ajak berbasis di Jogja. Saya sedang memikirkan untuk mengumpulkan penulis-penulis dari kota-kota lain. Soalnya memang menulis minimal 4000 sampai 5000 kata sekarang ini cukup susah. Agak sulit untuk mencari orang yang energi seperti itu.
Sekarang ini, hampir semua tulisan seni sifatnya review. Jarang kita mendapatkan tulisan dengan perspektif tertentu. Kalau kita tidak segera memulai sekarang, kita akan ketinggalan. Ini soal latihan, dan latihan itu membutuhkan media. Saya merasa beruntung, saat saya memulai langkah saya dalam menjadi bagian dari masyarakat seni, masih ada rubric Bentara di Kompas. Kadang pula saya menulis di jurnal kebudayaan yang sekarang sudah tidak terbit lagi. Kalau sekarang, orang-orang palingan menulis di media kampusnya, atau di blog. Kalau tidak ada tulisan yang panjang, pembaca juga akan terbiasa dengan tulisan-tulisan yang pendek, saat membaca tulisan panjang, orang akan dengan mudah pecah konsentrasinya. Tapi bisa saja ini karena saya konvensional dan ketinggalan jaman. Bahwa bisa juga dengan membaca informasi-informasi pendek, orang lebih maju, dan cara membacanya lebih strategis.
H
Memang lucu, sekarang di artikel, teks menemani foto, dimana sebelumnya foto yang melengkapi teks.
A
Banyak yang berkata kepada saya bahwa saya orang aneh yang tidak mempunyai Instagram, padahal profesi saya adalah kurator yang membutuhkan konektivitas yang lebih dan harus selalu update. Pertimbangan pertama adalah karena saya merasa bahwa Instagram itu medium yang personal, dan di saat orang-orang membagikan hidup personal, saya berusaha untuk agak menguranginya. Bukan berarti saya tidak tertarik dengan budaya visualnya, tapi saya berpikir bahwa setiap media mempunyai efek masing-masing, dan saya ingin memilih efek yang menurut saya lebih indah. Meski saya tidak memiliki akun Instagram, tapi saya masih mengikuti Instagram-Instagram orang dengan akun lembaga (ketawa).
H
Ada poin lain yang Mbak Alia ingin tambahkan?
A
Saya ingin meluruskan satu hal. Saya rasa banyak orang merasa bahwa kehidupan seorang kurator itu penuh dengan glamor. Apalagi orang melihat saya pergi kesana-kesini, kadang-kadang di undang ke party oleh orang dari sana dan orang dari sini, dan berada dibagian jantung dunia kelas atas. Menurut saya itu hanya yang terlihat karena hanya itu yang diberitakan oleh media massa. Kalau teman-teman muda ingin menjadi seorang kurator, ada perjalanan panjang yang tidak terkover oleh cerita-cerita yang kita dengar. Misalnya tentang sesi pertemuan-pertemuan langsung dengan kurator dan seniman senior yang harus dilakukan demi berita-berita yang akurat. Kurator itu pekerjaaanmya teknis. Dari ngepel di saat-saat sebelum pameran sampai mencari uang supaya suatu projek bisa berlangsung – menjadi kurator tidak segampang atau seenak yang dibilang orang.
Klause Biesenbach adalah kurator dari PS1 di New York dan Instagramnya berisi foto-foto dia dengan Pharrel Williams, James Franco, Bjork. Melihat fenomena seperti ini, orang bisa saja berpikir bahwa menjadi kurator berarti seolah-olah mereka serta merta menjadi bagian dari selebritas. Menurut saya, hal tersebut harusnya dilihat sebagai hasil/efek dari kerja keras.
H
Kemarin kami sempat ngobrol dengan Reza Asung dan dia menyatakan sesuatu yang hampir senada, bahwa orang-orang cenderung berpikir bahwa hidup seniman seru karena jalan-jalan kesana-sini, padahal sebenarnya mereka bekerja.
A
Tapi sebenarnya kalau saya melihat seniman, saya kadang merasa iri tentang bagaimana seniman bisa memikirkan sebuah perspektif. Barangkali itu adalah salah satu hal yang membuat endurance saya di dunia seni begitu besar, karena saya selalu jatuh cinta terhadap bagaimana seniman berpikir – itu yang saya tidak banyak dapatkan di hal lain.
Saya juga senang terlibat di dalam proses. Kalau misalnya seorang seniman bekerja dengan petani, biasanya saya akan ikut dan pergi ke tempat petaninya, dan proses ini selalu mengajarkan saya dengan hal-hal baru. Ini satu-satunya profesi yang membuat saya benar-benar kaya. Misalnya satu seniman sedang membahas tentang tubuh, seniman lainnya membahas pertambangan, saya juga diharuskan untuk mempelajari bidang tersebut, dan mau ngga mau saya harus ikut turun ke lapangan. Menurut saya, ini kemewahan yang luar biasa, tidak banyak profesi yang menantang pelakunya untuk menjadi bagian dari kompleksitas hidup. Dan cara seorang seniman berpikir kadang-kadang kita tidak akan kita temukan di tempat-tempat lain – baik ilmuwan, jurnalis, apalagi politikus – seniman selalu punya tiga langkah kedepan untuk merefleksikan suatu fenomena. Setiap kali saya capek dan putus asa, saya bertemu dengan seniman, dan saya merasa wah, sialan, dia saja bisa berpikir sejauh itu, kenapa saya harus berhenti? Mungkin dibandingkan dengan kurator lain saya terlalu romantis. Bagi saya, pekerjaan ini cinta, dan saya tidak bisa menghindarinya. Memang bagi saya pada akhirnya, apa yang saya cintai dan perjuangkan dalam hidup itu ada di dalam kesenian.
—











